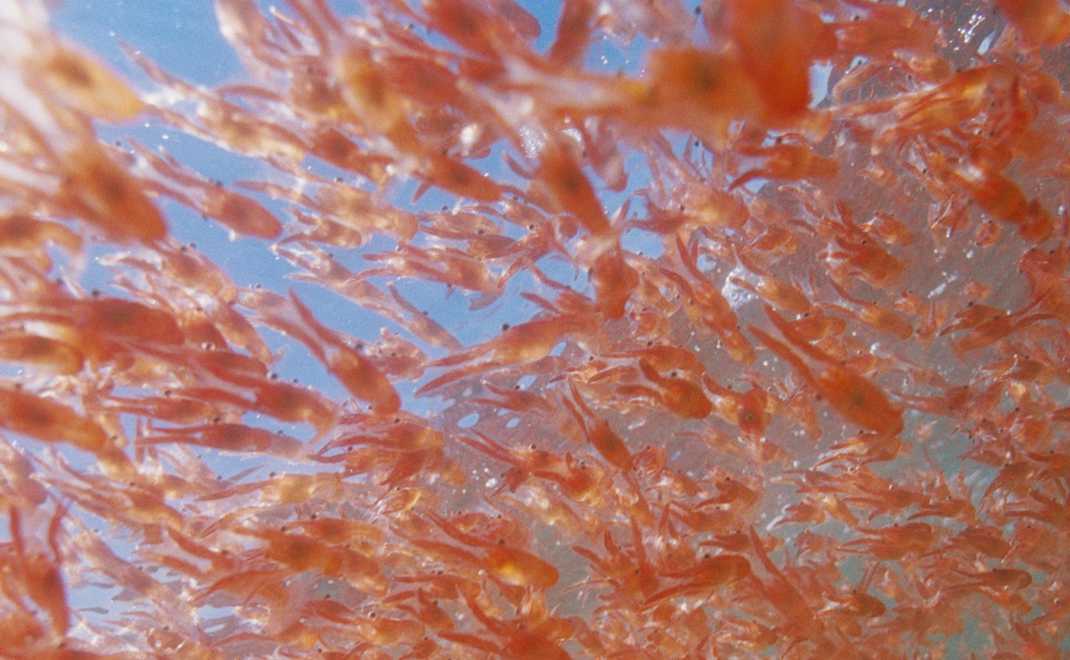SEBAGAI program reforma agraria, perhutanan sosial sudah berjalan selama tujuh tahun—jika kita mulai melihatnya sejak Presiden Joko Widodo mencanangkannya sebagai program nasional. Jika melihatnya sebagai praktik, perhutanan sosial sudah ada jauh sebelumnya, bahkan mulai dicetuskan sejak Kongres Kehutanan Sedunia di Jakarta pada 1978.
Apa yang berubah dan bagaimana perkembangan perhutanan sosial selama hampir satu dekade itu?
Reforma agraria merupakan amanat UUD 1945 melalui pasal 33 ayat 3 bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.” Dalam program Nawa Cita, reforma agraria merupakan program prioritas pemerintah yang akan membangun dari pinggiran wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
Reforma agraria adalah alokasi dan konsolidasi kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan lahan, baik tanah di hutan ataupun di desa. Di dalamnya ada dua hal yang diperhatikan pemerintah, yakni tanah objek reforma agraria (TORA) dan perhutanan sosial (PS). Dalam praktiknya, lahan yang termasuk dalam TORA dan PS akan dibuat per klaster dan dikelola oleh kelompok masyarakat terutama untuk diberdayakan di bidang pangan.
Beda keduanya terletak pada hak pemanfaatannya. Jika lahan TORA bisa dipakai sebagai hak milik atas tanah, lahan perhutanan sosial hanya hak akses, izin, atau kemitraan pengelolaan hutan. Untuk lahan TORA, sertifikat hak milik lahan akan dibuat untuk tidak bisa dijual dan tidak bisa dipecah melalui sistem waris.
Sedangkan lahan perhutanan sosial tidak boleh merusak ekosistem hutan dan penebangan kayu hanya dibolehkan di hutan produksi.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai pihak yang menyediakan lahan dari kawasan hutan, dalam meredistribusikan lahan punya kesempatan menata dan memvalidasi data luas hutan sesuai peruntukkannya. Di sini perlu hati-hati untuk menghindari tumpang-tindih peruntukan termasuk pemutihan lahan bermasalah. Keterbukaan data juga penting untuk menghindari penyesatan tidak perlu.
Misalnya, TORA yang berasal dari penguasaan tanah masyarakat di kawasan hutan sesungguhnya merupakan pemutihan secara de jure saja. Secara de facto, kawasan hutan itu mungkin sudah bertahun tahun menjadi lahan permukiman, lokasi transmigrasi, atau perkebunan.
Untuk perhutanan sosial, untuk lima tahun pertama (2014-2019), pemerintah menyediakan lahan hutan 10% dari luas hutan yang ada di Indonesia atau 12,7 juta hektare. Hingga 2019, baru 6.411 izin perhutanan seluas 4,04 juta hektare untuk 818.457 kepala keluarga yang terealisasi.
Kita bisa paham mengapa capaiannya seret.
Perhutanan sosial merupakan program yang implementasinya rumit dengan kompleksitas tinggi. Setidaknya ada tiga pilar jika perhutanan sosial ingin mencapai target seluas itu: masyarakat di dalam dan sekitar hutan yang mau dan mampu membentuk kelompok tani, b) kesiapan, kemampuan, dan ketrampilan penyuluh kehutanan serta pendamping petani hutan sosial, dan c) kesiapan, kemauan, dan kemampuan pemerintah memfasilitasi (perizinan, permodalan, pemasaran).
UU Cipta Kerja mengangkat perhutanan sosial ke dalam konstitusi. Dampak yang segera adalah hutan untuk perhutanan sosial bertambah sekitar 1 juta hektare, terutama di Jawa. Sebab menurut Peraturan Pemerintah 23/2021, hutan seluas itu akan diambil dari 2,4 juta hektare areal Perhutani menjadi Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK).
Selama lima tahun sejak 2014, dukungan regulasi perhutanan sosial bisa dikatakan minim. Secara kontekstual, tersirat melalui PP 6/ 2007. Pasal 83 dan 84 menyebut bahwa untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil, dilakukan pemberdayaan masyarakat setempat, melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat setempat dapat dilakukan melalui : a) hutan desa; b) hutan kemasyarakatan; atau c) kemitraan. Hutan adat dan hutan tanaman rakyat tidak masuk dalam skema pemberdayaan masyarakat ini.
Basis aturan perhutanan sosial kemudian muncul dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.83/2016 untuk mengatur dan mengontrol perhutanan sosial melalui lima skema: Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Kemitraan Kehutanan (KK), Hutan Adat (HA) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR).
Salah satu masalah krusial perhutanan sosial adalah perizinan dan administrasi yang panjang dan berbelit belit untuk ukuran kelompok tani hutan (KTH). Dari persiapan, pengajuan, hingga pemberian izin memerlukan pendampingan karena syarat clean dan clear untuk mendapatkan izinnya.
Masalah lain adalah kesalahan menetapkan target perhutanan sosial berdasarkan luas. Praktiknya, penyuluhan dilakukan kepada kelompok tani yang mengelola usaha perhutanan sosial. Semestinya ukuran keberhasilan perhutanan sosial secara kuantitatif adalah jumlah kelompok tani yang terlibat.
Target jumlah kelompok yang akan dibentuk selama 2014-2019 sebanyak 5.000. Realisasinya adalah 6.411 izin atau 128% dari target.
Setelah pembentukan kelompok, KUPS terbagi ke dalam empat kelas: “gold”, jika kegiatan pendampingan telah berhasil dalam pembinaan pada aspek kelembagaan, kawasan dan usaha. “Silver”, jika kegiatan pendampingan baru berhasil dalam pembinaan pada aspek kelembagaan dan kawasan dan “Blue”, bila kegiatan pendampingan telah berhasil dalam pembinaan pada aspek kelembagaan. “Platinum” jika KUPS tersebut telah memiliki pasar yang luas baik nasional maupun internasional.
Hasil penilaian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan pada 5.208 KUPS, baru 48 atau 0,92% yang mandiri atau platinum. Sisanya, 433 (8,31%) ada di tahap maju (emas/gold), 1.286 (24,69%) di tahap moderat (silver/perak), dan yang terbanyak 3.441 (66,07%) masih di tahap awal (biru).
Untuk menilai kualitas KUPS proses dan waktu. Dari indikator capaian pendampingan, proses naik kelas dari sisi kelembagaan membutuhkan waktu minimal dua tahun. Demikian juga, dari kelola kelembagaan ke kelola usaha membutuhkan 2-5 tahun.
Kemampuan naik kelas usaha hutan sosial ini sangat tergantung pada pendamping. Salah satunya penyuluh kehutanan. Jumlah penyuluh kehutanan saat ini tidak lebih dari 3.500 orang, 300 orang di antaranya di bawah KLHK dan sisanya 3.200 orang kewenangan daerah.
Jika melihat jumlah kelompok tani dan luas hutan untuk perhutanan sosial setidaknya butuh 10.000 pendamping. Belum lagi jika bicara kualitas dan kapasitas pendamping di daerah akibat mandeknya pendidikan dan pelatihan.
Sementara distribusi penempatan tenaga penyuluh kehutanan tidak merata. Hampir 50% penyuluh kehutanan banyak bertugas di pulau Jawa, sementara 50% menyebar dalam 29 provinsi lain.
Maka, meski perhutanan sosial naik kelas ke dalam UU Cipta Kerja, perhutanan sosial masih menghadapi banyak problem lain yang sama pentingnya setelah regulasi. Justru problem ini yang menunjang keberhasilan program ini sebagai kebijakan pengelolaan hutan lestari bersama masyarakat.
BERSAMA MELESTARIKAN BUMI
Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.
Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.
Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.

Pernah bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Topik :