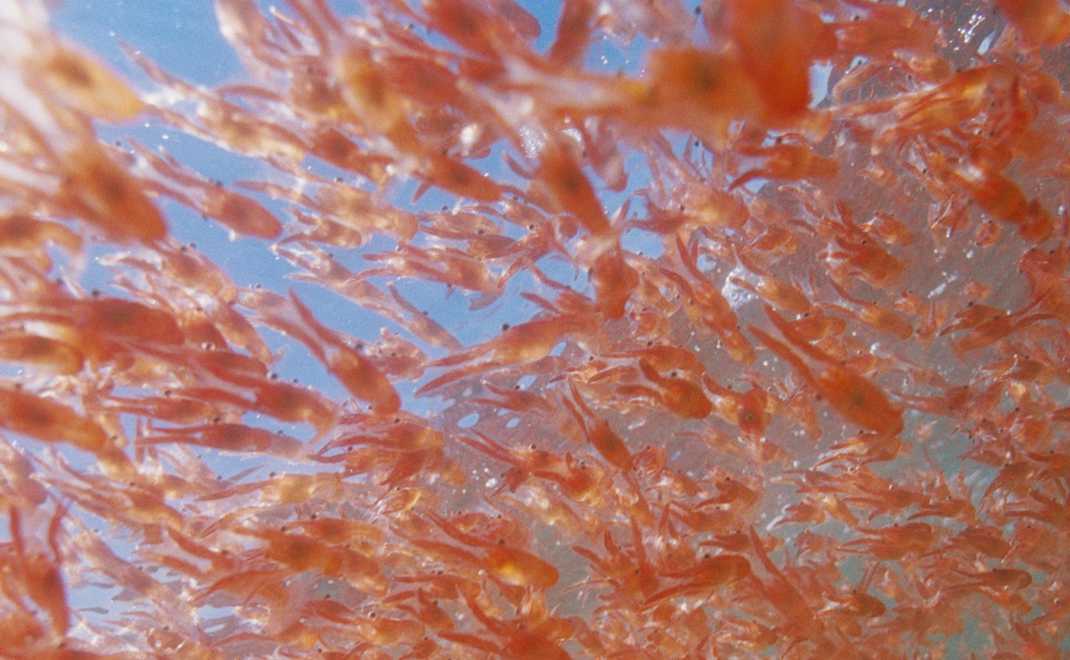KITA sudah tahu bahwa Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dibuat untuk melancarkan investasi melalui perizinan berusaha. Karena dampaknya akan berpengaruh pada lingkungan hidup, kita semua harus menerapkan prinsip kehati-hatian.
Menerapkan prinsip kehati-hatian berarti menjalankan pasal-pasal UU Cipta Kerja dengan tidak menurunkan standar lingkungan hidup maupun keadilan pemanfaatan sumber daya alam. Masalahnya ada keraguan atas harapan itu akhir-akhir ini. Artikel ini membahas soal itu, terutama yang terkait dengan penggunaan kawasan hutan.
Pasal 90 dan 91, Peraturan Pemerintah Nomor 23/2021 tentang penyelenggaraan kehutanan mengatur bahwa kebijakan penggunaan kawasan hutan dijalankan untuk memberi kesempatan selain kegiatan kehutanan—terutama bagi kegiatan yang punya tujuan strategis dan tidak bisa dielakkan—untuk memanfaatkan kawasan hutan produksi dan hutan lindung, tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dan kelestarian lingkungannya.
Berpegang pada norma di kedua pasal itu, cukup jelas urgensi adanya kebijakan itu maupun batasan ataupun larangannya, agar dampak negatifnya dapat diminimalkan. Namun, dalam PP itu masih ada beberapa ketentuan yang berpotensi meningkatkan kerusakan lingkungan hidup.
Pertama, pada pasal 92 tentang larangan tambang terbuka di hutan lindung dikecualikan bagi kegiatan pertambangan telah melalui kajian dampak penurunan permukaan tanah, perubahan fungsi pokok kawasan hutan secara permanen, serta gangguan akuifer air tanah, dan ada upaya untuk mengurangi dampaknya.
Ketetapan itu berbeda dengan pasal 38 UU Kehutanan yang menyatakan bahwa pada kawasan hutan lindung pemegang izin dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. Artinya, ketentuan baru UU Cipta Kerja melonggarkan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) tadi.
Prinsip kehati-hatian mengelola lingkungan diadopsi secara global dan telah menjadi Prinsip 15 Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan yang disepakati oleh semua negara anggota PBB pada 1992. Isinya sebagai berikut:
Untuk melindungi lingkungan, pendekatan kehati-hatian harus diterapkan secara luas oleh negara-negara sesuai dengan kemampuannya. Jika ada ancaman kerusakan serius yang tidak bisa diubah, kurangnya kepastian ilmiah, kegiatan ekonomi tidak boleh dipakai sebagai alasan menunda langkah-langkah hemat biaya untuk mencegah degradasi lingkungan.
Rupert Read dan Tim O'Riordan dalam The Precautionary Principle Under Fire (2017) menulis bahwa tidak mungkin menunggu konfirmasi bahaya dan sumber bahaya, sementara kerusakan lingkungan di negara-negara tetangga secara gamblang sudah terjadi. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak atas suatu mekanisme yang tidak hanya mengikuti jalan metodologi ilmiah biasa.
Di sini kita memikirkan penghindaran dari hasil yang berpotensi serius yang tidak terduga. Reputasi ilmiah seseorang hanya momen kecil, dibandingkan dengan keterlibatannya dalam menghapus kemungkinan bahaya serius (yang tidak bisa pulih) yang bisa dihindari. Jika seseorang terlalu berpegang teguh pada kebiasaan ilmiah normal untuk menunggu bukti dan menghindari alarm palsu, dia mungkin terlibat dalam situasi di mana sesuatu yang benar-benar mengkhawatirkan dan mengerikan terjadi—tanpa ada yang memperingatkannya.
Saat ini, menurut Read dan O'Riordan, proses keberlanjutan secara umum semakin melemah karena berbagai bentuk tata kelola lingkungan sedang dirusak oleh perilaku koruptif, konflik kepentingan dan lemahnya kapasitas pengawasan oleh lembaga negara maupun semakin sempitnya partisipasi warga negara secara efektif. Ketika kita tidak mampu mengatasi pelemahan tersebut, landasan hukum dan aturan prinsip kehati-hatian yang diabaikan benar-benar bisa menjadi bumerang.
Kedua, pasal 94 menyebutkan untuk kegiatan pertambangan serta kegiatan untuk kepentingan umum yang pengadaan tanahnya dilakukan selain oleh instansi pemerintah dan digunakan secara tidak permanen, bisa dilakukan di provinsi dengan luas hutan melampaui kecukupannya ataupun kurang dari kecukupannya. Namun, apabila penggunaan kawasan hutan itu bersifat permanen, pemerintah bisa mengizinkannya melalui pelepasan kawasan hutan.
Pada pasal ini ditetapkan pula bahwa apabila kegiatan tersebut dilakukan di provinsi dengan luas kawasan hutan melampaui kecukupan, pengusaha harus membayar pendapatan negara bukan pajak (PNBP) penggunaan kawasan hutan.
Sedangkan bila kegiatan dilakukan di provinsi dengan luas hutan kurang cukup, selain membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan, pengusaha juga harus membayar PNBP Kompensasi serta melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai.
Bagaimana dengan kegiatan lain? Jika kegiatan itu termasuk program strategis nasional, pemulihan ekonomi nasional, ketahanan pangan (food estate) pemerintah membebaskannya dari kewajiban membayar PNBP.
PNBP Kompensasi adalah kebijakan baru. Dalam kebijakan lama, bila luas hutan di provinsi kurang dari kecukupannya, yaitu di seluruh pulau Jawa, Bali, dan Lampung—yang saat itu ditentukan seluas minimal 30% dari luas masing-masing wilayah—pemrakarsa harus memberi kompensasi berupa lahan pengganti, bukan PNBP. Di sini ada dua isu yang mesti kita cermati.
Setelah beberapa peraturan menteri turunan UU Cipta Kerja terbit, belum ada batasan operasional bagaimana menentukan kecukupan luas hutan tiap provinsi atau pulau karena pasal 30% luas hutan sudah dihapus. Semoga batasan operasional itu masih menetapkan pulau Jawa, Bali, dan Lampung sebagai wilayah dengan luas hutan kurang cukup agar bisa daerahnya terlindungi. Dalam kenyataannya provinsi-provinsi ini telah mengalami defisit air bersih dan air pertanian yang masih sangat diandalkan sebagai daerah sumber pangan.
Isu lain soal usulan nilai PNBP Kompensasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Menteri Keuangan sebesar Rp11,5 juta hingga Rp 15,5 juta per hektare, yang dibedakan menurut fungsi hutan dan rayon. Nilai itu dihitung atas dasar nilai pembangunan hutan.
Kegiatan pembangunan yang akan mengurangi kawasan hutan di daerah dengan luas hutan yang kurang, sesungguhnya tidak bisa diganti melalui nilai pembangunan hutan. Norma pengaturannya perlu dikembalikan ke pasal 90 dan 91 di atas, yakni tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dan kelestarian lingkungannya.
Bila diganti dengan PNBP, semestinya nilai kompensasinya seharga lahan pengganti, berupa hutan atau lahan yang bisa dihutankan kembali. PNBP harus dijamin hanya untuk mendapatkan lahan pengganti itu.
Skenario lain untuk wilayah-wilayah dengan luas hutan kurang dari kecukupannya, semestinya tidak lagi ada kebijakan penggunaan kawasan hutan secara permanen atau pelepasan kawasan hutan. Sebaiknya, daerah dengan kategori itu masuk daftar wilayah negatif investasi untuk kegiatan di luar kehutanan.
Ketiga, pasal 372 Peraturan Menteri LHK Nomor 7/2021 ada ketetapan bahwa kuota luas persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk tambang mineral dan batu bara maksimum 10% yang diterapkan di wilayah pulau-pulau kecil dan wilayah Perum Perhutani di Jawa, dalam kawasan hutan produksi dan hutan lindung.
Sayangnya ada 10 jenis kegiatan yang dikeluarkan dari perhitungan 10% tersebut, termasuk kegiatan operasi tambang yang disertai pembangunan smelter, operasi tambang perpanjangan periode ke dua, maupun kegiatan perkebunan.
Dari ketiga hal di atas sulit rasanya tidak mengatakan bahwa kebijakan itu melumpuhkan prinsip kehati-hatian. Ironinya, dalam suasana politik kontemporer yang “pro-pertumbuhan”, prinsip kehati-hatian memang telah menjadi sasaran pemusnahan secara agresif oleh mereka yang bertekad mencegah apa pun yang melemahkan “pasar bebas” (American Enterprise Institute, 2016).
Read dan O'Riordan menambahkan bahkan terdapat aliansi menarik antara sains dan ideologi perusahaan dalam serangan kontemporer terhadap upaya pelaksanaan prinsip kehati-hatian itu. Mereka berargumen, kecuali ada bukti kuat tentang bahaya, tindakan kehati-hatian hanya jadi penghalang tidak berguna dalam inovasi dan perolehan keuntungan.
Di sini penting kita merumuskan kembali ilmu keberlanjutan ke dalam kerangka kerja yang lebih berbasis etika, yang bisa membantu menghapus kecerobohan dan mengembalikan tindakan kehati-hatian ke tempat yang seharusnya. Karena versi kecerobohan dalam konteks teknologi dan pendekatan tertentu untuk permodelan bisa menyamar di bawah panji-panji ilmu pengetahuan itu sendiri.
Kita mungkin juga perlu memahami—seperti Socrates—jalan paling bijaksana adalah mengakui bahwa kita ternyata lebih bodoh daripada yang ingin kita percayai. Kita harus belajar untuk hidup dengan berbagai tingkat ketidaktahuan dan ketidakpastian, daripada menyembunyikan ambisi sombong seolah menguasai fenomena alam secara total.
Dengan cara hidup seperti itu prinsip kehati-hatian akan terancang untuk kita jalankan.
BERSAMA MELESTARIKAN BUMI
Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.
Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.
Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.

Guru Besar Kebijakan Kehutanan pada Fakultas Kehutanan dan Lingkungan serta fellow pada Center for Transdiciplinary and Sustainability Sciences, IPB.
Topik :