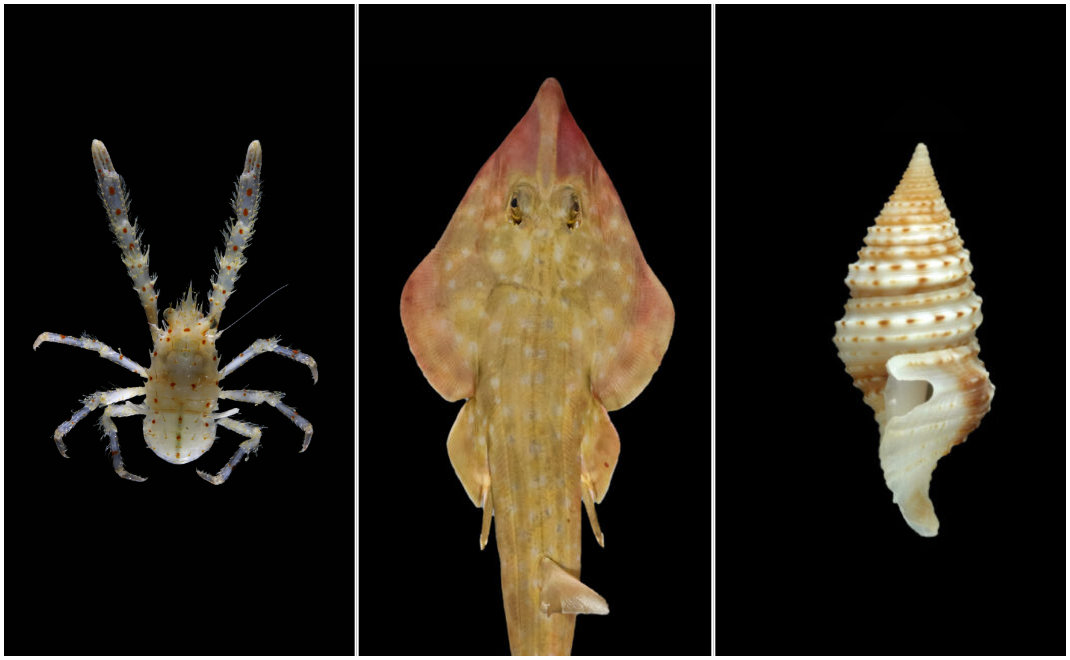KONFLIK masyarakat adat di sekitar Danau Toba Sumatera Utara dengan PT TPL atau PT Toba Pulp Lestari Tbk adalah konflik tenurial tipikal yang terjadi di hampir seluruh Indonesia. Sebelum Danau Toba, ada konflik masyarakat adat Laman Kinipan di Kalimantan Tengah dengan perusahaan kelapa sawit.
Konflik tenurial itu akibat pemberian izin bisnis untuk perusahaan di lahan-lahan masyarakat adat yang sudah menghuni wilayah tersebut jauh sebelumnya. Reforma agraria yang mandek membuat wilayah masyarakat adat tak mendapatkan legalitas sehingga pembagian izin pemanfaatan ruang kepada perusahaan oleh pemerintah memakai asumsi lahan kosong.
Konsesi PT TPL terbit pada 1992 melalui surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/Kpts-II/1992 seluas 269.060 hektare. Pada 2011, luasnya berkurang menjadi 188.055 hektare. Luas terakhir 167.912 hektare dengan merujuk pada keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 307/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2020.
Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), LSM yang mendampingi masyarakat adat Danau Toba, dari luas konsesi perusahaan hutan tanaman industri (HTI) penghasil bubur kertas itu, ada 20.754 hektare merupakan wilayah adat (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Tano Batak menyebut 25.000 hektare). Menurut Walhi, LSM lain, ada 11 komunitas masyarakat adat di lima kabupaten yang berada di konsesi tersebut.
Selama 30 tahun konflik itu tak kunjung usai. PT TPL mengklaim menyelesaikan konflik itu dengan membuat kemitraan dengan masyarakat adat. Namun, para pendamping masyarakat adat menolak klaim itu dengan menuding mereka yang diajak bermitra bukan berasal dari masyarakat adat di sekitar Danau Toba.
Saling klaim ini kian meruncing. Para pendamping masyarakat adat mendokumentasikan beberapa kali konflik fisik sejak September 2020. Puncaknya intimidasi masyarakat adat di Natumingka pada 18 Mei 2021.
Setelah kejadian itu, 11 orang perwakilan masyarakat adat memutuskan berjalan kaki dari Makam Sisingamangaraja XII—pahlawan Sumatera Utara—menuju kantor presiden di Jakarta sejauh 1.700 kilometer. Mereka meminta pemerintah menutup PT TPL.
Setelah berjalan kaki selama 44 hari, sebelas orang perwakilan ini tiba di Jakarta pada 27 Juli 2021. Namun, protokoler Istana Negara yang menghubungi wakil masyarakat adat pada 5 Aguatus 2021 hanya mengizinkan satu orang bertemu Presiden Joko Widodo. Dia adalah Togu Simorangkir. “Kami sudah muak dengan PT TPL,” katanya, tentang alasan jalan kaki ke Jakarta.
Kepada Jokowi, Togu memberikan dua dokumen, yakni “satu bundel dosa TPL selama 34 tahun dan satu bundel petis tutup TPL yang ditandatangani 18.000 orang melalui change.org”. Dalam pertemuan itu, Togu menyinggung ekosistem sekitar Danau Toba yang rusak oleh aktivitas perusahaan. Dua perusahaan besar perikanan di Danau Toba memakai jaring apung dan mengotori ekosistem danau.
“Saya tidak tahu itu,” kata Jokowi menanggapi laporan Togu.
Soal TPL Jokowi menduga bahwa perusahaan ini hanya menebang pinus. Menurut Togu, TPL tak hanya menebang pohon pinus tapi kayu hutan alam lalu menggantinya dengan eukaliptus. Wilayah sekitar Danau Toba merupakan rumah hutan kemenyan dan sebagai sumber air.
Jokowi rupanya sudah menyiapkan lima SK hutan adat. Menurut dia, 10 SK hutan adat lainnya masih dalam proses. Ia berjanji menyelesaikannya dalam sebulan. “Ada tim KLHK yang mengaudit TPL,” kata Jokowi. “Jika ada pelanggaran bisa ditutup.”
Tepatkah solusi Jokowi itu? Jika melihat data konflik tenurial masyarakat adat dan perusahaan, solusi permanen adalah menjalankan reforma agraria. Menurut catatan AMAN, sebanyak 80% wilayah masyarakat adat tertindih oleh konsesi perusahaan perkebunan dan kehutanan yang menyimpan konflik tenurial yang kompleks.
Selama ini, penyelesaian konflik ruang antara bisnis dan masyarakat adat diselesaikan memakai pasal 67 UU Kehutanan, yakni melegalkan wilayah adat melalui proses politik lewat peraturan daerah. Tanpa Perda, pemerintah pusat tak akan mengakui sebuah wilayah adat sehingga secara hukum selalu kalah oleh perusahaan pemilik konsesi di atasnya.
UU Cipta Kerja, yang telah diturunkan ke dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/2021, coba memutus kebuntuan itu dengan membolehkan kepala daerah memberikan izin prinsip kepada sebuah wilayah adat.
Tanpa harus mendapat persetujuan lembaga legislatif, kepala daerah bisa memberikan izin prinsip kepada masyarakat adat yang lulus verifikasi. Dengan izin prinsip, pemerintah tak bisa memberikan izin untuk keperluan lain.
Masalahnya, menurut peneliti masyarakat adat Yando Zakaria, izin prinsip hanya sebatas memberikan klaim wilayah adat. Sebelum pengakuan melalui Perda terbit, masyarakat adat tetap belum bisa membuat rencana dan memanfaatkan hutan adat mereka.
Padahal, seperti di Danau Toba, masyarakat adat memanfaatkan hutan kemenyan seraya memuliakan air untuk hidup mereka secara turun-temurun. Kehadiran PT TPL membuat kearifan lokal masyarakat adat menjaga hutan tersendat akibat konflik tenurial bertahun-tahun.
BERSAMA MELESTARIKAN BUMI
Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.
Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.
Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.

Alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University
Topik :