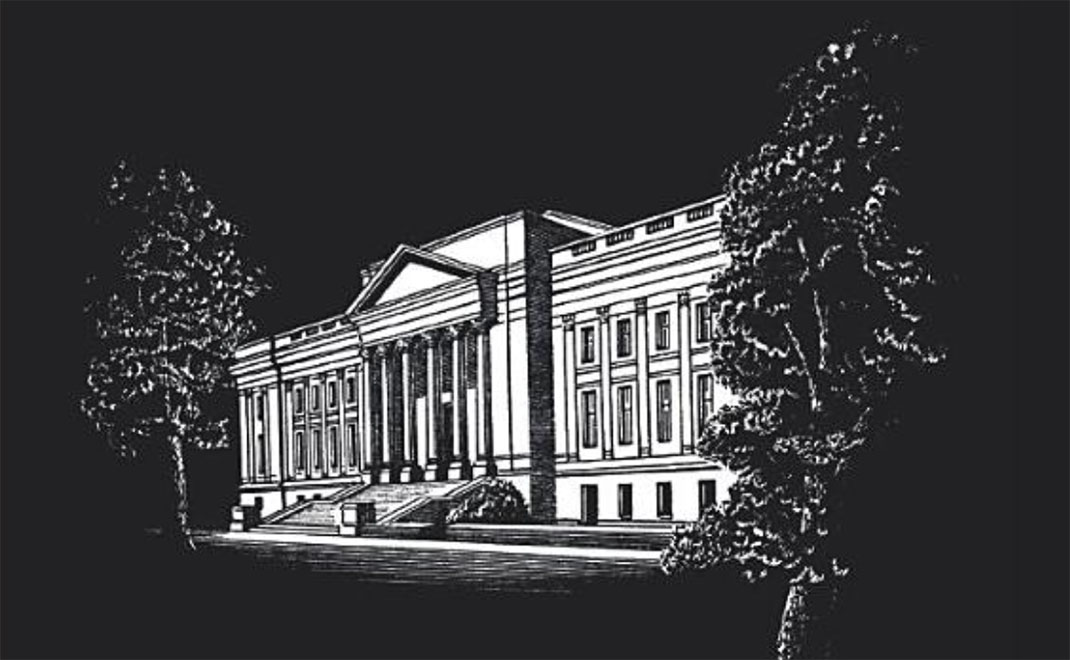
DI kalangan akademikus, buku ini sedang hangat jadi perbincangan. Terbit pada Mei 2021, Dark Academia mengungkap sisi gelap universitas yang ingkar dari tujuan perguruan tinggi, yakni tempat pertukaran ide, persemaian gagasan dan inovasi, serta pengabdian kepada masyarakat.
Peter Fleming, penulis Dark Academia: How Universities Die, memang menyoroti banyak kampus di Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, yang tak lagi mendukung kualitas akademik akibat terkurung sistem neoliberal yang kapitalistik sehingga universitas cenderung berorientasi bisnis. Apakah fenomena yang sama terjadi di Indonesia.
Dewan Guru Besar IPB University menggelar pembahasan buku ini secara online dengan mengundang sejumlah ahli. Antara lain Zulfan Tadjoeddin, dosen di Western Sydney University; Arya Hadi Dharmawan, guru besar Fakultas Ekologi Manusia IPB, dan Hariadi Kartodihardjo, guru besar kebijakan kehutanan IPB University.
Menurut Zulfan, kecenderungan universitas menjadi lebih komersial membuat mahasiswa didorong menjadi konsumen dan dosennya menjadi faktor produksi ekonomi. Zulfan bahkan mengatakan, apa yang terjadi Indonesia lebih dari apa yang diungkap Fleming dalam Dark Academia.
Kampus di Indonesia, kata Zulfan, belum memiliki fondasi yang kokoh sebagai kampus yang melahirkan tri dharma perguruan tinggi hingga keburu tergerus oleh arus neoliberalisme yang kapitalistik. “Saya merasakan, melihat, dan mengalami sendiri bagaimana itu terjadi,” kata dia.
Arya Hadi Dharmawan mengupas lebih detail sisi gelap kampus dari delapan fenomena yang ditulis Fleming:
- Elitis. Kampus menjadi elitis sehingga jauh dari masyarakat. Di Indonesia para peneliti dan dosen jauh dari memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menciptakan inovasi yang menyelesaikan problem-problem orang banyak. Masyarakat akan menggugat elitisme ini jika peneliti ingin selalu berada di posisi paling atas.
- Pabrik pengetahuan. Kampus menjadi semacam pabrik ilmu pengetahuan. Di Indonesia cirinya adalah kinerja akademisi diukur melalui indeks kinerja utama sehingga penelitian menjadi semacam produksi barang.
- Birokrasi kampus. Universitas terjebak pada umumnya organisasi, yakni pengelolaan secara birokratis. Alih-alih menjawab problem di masyarakat, para ilmuwan sibuk mengejar angkat kredit untuk memenuhi syarat-syarat birokrasi.
- Angka kredit. Capaian kinerja diukur melalui angka-angka yang wajib dipenuhi para dosen. Jumlah publikasi dan kepangkatan menjadi yang utama, bukan pada isi yang berguna bagi orang banyak.
- Homo academicus. Ada gejala kompleksitas gejala mental para dosen akibat kurang bergaul, kesepian, stres, dan kesehatan mental lainnya akibat fokus meneliti dan memenuhi birokrasi kampus. Di Indonesia gejala ini belum terlalu menonjol.
- Kontrol negara. Tak ada lagi kebebasan akademik karena negara terlalu turut campur dalam menentukan kebijakan-kebijakan akademis, hingga penentuan pejabat kampus. Kontrol lain melalui pengawasan akademik melalui angka-angka yang harus dipenuhi para dosen.
- Selebritas akademik. Ini semacam sindrom popularitas dosen yang berbentuk cara mereka mengasongkan diri dan pendapat dari forum ke forum. Di Indonesia, fenomenanya lebih parah karena mengasong itu sebagai cara mendapatkan penghasilan tambahan.
- Krisis keuangan mahasiswa. Di negara barat fenomena ini jamak karena untuk sekolah mahasiswa meminjam kredit ke bank akibat tuntutan pembayaran kampus yang besar. Di Indonesia, fenomena ini belum terlalu parah meski ada beberapa kejadian orang tua mahasiswa berutang banyak dan terjerat rentenir akibat tak mampu memenuhi uang pangkal atau SPP anaknya.
Dengan fenomena-fenomena itu, pendidikan tak lagi menjadi hak setiap orang. Perguruan tinggi menjadi organisasi atau lembaga bisnis yang membuat setiap orang tak bisa mencapainya dengan mudah. Ketimpangan pun, yang harusnya diselesaikan sektor pendidikan, justru terjadi di bidang ini. “Dengan sangat kuat buku ini mengkritik neoliberalisme perguruan tinggi, korporatisasi, dan elitisme kampus,” kata Arya.
Hariadi Kartodihardjo menilai apa yang diutarakan Fleming merupakan akibat dari modernisasi perguruan tinggi yang berakibat fatal. “Apakah kita sedang menuju ke arah yang sama dan apakah kita bisa menghindarinya?” tanya Hariadi.
Menurut dia, ada 3 aspek yang menjadi dasar mengapa sisi gelap kampus ini terjadi, seperti diungkap Fleming:
Pertama masalah kebebasan. Pasal 28E UUD 1945, pasal 24 ayat 1 UU Nomor 20/2003, dan pasal 8 ayat 3 UU Nomor 12/2012 mengamanatkan dan menjamin kebebasan berpendapat dalam segi apa pun. Pasal-pasal ini pernah dicoba dilucuti oleh omnibus law UU Cipta Kerja ketika masih berbentuk rancangan.
Menurut Hariadi, RUU Cipta Kerja menempatkan pendidikan dalam konteks uang, investasi, dan perolehan laba serta proses industri. Para elite politik Indonesia mendorong liberalisasi pendidikan sejak dari kebijakan hulunya, yakni undang-undang.
Kedua konflik kepentingan dan korupsi yang menyebabkan hilangnya kebebasan berpendapat. Jabatan dalam sektor pendidikan pun diperjualbelikan sehingga para aktor di dalamnya menjadi tidak bisa berpendapat dan punya benturan kepentingan. Mereka tak bisa menyuarakan antikorupsi karena mereka sendiri adalah pelakunya.
Hariadi data Komisi Pemberantasan Korupsi (2021) yang menemukan data bahwa ada tarif jual-beli jabatan dari pemerintah pusat hingga daerah. Eselon III di pusat tarifnya Rp 10-80 juta, sekelas Kepala Dinas di daerah Rp 80-400 juta, untuk menjadi Kepala Sekolah SD dan SMP mesti menyuap Rp 80-150 juta, bahkan mutasi guru Rp 15-60 juta.
Ketiga daya tahan personal. Dalam cengkeraman liberalisasi itu daya tahan personal tiap peneliti dan dosen diperlukan untuk mempertahankan kebebasan berpendapat. Di atas kertas, kata Hariadi, semua orang setuju demokrasi perlu kebebasan berpendapat. Inovasi tak akan terjadi tanpa kebebasan. Namun, ketika kebebasan itu hadir, semua orang lupa memanfaatkan dan mengisinya.
Akibatnya, kebebasan yang tak terisi oleh ilmuwan itu dipenuhi oleh oligarki dan politikus yang mendagangkan kepentingan. Hariadi menunjukkan bahwa RUU Cipta Kerja adalah buah kebebasan para politikus dan oligarki memakai instrumen negara dalam mendesakkan kepentingan mereka akibat absennya pada ilmuwan mengisi kebebasan.
Para pembicara sepakat bibit sisi gelap universitas mulai muncul di Indonesia. Cara menghindarinya adalah penguatan fundamental kampus dan daya tahan personal tiap ilmuwan bersama-sama mengisi kebebasan berpendapat untuk meluaskan ilmu dan pengetahuan untuk mencegah kepentingan lain mengisinya.
BERSAMA MELESTARIKAN BUMI
Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.
Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.
Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.

Alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University
Topik :












