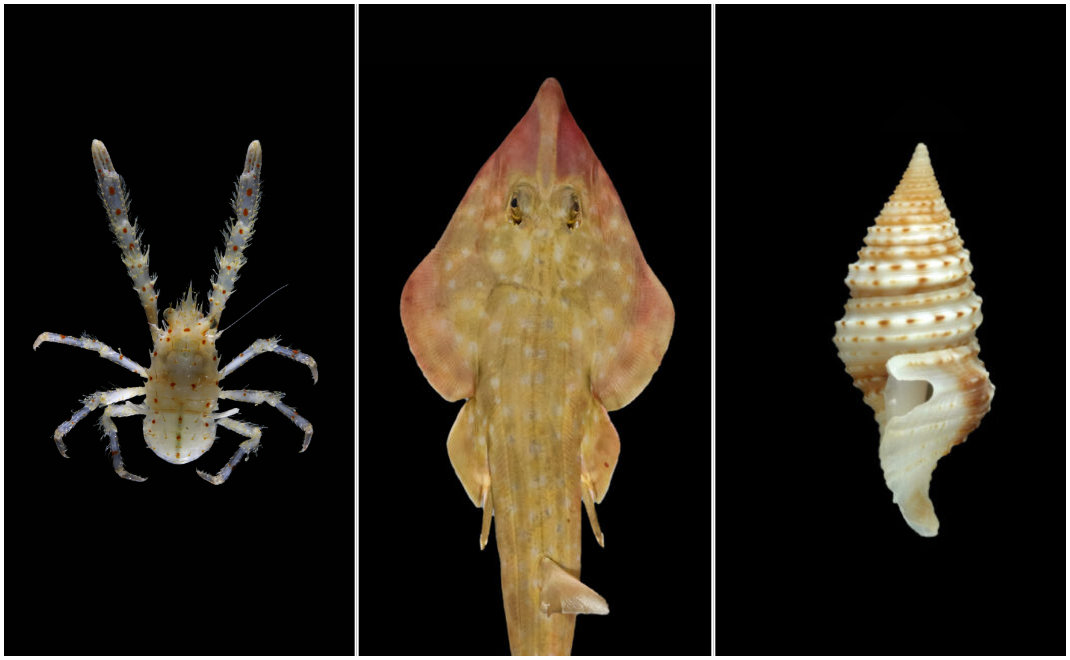Kabar Baru| 14 Oktober 2021
10 + 1 Penerima Kalpataru 2021

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan penghargaan Kalpataru, penghargaan lingkungan sejak 1980, kepada sepuluh penerima tahun ini. Menteri Siti Nurbaya menyerahkannya di Gedung Manggala Wanabakti pada 14 Oktober 2021.
Kriteria penerima Kalpataru, menurut rilis KLHK, diberikan kepada para penjaga lingkungan yang memberikan dampak ekologi, sosial, dan ekonomi. “Untuk memberikan kesadaran, membuka peluang berkembangnya inovasi dan kreativitas dan mendorong prakarasa mengelola lingkungan secara berkelanjutan,” tulis rilis itu
Ada empat kategori penerima Kalpataru: perintis lingkungan, pengabdi lingkungan, penyelamat lingkungan, dan pembina lingkungan. Kalpataru Tahun 2021 diberikan kepada empat orang kategori perintis lingkungan, satu pengabdi Lingkungan, tiga kelompok masyarakat dalam kategori penyelamat lingkungan, dan dua orang dari kategori pembina lingkungan.
Berikut ini catatan juri Kaplataru 2021:
Perintis Lingkungan
Purwo Harsono, Bantul, Yogyakarta
Ia biasa disapa Ipung. Lahir pada 1967 di Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta, Ipung merintis desanya menjadi Desa Wisata Kaki Langit. Pada 2015, Kelompok Sadar Wisata mendirikan Koperasi Noto Wono sebagai salah satu lini kegiatan masyarakat desa. Lini bisnisnya merambah banyak jenis: Atap Langit (homestay), Rasa Langit (kuliner), Budaya Langit (budaya dan tradisi), Langit Ilalang (taruna wisata), Karya Langit (cenderamata), Langit Terjal (akomodasi wisata/jip wisata), Langit Hijau (wisata tani), dan Langit Cerdas (wisata edukasi).
Karena ekowisata berbasis alam, penduduk membutuhkan hutan. Mangunan punya hutan desa seluas 30 hektare. Dengan konservasi yang dipimpin Purwo Harsono, jumlah kebakaran hutan dan perambahan hutan di wilayah Mangunan turun. Kegiatan penanaman pohon dan pelestarian hutan juga telah memunculkan sumber-sumber mata air baru, pembuatan talud penahan erosi di desa wisata mengurangi terjadinya bencana erosi, penataan kandang ternak dan pembuangan limbah membuat lingkungan tertata lebih asri, sejuk, dan nyaman.
Kegiatan Desa Wisata dan Wana Wisata telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi mereka yang berpartisipasi aktif sebagai pengelola. Kegiatan ini juga membuka lapangan kerja dan peluang usaha baru, serta memberikan kontribusi terhadap PAD sebesar Rp 7.625.606.250 dalam kurun waktu empat tahun.
Damianus Nadu, Bengkayang, Kalimantan Barat
Usianya 62 tahun. Ia sosok penting di balik keberadaan hutan Pikul. Ia dikenal sebagai tabib hutan adat Pikul dengan pengobatan menggunakan tanaman dan juga tokoh adat Dayak Bekatik Lara untuk acara-acara adat, seperti acara gawai, perkawinan, pesta adat, dan penyelesaian konflik di masyarakat.
Sejak 1980, hutan adat Pikul yang berada di dalam kawasan Hutan Hak Penggunaan Lain (HPL) dan Hutan Produksi Konversi (HPK) dijaga dan dipertahankan keberadaannya. Pada 28 Maret 2018 hutan adat Pikul menjadi hutan adat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Damianus Nadu merintis kegiatan penanaman dengan jenis belian, bengkirai, mahoni, keladan, dan lainnya bersama masyarakat adat di lahan kritis bekas eksploitasi oleh perusahaan kayu dan pembalak liar telah dimulai sejak tahun 1996. Penanaman tengkawang di kebun dan ladang milik penduduk, termasuk di pekarangan, mencapai 2.000. Ia mendirikan Kelompok Tani Tengkawang Layar sebagai jalan pemberdayaan.
Beberapa Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) juga dibentuk. Salah satunya adalah KUPS Bunga Layar yang beranggotakan 20 perempuan Dusun Melayang yang telah mengikuti pelatihan membuat mi, kue, dan es krim. Berkat Damianus Nadu hutan adat Pikul seluas 107,44 hektare beserta keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya terjaga dari pembalakan, perambahan, dan kebakaran.
Darmawan Denassa, Gowa, Sulawesi Selatan
Lahir 1976, ia menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin. Setelah lulus menjadi dosen di almamaternya selama enam tahun. Ia memilih pulang kampung dan mendirikan Rumah Hijau Denassa sebagai wadah pembelajaran yang memadukan kearifan lokal dan budaya Sulawesi Selatan dengan pelestarian dan penyelamatan keanekaragaman hayati.
Beragam kegiatan RHD adalah penyelamatan tanaman langka dan endemik Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, pendirian Kampung Literasi pada 2016 untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang enam literasi dasar, pengembangan kegiatan ekowisata yang dipadukan dengan kegiatan edukasi melalui kelas alam bagi murid-murid SD, pendirian Kelas Komunitas gratis, pembentukan Forum Diskusi Warga yang berkembang menjadi Diskusi Tematik, serta penyelamatan dan pemurnian lahan di lokasi RHD. Di RHD anak-anak belajar mengolah sampah.
Kegiatan penanaman tanaman investasi keluarga dimulai pada 2007 dengan 100 batang bibit jati, 160 batang bibit mahoni, dan 30 batang kelapa dalam yang ditanam di lahan RHD dan kebun masyarakat. Tanaman-tanaman bisa dipanen oleh Denassa dan masyarakat ketika anak mereka membutuhkan biaya pendidikan di perguruan tinggi.
Buah kelapanya pun bisa dipanen dan dijual. Kegiatan yang dilakukan Denassa telah berhasil menyelamatkan dan mengembalikan keanekaragaman hayati yang sempat hilang di Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Barat. Ia juga berkontribusi melengkapi data Balai Kliring Keanekaragaman Hayati dan membantu Dinas Lingkungan Hidup untuk mendata dan mendokumentasikan keanekaragaman hayati endemik Kabupaten Gowa.
Rumah Hijau Denassa (RHD) menjadi model penyelamatan keanekaragaman hayati dan pengembangan ekowisata dan edukasi yang mendukung dan bersinergi dengan program-program pemerintah. Denassa mempekerjakan tujuh orang sebagai operator, 32 orang yang terlibat langsung pada setiap kunjungan, lima orang relawan pemandu.
Muhammad Yusri, Polewali Mandar, Sulawesi Barat
Ia pendiri Rumah Penyu dan komunitas Sahabat Penyu, yang berlokasi di Dusun Mampie, Desa Galeso, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Upaya pelestarian penyu oleh laki-laki yang lahir 1989 ini dimulai pada 2013 di kawasan Pantai Mampie seluas 7 km². Selain kampanye untuk mengubah persepsi masyarakat, inisiatif pembelian lubang penyu juga dilakukan seharga Rp 100.000 per lubang.
Lubang penyu sebagai “rumah” bagi induk penyu menjadi alasan Pantai Mampie disebut “Rumah Penyu”. Pada tahun 2014, kegiatan Adopsi Penyu dirintis dengan dana adopsi Rp300.000 per lubang. Pada tahun 2016, Sahabat Penyu yang dibentuk pada tahun 2015 menerima SK Kepala Desa Mampie untuk mengelola Pantai Mampie sepanjang 9 km, dengan zonasi 7 km sebagai daerah pendaratan penyu dan 2 km sebagai daerah perlindungan penyu. Kurang lebih 3.000 lubang telah diselamatkan setiap tahunnya, dengan tingkat keberhasilan penetasan sebesar 80% dan 40.000 tukik telah dilepasliarkan hingga kini.
Kegiatan Wisata Edukasi Rumah Penyu dimulai dengan membangun dua resor menggunakan dana hasil kegiatan Adopsi Penyu dan dana pribadi untuk disewakan. Pelestarian mangrove telah dimulai dengan penanaman mangrove sejak tahun 2008. Rata-rata jumlah bibit yang ditanam sebanyak 5.000 batang per tahun dengan luasan lahan 10 hektare di Pantai Mampie. Sampai saat ini, telah dilakukan penanaman sebanyak 35.000 pohon jenis Rhizophora apiculata, Avicennia germinans, dan Bulgeria sp.
Pendampingan kelompok ibu-ibu PKK juga dilakukan untuk mengolah buah mangrove menjadi bahan makanan, seperti kue brownis, krupuk, dan bahan pengganti beras. Kegiatan yang dilakukan Yusri berdampak pada bertambahnya populasi penyu dan berkurangnya telur penyu yang dijual di pasar tradisional yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. jumlah kunjungan wisata semakin meningkat dengan adanya Rumah Penyu. Kunjungan pengadopsi dan tamu ker Rumah Penyu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pantai Mampie dengan jumlah transaksi mencapai Rp150.000.000 per tahun.
Kategori Pengabdi Lingkungan
Suswaningsih, Gunungkidul, Yogyakarta
Pegawai negeri Dinas Pertanian dan Pangan Gunung Kidul ini mengajak masyarakat untuk melakukan gerakan penghijauan memakai jenis tanaman buah-buahan, kayu-kayuan, dan rumput, sejak 1996. Ketika itu ia masih pegawai honorer selama enam tahun. Pemanfaatan lahan secara optimal juga dilakukan dengan menanam tanaman kayu-kayuan dan tanaman pangan dengan sistem tumpang sari di kawasan bebatuan bertanah dan bawah tegakan seluas 903,7 hektare.
Penanaman kelapa juga dilakukan di pekarangan rumah, ladang, dan tepi lahan tegalan yang sampai saat ini telah berjumlah ± 585 batang pohon kelapa. Sebanyak 5% yang berbuah setiap bulannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan produksi jenang. Pendampingan masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan dan tepi tegal seluas ± 25 hektare di Kelurahan Melikan dilakukan dengan menanam jenis tanaman buah dan sayuran.
Selain pendampingan, bimbingan dan pelatihan diberikan kepada kelompok dan individu untuk mengolah hasil pertanian dengan memanfaatkan bahan baku lokal hasil budidaya masyarakat. Jenis hasil olahan yang dihasilkan adalah kripik pisang tanduk, jenang dodol, kripik singkong, emping melinjo, wajik kletik, dan lain-lain. Kegiatan penghijauan yang dilakukan berhasil mengurangi lahan kritis dan membuat air telaga lebih awet.
Penyelamat Lingkungan
LPHD Pasar Rawa, Langkat, Sumatera Utara
Lembaga Peneglola Hutan Desa Pasar Rawa mengelola kawasan hutan desa seluas 138 hektare di Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat. LPHD Pasar Rawa yang didirikan pada tanggal 15 Juli 2014 yang berawal dari kesepakatan bersama 25 orang masyarakat desa yang prihatin dan peduli terhadap keberlangsungan ekosistem mangrove untuk membentuk Kelompok Tani Hutan Desa Pasar Rawa.
Rehabilitasi mangrove mereka lakukan karena rusak akibat perkebunan kelapa sawit seluas 138 hektare. Pembibitan secara swadaya sejak 2012 dan bibit yang telah dihasilkan sebanyak 800.000 batang jenis Rhizophora. Penanaman di areal seluas 113 hektare dengan dukungan dari Yagasu dan di areal 20 hektare bersama dengan BPDAS-HL Wampu Sei Ular Sumatera Utara.
Penanaman 2018 sebanyak 15.000 batang jenis Rhizophora sp. bersama pemerintah daerah, masyarakat, dan pelajar. Patroli pengawasan mangrove telah dilakukan sekali sebulan sejak tahun 2010 dengan dukungan dari dinas terkait dan LSM. Tambak percontohan model tambak empang parit seluas 18,5 hektare dibangun dan dikelola dengan konsep kombinasi hutan mangrove dan budidaya perikanan.
Desa wisata mangrove mulai didesain pada tahun 2019. Penanaman dan pemeliharaan mangrove yang dilaksanakan berhasil memulihkan ekosistem mangrove seluas 263,5 hektare, mengurangi banjir rob, memulihkan jalur hijau desa yang melindungi dari abrasi, meningkatkan biota laut, dan memperbaiki kondisi lingkungan di Desa Pasar Rawa. Dampak ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Langkat, turut meningkat. Hasil kegiatan perikanan masyarakat meningkat sekitar 30-50% per tahun. Mereka juga mendapatkan tambahan penghasilan dari kegiatan pengembangan wisata sekitar Rp300.000- Rp500.000 per bulan.
Forum Pemuda Peduli Karst Citatah, Bandung Barat Provinsi Jawa Barat)
(FP2KC berdiri pada 20 Mei 2009 di Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat sebagai upaya penyelamatan kawasan karst Citatah dan penanggulangan dampak negatifnya. Forum ini diketuai oleh Deden Syarif Hidayat dan terbentuk dari beberapa kelompok pemuda dan karang taruna, peneliti, pencinta alam, pegiat panjat tebing, dan kelompok masyarakat lainnya.
Pembentukan objek geowisata berwawasan konservasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dilakukan di empat desa, yaitu Desa Padalarang, Desa Gunungmasigit, Desa Citatah, dan Desa Cirawamekar, sejak 2009. Kegiatannya penyampaian opini melalui media elektronik dan diskusi bersama masyarakat lokal dan komunitas penggiat lingkungan dan penyadaran kapur.
Masyarakat juga diajak untuk mengonservasi bekas tambang dan melakukan penanaman sekitar 90.000 pohon, membuat sarana prasarana informasi dan edukasi, dan membentuk kelembagaan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan berhasil menghentikan pertambangan ilegal di beberapa titik kawasan sejak awal tahun 2010 dan mendorong dikeluarkannya Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perlindungan Kawasan Konservasi Pasir Pawon.
Pengelolaan geowisata melibatkan 185 orang warga (akomodasi, transportasi, jasa pemandu, dan kelompok industri kreatif masyarakat lokal, serta warung). Kampung Berbudaya Lingkungan (Ecovillage)/Kampung Berseri Astra (KBA) mulai dibentuk pada tahun 2017 dengan dana sebagian besar dari swadaya FP2KC dan didukung oleh PT Astra Honda Motor untuk bantuan prasarana dan pembinaan masyarakat.
Kegiatan rehabilitasi yang dilaksanakan oleh FP2KC berkontribusi pada terselamatkannya sekitar 91 hektare Kawasan Lindung Karst dari kegiatan pertambangan, terjaganya sumber mata air, terjaganya keanekaragaman hayati, bertambahnya tutupan vegetasi, dan berkurangnya lahan kritis, polusi udara, erosi, dan longsor.
Dampak kegiatan FP2KC berkontribusi pada pembukaan lapangan usaha baru bagi masyarakat, pembinaan petani dengan usaha budidaya pertanian dan kelompok usaha wanita bidang olah hasil tani, dan pemanfaatan pekarangan rumah dengan tanaman pangan untuk pemenuhan kebutuhan pangan keluarga. Pendapatan masyarakat juga meningkat, baik sebagai pengelola geowisata, nasabah bank sampah, maupun pelatih panjat tebing.
Sombori Dive Conservation, Morowali, Sulawesi Tengah
Ini kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan dan penyelamatan pesisir pantai dan terumbu karang di Pantai Morowali, Kabupaten Morowali. Kelompok yang beranggotakan sebagian besar anak muda milenial ini berdiri pada tanggal 15 September 2015. Kegiatan rehabilitasi dan transplantasi terumbu karang dengan jenis Acropora branching (tipe karang bercabang) dilakukan di Pulau Sombori dan sampai saat ini telah berhasil merintis pemulihan sebagian terumbu karang.
Taman bawah laut sebagai wisata diving dikembangkan selama proses rehabilitasi terumbu karang, khususnya di Desa Mbokita, Pulau Sombori; Aquarium Point Desa di Desa Pulau Dua Keca; Bungku Selatan dan Home Fish di Desa Fatufia, Kecamatan Baodopi. Lokasi tersebut telah diliput oleh beberapa stasiun TV nasional dan jumlah wisatawan meningkat dari sekitar 2.000 wisatawan pada tahun 2017 menjadi 5.000 wisatawan lokal, nasional, dan mancanegara pada tahun 2020.
Pembibitan dan penanaman mangrove untuk mengatasi abrasi pantai dilakukan di tiga desa di Kecamatan Bungku Pesisir yang merupakan lingkar tambang nikel. Jenis Rhizophora sp. adalah bibit mangrove yang dikembangkan dan ditanam di lahan seluas 4,5 hektare pada tahun 2020. Area penanaman mangrove kini telah dilengkapi dengan trekking dan menjadi lokasi wisata.
Kegiatan Sombori Dive Conservation (SDC) Morowali secara ekologi berdampak pada perlindungan ekosistem laut dari kegiatan pengeboman ikan, pemulihan ekosistem mangrove dari aktivitas pertambangan di pesisir pantai, dan pencegahan abrasi pantai. Perusahaan sekitar tambang juga lebih memperhatikan keseimbangan ekosistem dengan aktivitas rehabilitasi kembali. Dampak ekonomi, penghasilan masyarakat bertambah dari usaha penginapan masyarakat desa untuk pengunjung lokasi wisata trekking mangrove, dan dari penjualan hasil pembibitan mangrove.
Pembina Lingkungan
K.H. Zarkasyi Hasbi, Lc., Banjar, Kalimantan Selatan
Sebagai anak petani, Pak Kyai yang lahir pada tanggal 29 Februari 1952, mencintai lingkungan sejak kecil. Ia adalah lulusan Institut Pendidikan Darussalam Gontor pada 1980. Cita-citanya untuk membangun pesantren yang modern di Kalimantan Selatan. Sepulangnya dari Madinah pada 1986, ia mulai membangun Pondok Pesantren Darul Hijrah di Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar.
Pengembangan budidaya perikanan dimulai sejak tahun 1986 dengan menggunakan lahan yang tidak produktif dan tidak dimanfaatkan. Usaha yang dilakukan mendorong pemerintah untuk mengembangkan sistem irigasi pada tahun 1995, meskipun awalnya untuk pengairan sawah.
Beberapa kegiatan dikembangkan dengan model silvofishery. Perintisan kegiatan menunjukkan hasil yang baik sejak 2000 dan mulai dicontoh oleh masyarakat dengan mengembangkan budidaya ikan di lahan seluas 500 hektare oleh sekitar 100 keluarga. Pembinaan kepada masyarakat juga terus dilakukan. Saat ini, luas lahan masyarakat yang kurang produktif untuk budidaya ikan mencapai 3.100 hektare dengan 539 usaha budidaya ikan.
Pengembangan eco-pesantren dirintis sejak awal pendirian Pondok Pesantren Darul Hijrah pada tahun 1986. Saat ini, berbagai kegiatan dilakukan adalah pemanfaatan lahan pesantren untuk budidaya perikanan, pengelolaan dan pendirian bank sampah, pembibitan tanaman, peternakan, dan pertanian hidroponik.
Kegiatan eco-pesantren ini menjadi model yang pertama dan dicontoh oleh 21 pondok pesantren di Provinsi Kalimantan Selatan. K.H. Zarkasyi Hasbi menjadi pembina sekaligus contoh bagi masyarakat dalam memanfaatkan lahan kurang produktif yang luasnya mencapai 3.100 hektare untuk budidaya ikan.
Beberapa dampak ekologi dari kegiatan yang dilaksanakan adalah lahan yang digunakan untuk budidaya ikan tetap lembap dan basah sehingga tanah menjadi lebih subur, dan kolam budidaya perikanan juga berfungsi sebagai embung untuk persediaan air mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Rehabilitasi 50 hektare lahan kritis dengan berbagai jenis tanaman membuat kondisi lingkungan semakin nyaman dan sejuk.
Dampak ekonomi, pembinaan yang dilakukan berkontribusi pada terbukanya lapangan usaha yang mencapai 539 usaha budidaya ikan dan berkembangnya usaha lain seperti usaha pakan ikan, ekowisata, peternakan, dan pertanian. Pendapatan masyarakat, khususnya di Desa Cindai Alus, mengalami peningkatan yang secara total mencapai Rp24 miliar per bulan dari budidaya ikan patin.
Suhadak, Lampung Timur, Lampung
Suhadak yang lahir di Banyuwangi pada tanggal 9 Desember 1970 bertugas sebagai Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) Kabupaten Lampung Timur. Selain itu, ia juga Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Bina Warga, Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Braja Harjosari dan pengurus Forum Rembug Desa Penyangga (FRDP) Taman Nasional Way Kambas (TNWK).
Advokasi penanganan konflik gajah dan manusia dilakukan sejak tahun 2011 bersama Pengurus Forum Rembug Desa Penyangga (FRDP) Taman Nasional Way Kambas dan Balai Taman Nasional Way Kambas (TNWK) kepada masyarakat desa di kawasan penyangga. Kegiatan difokuskan di dua desa, yaitu Desa Braja Sari dan Desa Labuhan Ratu VII.
Upaya penyuluhan kepada masyarakat dilakukan dengan menyampaikan perlunya menyelamatkan gajah dan menjaga agar lahan pertanian masyarakat tidak diganggu gajah. Pengembangan pertanian dan padang penggembalaan dilakukan dengan memanfaatkan tanah desa seluas 3 hektare sehingga ternak kerbau yang dilepas tidak masuk ke lahan pertanian dan perkebunan, serta ke kawasan TNWK.
Lahan terbuka yang diberi nama padang sabana tersebut ditanami rumput dan dibatasi parit sehingga kerbau tidak masuk ke kawasan TNWK. Selain itu, pengembangan wisata minat khusus juga dilakukan pada tahun 2014 yang memanfaatkan kegiatan penghalauan gajah liar.
Homestay, suvenir, dan paket-paket lainnya seperti ternak kambing, budidaya ikan air tawar, budidaya lebah trigona, budidaya tanaman obat atau empon-empon, pembuatan pakan ternak, pembuatan pupuk kompos, dan pembuatan minuman herbal dari buah maja juga turut dikembangkan. Kegiatan yang dilakukan berdampak pada berkurangnya tekanan terhadap kawasan TNWK dengan adanya usaha wisata minat khusus yang mengurangi perambahan dan memberikan pendapatan alternatif.
Tegakan hutan TNWK yang rusak akibat penggembalaan liar kerbau juga dapat terpulihkan dengan penanaman sejumlah 12.000 bibit. Dampak ekonomi, usaha wisata minat khusus rata-rata memberikan penghasilan sebesar Rp5 juta per homestay ketika wisatawan asing berkunjung. Saat ini, 25 KK telah menggunakan rumah mereka untuk homestay. Hasil pertanian yang meningkat juga menambah kesejahteraan masyarakat.
Selain Kalpataru, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan satu Penghargaan Khusus kepada Ali Topan dari Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Pemuda Inspiratif untuk Advokasi Lingkungan.
Ia lahir di Pinrang pada tanggal 7 Mei 1985. Sejak SMA, ia sudah gemar berorganisasi. Ia menjadi pendiri beberapa organisasi, seperti Kelompok Pencinta Alam (2005), SAR Pinrang (2009), Petani Milenial Pinrang (2018), dan Bank Sampah Peduli Pinrang (2019). Ia juga aktif di beberapa organisasi, seperti Karang Taruna Sarsos/Bidang Lingkungan dan organisasi lainnya.
Penanaman mangrove dan pembersihan dilakukan di pesisir bersama Saka Bahari (Pramuka). Kampanye juga dilakukan untuk mempromosikan kegiatan tersebut. Pada tahun 2018, kegiatan World Clean Up Day diinisiasi karena rasa keprihatinan terhadap kondisi sampah di Kabupaten Pinrang dan rendahnya partisipasi anak muda untuk mengelola sampah
BERSAMA MELESTARIKAN BUMI
Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.
Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.
Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.

Redaksi
Topik :