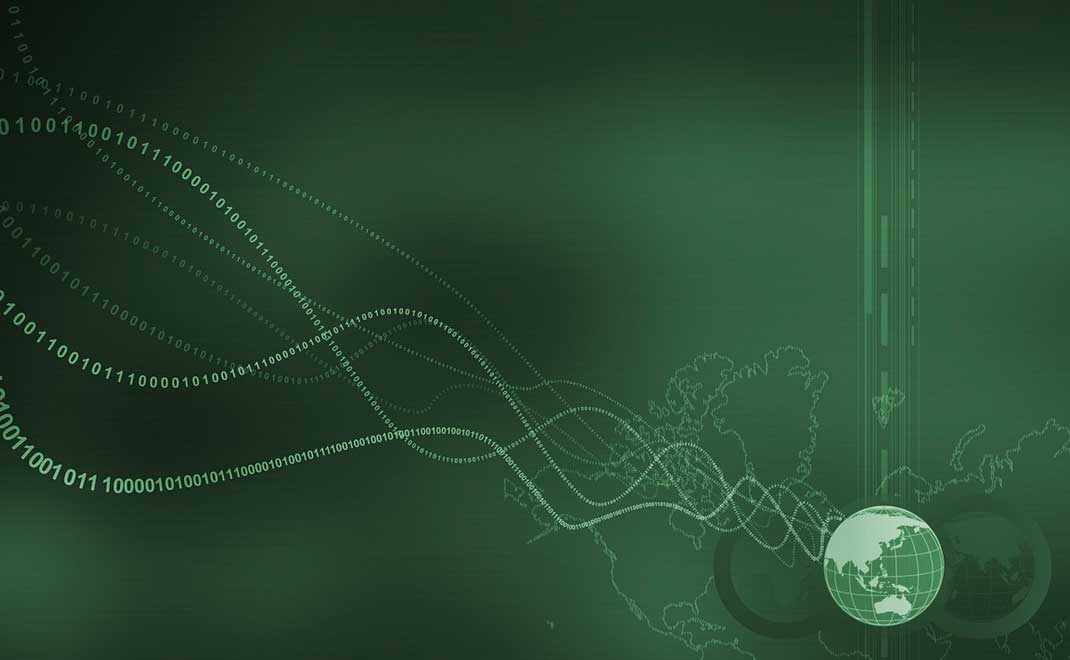
PEMANFAATAN sumber daya alam yang berpotensi merusak lingkungan dan sosial seharusnya bisa dikendalikan oleh pemberi izin pemanfaatannya, yakni pemerintah pusat maupun daerah. Faktanya, tanggung jawab itu belum terjalankan dengan baik. Padahal, bukti kerusakan lingkungan dan sumber daya alam akibat perizinan menjadi penyebab bencana dan berbagai konflik agraria.
Angka Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan pada 2021 banjir sebanyak 1.794 kali dan longsor 1.321 kejadian dari fenomena lokal serta 1.577 peristiwa cuaca ekstrem. Demikian pula konflik sosial pemanfaatan sumber daya alam. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam lima tahun terakhir mendapat pengaduan masyarakat dan sekitar 30% berupa konflik agraria.
Sementara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada 2020 melaporkan konflik agraria antara masyarakat dan pemerintah sebanyak 2.866 kasus, antara perorangan dan badan hukum 1.668 kasus, dan antar badan hukum 131 kasus. Pemberian izin pemanfaatan sumber daya alam punya peran besar dalam berbagai kasus itu.
Pemberi izin memang tidak harus bertanggung jawab sendirian. Izin memang menjadi penentu. Tidak ada izin, tidak ada kegiatan yang merusak. Tetapi kegiatan seperti itu juga tidak akan berjalan tanpa modal. Maka, lembaga keuangan juga harus ikut bertanggungjawab.
Masalahnya, apakah logis hal itu diterapkan dalam transaksi komersial antara lembaga keuangan—khususnya bank—dengan para debiturnya?
Koalisi Forest and Finance, terdiri dari Rainforest Action network, TuK Indonesia, Profundo, Amazon Watch, Reporter Brasil, Bank Track, Sahabat Alam Malaysia dan Friends of the Earth Amerika Serikat, sudah dan sedang mendorong kebijakan lembaga jasa keuangan yang bisa mencegah pendanaan terhadap bisnis (debitur) yang mengakibatkan masalah sosial dan kerusakan lingkungan.
Pekan lalu, di Jakarta, koalisi itu melaporkan dari 50 lembaga keuangan global terbesar yang mendanai sektor yang berisiko terhadap kerusakan lingkungan—dengan fokus pada deforestasi—hanya punya skor 2,3 dari maksimal 10. Skor 10 adalah yang terbaik.
Lembaga-lembaga itu telah memberi kredit US$ 128 miliar pada 2016-2020 serta kepemilikan saham dan obligasi sebesar US$ 28 miliar (per April 2021). Di Indonesia, bank nasional “terbaik” pun, dengan nilai skor di bawah 3, yaitu Bank Mandiri, Bank Central Asia, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, meski punya komitmen terhadap pendanaan berkelanjutan (sustainable finance), tapi masih sekadar janji di atas kertas.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyusun peta jalan Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025) dan juga telah mempunyai Taksonomi Hijau Indonesia—Edisi 1.0, 2022, yang disusun oleh delapan kementerian. Tentu saja optimisme itu perlu terus didorong, juga oleh koalisi. Untuk di Indonesia, mungkin perlu menggunakan pembelajaran di masa lalu, bagaimana kebijakan serupa itu berjalan.
Dalam artikel “The Role of Sustainable Finance in Achieving Sustenable Development Goals: Does it work?” (2020), Ziolo dkk menyebut untuk negara-negara maju d ibawah Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), kebijakan keuangan terbukti mampu meningkatkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Mereka menemukan hubungan yang kuat antara model keuangan berkelanjutan dan keberlanjutan sosial (SDG1, 3, 4, 5, 10, 16), kelestarian lingkungan (SDG11, 12, 13, 15) dan keberlanjutan ekonomi (SDG8, 9, 17).
Untuk banyak negara—bahkan di negara maju—mewujudkan pembangunan berkelanjutan memerlukan dana besar dan dana ini berasal dari berbagai jenis lembaga keuangan. Melalui studi berbagai pustaka, artikel Ziolo dkk ini menyimpulkan bahwa pembiayaan konvensional tidak memadai dan tidak cocok untuk membiayai SDGs, karena tidak menyisakan ruang untuk masalah lingkungan dan sosial. Postulat telah dirumuskan yaitu harus dengan memasukkan faktor non-keuangan (lingkungan, sosial, tata kelola) ke dalam analisis risiko lembaga keuangan.
Untuk pelaksanaan bisnis lingkungan berkelanjutan di Indonesia, saya memberikan beberapa pertimbangan:
Pertama, perlu perluasan lingkup berpikir. Sifat transaksi bisnis dengan bisnis, yaitu bank dengan kegiatan usaha dalam hal kebutuhan finansial, biasanya ditangani oleh holding. Ini bisa dimengerti, karena penguasaan aset sebagai jaminan maupun rekam jejak diwakili oleh holding itu.
Bila faktor lingkungan, sosial , dan tata kelola (LST) dimasukkan, persoalan akan timbul karena penilaian dampak LST tidak berada di “ruang” holding. Dampak itu berada dalam ruang dan waktu tertentu yang menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dampak LST juga tidak bisa hanya dicirikan oleh bentuk dan sifat kegiatan usaha, juga oleh kondisi lingkungan dan sosialnya. Artinya, memasukkan faktor LST berarti mengubah cara berpikir transaksi pembiayaan, risiko finansial maupun kegiatan suatu usaha.
Kedua, substansi hubungan antar lembaga. Dalam kenyataannya, setiap usaha pemanfaatan sumber daya alam tidak senantiasa langsung memenuhi kriteria LST. Dalam sertifikasi ekolabel yang sudah berjalan, misalnya, selalu ada koreksi, baik yang bersifat minor ataupun mayor. Sifat minor bisa dilakukan sendiri oleh usaha itu, sedangkan sifat mayor perlu peran pemerintah. Bila terjadi konflik agraria atau ada persoalan tata ruang, misalnya, pemerintah perlu memainkan peranannya. Ini menjadi tantangan tersendiri karena pemerintah belum melakukan implementasi kebijakan satu data dan satu peta untuk mencegah konflik penggunaan ruang.
Untuk menyikapi hal tersebut, dalam kasus sertifikasi di kehutanan, ada kebijakan pendekatan bertahap (phase approach). Misalnya, verifikasi legalitas kayu menjadi tahap awal menuju pengelolaan hutan keberlanjutan. Sebab kata “berkelanjutan” itu bukan hanya didukung oleh syarat-syarat administrasi, tapi harus nyata bisa dilihat kondisinya di lapangan.
Hal ini memang ironis. Karena sahnya izin dari surat keputusan oleh pihak yang berwenang itu tidak selalu berarti mempunyai legitimasi secara sosial. Itulah mengapa konflik kerap terjadi. Untuk itulah, sektor keuangan dan sektor sumber daya alam perlu menetapkan urusan-urusan yang bisa menjamin legal sekaligus legitimasi sosial atas pemanfaatan sumber daya alam yang mendapatkan pembiayaan berkelanjutan.
Ketiga, soal konflik kepentingan. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam transaksi keuangan berkelanjutan bisa terjadi konflik kepentingan. Hal ini perlu didalami lebih lanjut terutama terkait dengan kontroversi adanya kerahasiaan transaksi keuangan di satu sisi dan kewajiban terbuka akibat dampak lingkungan dan sosial bagi publik di sisi lain.
Analisis dalam Laporan Risiko Global 2020 memperlihatkan dalam daftar 10 risiko bagi ekonomi adalah kegagalan aksi iklim. Kelompok risiko lingkungan menempati urutan pertama, diikuti risiko sosial, risiko teknologi dan risiko geopolitik. Untuk mengatasi konflik kepentingan bisnis lingkungan harus ada kebijakan afirmatif, dengan memastikan apa dan siapa yang harus dibela.
Perlu juga menerapkan nilai finansial dari seluruh dampak kegiatan terhadap lingkungan dan sosial. Karena itu kelayakan transaksi keuangan harus didasarkan pada nilai finansial dampak tersebut. Konsekuensinya, dalam bisnis lingkungan berkelanjutan, seluruh pihak yang bertransaksi tidak boleh melarikan diri dari nilai dampak yang terjadi itu.
BERSAMA MELESTARIKAN BUMI
Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.
Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.
Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.

Guru Besar Kebijakan Kehutanan pada Fakultas Kehutanan dan Lingkungan serta fellow pada Center for Transdiciplinary and Sustainability Sciences, IPB.
Topik :

















