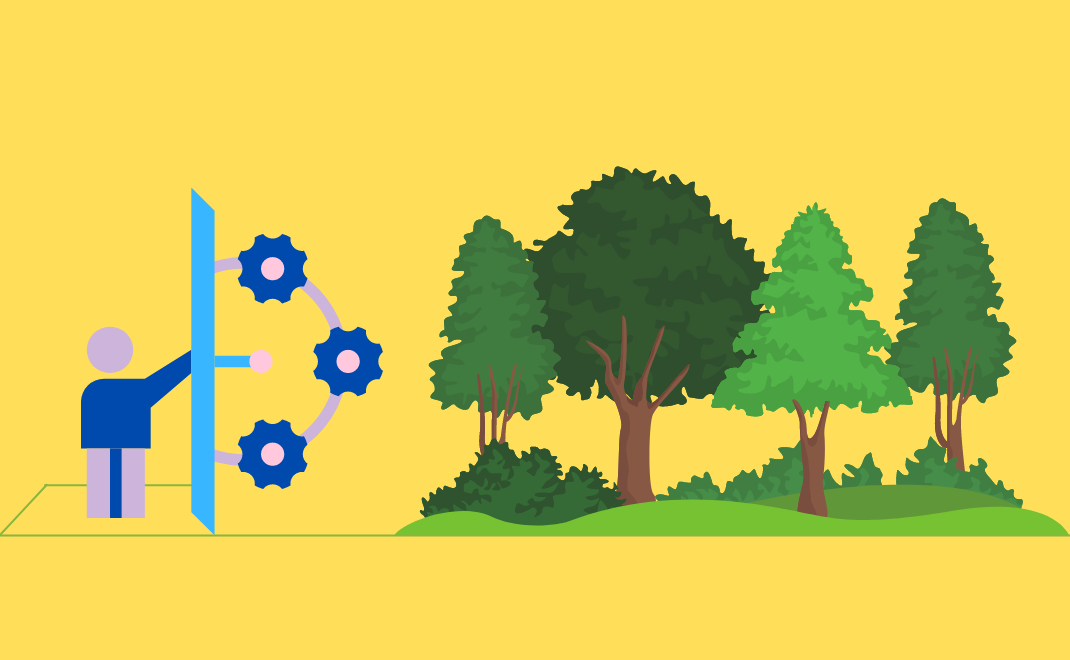
KINI kawasan hutan semakin dituntut memberikan peranannya dalam mempertahankan fungsi lingkungan, sosial, maupun ekonomi secara nyata. Untuk mewujudkannya memang tidak mudah. Ada berbagai tantangan para pengelola hutan, di tingkat operasional maupun analitis, dalam memakai ilmu pengetahuan dan politik yang bisa menggagalkan tujuan itu.
Dua artikel saya sebelumnya, “Modal Sosial Rehabilitasi Hutan dan Lahan” dan “Distorsi Komunikasi Kebijakan Publik”, yang membicarakan pentingnya penguasaan kondisi sosial di lapangan serta strategi komunikasi kebijakan yang tepat, mendapat tanggapan langsung dari pembaca yang meminta penjabaran lebih luas.
Saya coba mengulas kebijakan paling baru dalam manajemen hutan Jawa, yakni kawasan hutan dengan pengelolaan khusus (KHDPK)—lihat artikel “KHDPK: Kebijakan untuk Reformasi Perhutani”. Kebijakan ini menuai pro dan kontra, meski kebijakannya secara penuh dan utuh belum lagi dirilis pemerintah.
Sebelum membahas lebih jauh, mari kita mulai dari pemikiran Gerhard Weiss, dkk, dalam “Innovation Governance in the Forest Sector: Reviewing concepts, trends and gaps” (2021).
Weiss, dkk menyatakan, dengan kait-mengkait tujuan ekonomi dan sosial tadi, inovasi di sektor kehutanan adalah “inovasi sosial”. Inovasi ini mesti mengatasi masalah sosial dan ekonomi untuk kepentingan masyarakat luas. Karena itu inovasi sosial di sektor kehutanan mesti melibatkan berbagai aktor yang relevan, menjalankan perangkat tata kelola partisipatif dan lebih fokus pada manfaat ekonomi dan/atau sosial secara regional.
Ada anggapan bahwa segala praktik teknis kehutanan sudah tidak menjadi masalah mendasar, sehingga fokus perhatian mestinya bergeser kepada praktik sosial, hambatan secara kognitif serta pengendalian perilaku yang menghentikan inovasi akibat perubahan kelembagaan pengelola hutan.
Menurut saya, pandangan Weiss, dkk itu sejalan dengan kondisi umum hutan di Indonesia. Saat ini, selain kawasan hutan yang dikelola oleh swasta yang relatif tidak berhubungan secara langsung dengan masyarakat, standar kelembagaan baku yang sedang berjalan memerlukan penyesuaian. Terutama terhadap kondisi sosial yang muncul.
Kecuali di wilayah dengan modal sosial yang sudah terbentuk, sikap masyarakat pada umumnya cenderung mengikuti kebutuhan jangka pendek. Semakin rendah fungsi hutan memenihi kebutuhan ekonomi mereka, semakin rendah pula apresiasi masyarakat terhadapnya. Ini perlu menjadi pertimbangan karena pengelola hutan sering kali tidak bisa menjangkaunya. Padahal, modal sosial masyarakat adalah perlindungan hutan terbaik.
Weiss, dkk juga menyebut bahwa inovasi sosial di sektor kehutanan itu memerlukan pengetahuan baru—terutama analisis kondisi sosial masyarakat maupun pengetahuan di tingkat sistem seperti manajemen transformatif. Pengetahuan baru ini, selain bisa menambah modal analisis, sebaliknya juga bisa bertentangan dengan apa yang sudah diketahui dan diyakini para rimbawan selama ini. Hal ini berpotensi menjadi tantangan tersendiri, terutama apakah para perencana pengelolaan hutan sudah siap menjalankan cara pemikiran baru itu.
Berikut empat catatan krusial bila pendekatan inovasi sosial dijalankan dalam kebijakan pengelolaan hutan Jawa, dalam lingkup Perhutani yang selama ini mengelolanya maupun KHDPK:
Pertama, membangun modal sosial. Manajemen transformatif lebih cepat berhasil apabila perubahan diiringi dengan distorsi informasi seminimal mungkin. Desas-desus yang mengiringi kebijakan perlu segera diimbangi dengan penjelasan resmi melalui berbagai sarana maupun jaringan. Sarana dan jaringan itu, bila belum tersedia, perlu dibangun yang sejalan pula dengan upaya untuk menumbuhkan modal sosial tadi.
Untuk membangun modal sosial perlu kecakapan serta pemetaan sosial guna menghasilkan rasa saling percaya serta komitmen para aktor pengelolaan hutan dalam menjalankan program jangka panjang. Dalam pemulihan hutan, misalnya, perlu disertai harapan terhadap manfaat nyata secara finansial dari kegiatan itu. Tanpa benefit ekonomi, pemulihan hutan tak akan terjadi secara sukarela.
Di sini pedoman teknis kegiatan atau proyek tidak bisa sepenuhnya dipakai. Untuk itu perencanaan dan pengawasan terhadap kegiatan atau proyek juga perlu disesuaikan. Logika inovasi sosial adalah menyesuaikannya dengan hasil akhir, bukan sekadar memenuhi pedoman dan administrasi belaka.
Kedua, koreksi modal sosial. Di Jawa tidak semua modal sosialnya berwujud hubungan-hubungan sosial secara akuntabel. Dalam kasus-kasus tertentu di Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMHD), misalnya, ada praktik pungutan secara personal, LMDH dikuasai elite tertentu, sharing produksi yang tak adil, maupun problem legalitas. Secara keseluruhan asas akuntabilitas belum terbentuk sehingga mengelola hutan tak memberikan manfaat bagi perusahaan, kelompok masyarakat, maupun perorangan.
Untuk itu, perlu dua langkah. Pertama, memastikan bahwa Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) sebagai unit kerja yang bertanggungjawab atas kinerja LMDH melakukan identifikasi dan penetapan tipologi LMDH di wilayah kerjanya. Pemetaan ini perlu untuk sekaligus mengevaluasi KPH mana yang memiliki kapasitas dalam menjalankan hubungan dengan LMDH secara akuntabel. Kedua, mendalami hasil identifikasi oleh KPH itu untuk menentukan langkah-langkah apa yang diperlukan yang secara spesifik dipengaruhi oleh kondisi setempat.
Ketiga, identifikasi akar masalah dan model kepemimpinan KPH. Perlu ada kesepakatan bahwa pekerja yang menyimpang dari pedoman kerja bukan hanya karena perilakunya, tetapi akibat sistem kerjanya. Ini perlu analisis sebab dan akibat untuk menentukan solusi. Masalah, dengan demikian, dikonstruksikan di dalam pikiran, bukan semata dipotret dengan kamera. Tidak ada pedoman standar yang berlaku sepanjang pola pikir pelaksananya tidak mengikutinya.
Kepemimpinan model ini bukan hanya bekerja atas dasar kewenangan/kekuasaan yang sah, lebih sering karena kepercayaan dan integritas para pemimpin. Perintah bisa berjalan secara efektif bukan hanya oleh “tugas atasan yang sah”, tetapi karena tugas tersebut masuk akal dan pemberi tugasnya bisa dipercaya. Ciri kepemimpinan seperti ini diperlukan dalam sebuah kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Masyarakat biasanya punya stigma buruk terhadap pemimpin kegiatan yang tak bisa dipercaya sehingga melahirkan kebohongan berbungkus kepatuhan.
Untuk membangun kepemimpinan perlu “struktur”. Struktur bisa berupa indikator kinerja, insentif, akuntabilitas, serta bangunan pengetahuan yang mengalir dari lapangan (fakta) menuju ke sistem perencanaan dan administrasi kerja. Ini untuk menghindari sistem perencanaan dan administrasi kerja yang dibangun dengan logika dan asumsi balik meja tanpa melihat kondisi dan keadaan lapangan sesungguhnya.
Membangun struktur biasanya perlu waktu lama. Manajemen proyek atau kegiatan perlu memiliki sistem untuk “selalu belajar dari kesalahan” sehingga perlu “gaya pengawasan/audit” yang berbeda. Audit bukan hanya soal kesesuaian antara perencanaan dan aktualisasinya, tetapi juga mampu mengidentifikasi akar masalah yang jadi penyebab kegagalan atau kemandekan sebuah kegiatan.
Sebagai ilustrasi, dulu ada majalah Tectona yang memuat sintesis masalah pengelolaan areal Perhutani dari “Mantri Hutan”. Para mantri hutan harus mengisi buku harian dengan temuan-temuan di lapangan. Keberhasilan dan kegagalan lalu dievaluasi untuk menjadi pelajaran bagi seluruh jajaran manajemen.
Untuk saat ini, mantri hutan hanya perlu mengisi apa yang terjadi di areal kelolanya di aplikasi. Sehingga data tersebut menjadi bahan analisis yang bisa cepat dipakai sebagai basis mengetahui problem untuk segera dicarikan solusinya.
Terakhir, keberlanjutan inovasi. Dalam “Social Innovation in the Public Sector: An integrative framework”, Bekkers, dkk (2013) menulis cara mencapai dalam inovasi perlu ditopang berbagai nilai demokrasi, yaitu akses masyarakat yang setara, partisipasi dan pemberdayaan, transparansi, akuntabilitas, serta benefit ekonomi. Inovasi harus sah dan berkelanjutan secara politik, sehingga mampu menarik dukungan dan otoritas lembaga resmi.
Keempat hal itu menunjukkan inovasi pengelolaan hutan tidak hanya ditentukan oleh peraturan-perundangan dan administrasinya, juga oleh bentuk kelembagaan dan kapasitas kepemimpinan serta penggunaan ilmu pengetahuan dalam kebijakan yang berubah. Dalam hal hutan Jawa, kelembagaan KHDPK perlu empat hal tadi jika kelak mulai berjalan di awal 2023.
BERSAMA MELESTARIKAN BUMI
Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.
Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.
Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.

Guru Besar Kebijakan Kehutanan pada Fakultas Kehutanan dan Lingkungan serta fellow pada Center for Transdiciplinary and Sustainability Sciences, IPB.
Topik :
















