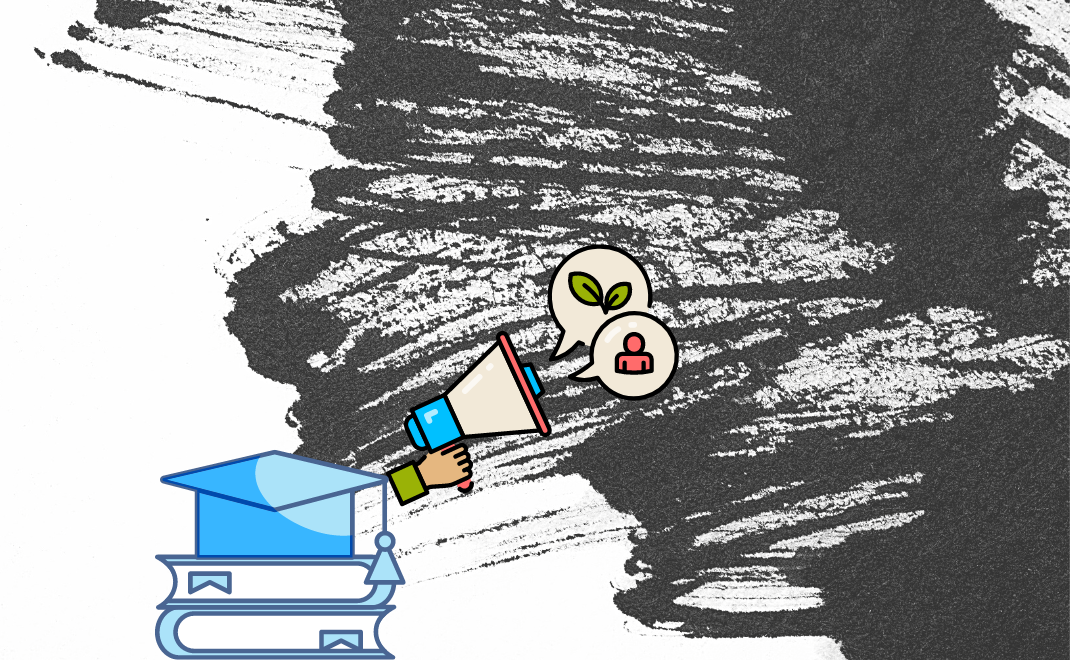
ACUAN negara memajukan masyarakat umumnya melalui pembangunan padat modal, yang di dalamnya memasukkan teknologi. Model pembangunan seperti ini lebih bersifat individual dengan asumsi bisa menyejahterakan masyarakat. Apa pun kondisi awalnya, masyarakat di kampung-kampung metropolitan atau di pedalaman diminta menyesuaikan dengan pendekatan itu.
Sering kali apa yang mereka alami tidak bisa dikompensasi oleh hasil-hasil pembangunan padat modal tersebut. Sebab pendekatan itu juga memberi dampak negatif bagi lingkungan hidup.
Tentu saja peraturan dan prosedur administrasi untuk mengatasi dampak negatif telah disiapkan, bahkan mungkin sudah dilaksanakan. Studi dampak lingkungan, misalnya, memberi keleluasaan pada teknologi untuk memperbaiki bahkan bisa mengubah proses produksi agar dampak lingkungannya minimal.
Nyatanya, tatanan seperti itu tergantung pada kekuatan investasi dalam skema neoliberal yang akan mempengaruhi keputusan dan tindakan pemerintah. Pada titik ini, keahlian menyusun berbagai bentuk studi lingkungan akan kehilangan manfaat. Di sini isu etika lingkungan para ilmuwan serta lembaga pendidikan tinggi atau universitas menjadi sangat krusial.
Akumulasi pengetahuan dalam berbagai penelitian obyektif mendapat tantangan secara sistematis. Akibatnya, kemajuan ilmu sebuah universitas tidak akan bermanfaat dalam mengendalikan kerusakan lingkungan. Kesan ini mencuat ketika saya mengikuti diskusi Pengembangan Profesi Berkelanjutan (PPB) oleh Perkumpulan Tenaga Ahli Lingkungan Hidup Indonesia pekan lalu.
Michel Foucault, dalam wawancara panjang “Truth and Power”, menggambarkan tokoh-tokoh intelektual tradisional sebagai pembawa “kesadaran universal”, dengan publikasi ilmiah sebagai bentuk ekspresi utama. Namun, dalam masyarakat kapitalis modern, kesadaran universal itu acap bertempur dengan “politik kebenaran” yang dibawa para ahli yang melayani kepentingan kapital.
Bagi Foucault, masyarakat kapitalis modern merupakan arena pertempuran antara kebenaran dan peran politik serta ekonomi. Dalam pertempuran itu kebenaran sering kali bukan atas dasar “fakta yang bicara”, tapi mobilisasi kepentingan.
Panagiotis Sotiris, guru besar filsafat politik dari Yunani, dalam “University Movements as Laboratories for (Counter) Hegemony” (2013), menyitir dua pendapat mengenai posisi ahli dan tempat mereka bekerja.
Pertama, gagasan Immanuel Kant tentang universitas yang mengurai ketegangan antara intervensi pasar dari masyarakat kapitalis dan intervensi pasar dari kekuasaan negara versus mengartikulasikan kritik rasional masyarakat kontemporer.
Kant menyebut universitas sebagai tempat nalar publik yang berusaha mengakomodasi kebutuhan produksi pengetahuan masyarakat (borjuis), di sisi lain berusaha mengatasi intervensi politik. Dalam banyak kasus, tarik-menarik ini cenderung disikapi secara taktis dengan membiarkan manipulasi politik berada dalam sinergi atau kadang-kadang kepentingan publik jadi senjata untuk menghadapi dua sisi ini.
Kedua, Jacques Derrida yang menawarkan tanggung jawab universitas. Bagi Derrida, memikirkan universitas dalam kondisi tanpa syarat berarti memikirkan kembali potensinya melahirkan nalar kritis. Tapi universitas juga rentan terhadap pengaruh kekuatan pasar yang membahayakan gagasan pendirian universitas itu sendiri.
Karena independensi itu, menurut Derrida, universitas menjadi benteng terbuka yang “ditenderkan”. Dalam tender itu para ilmuwan kadang-kadang menawarkan diri untuk dijual, diambil alih, lalu dibeli oleh kekuatan lain di luar kepentingan ilmu pengetahuan.
Karena itu Derrida menganjurkan agar para ilmuwan, terutama di bidang humaniora, memiliki tanggung jawab moral tertentu. Komitmen etis dan perlawanan terhadap kekuatan pasar tidak hanya terbatas pada teori, tetapi usaha membentuk aliansi dengan kekuatan di luar universitas.
Secara moral, kata Ellen M. Maccarone dalam “The Moral Case for Scientists as Advocates for Environmental Policy” (2013), para ilmuwan mesti memiliki aliansi dengan kekuatan di luar komunitasnya, misalnya, dengan menjadi pendukung atau advokat kebijakan lingkungan. Maccarone punya tiga alasan:
Pertama, karena ilmuwan juga warga negara. Tidak pantas mereka menolak kesempatan mengadvokasi hal-hal yang mereka anggap penting. Kedua, para ilmuwan yang memiliki keahlian di bidang kebijakan lingkungan harus mengadvokasi posisi-posisi yang memerlukan pengetahuan mereka. Ketiga, advokasi tak harus objektif, seperti penelitian ilmiah. Ilmuwan tidak harus netral bahkan harus berpihak pada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.
Pandangan Maccarone itu membawa konsekuensi tak perlu ada pembatasan bagi para ilmuwan. Jika mengikutinya, para ilmuwan tak perlu dipaksa melakoni siklus rutin ini: meneliti, mempublikasikan hasilnya, lalu mensosialisasikan temuannya. Sebab, jika peran ilmuwan cukup hanya seperti itu, universitas justru sedang mengisolasi ilmuwan dari dunia nyata. Mantra di kalangan ilmuwan bahwa ahli harus netral bahkan apolitis tidak berlaku lagi.
Mantra itu akan menjauhkan para ahli dari tindakan kritis yang bertujuan mengubah masyarakat secara keseluruhan. Teori kritis pada dasarnya berusaha menemukan asumsi-asumsi dasar yang menghalangi orang sepenuhnya memahami bagaimana dunia ini bekerja.
Hal itu berarti universitas perlu merespons dengan memperluas batas-batas kerja akademisi, termasuk ritual penelitian akademik formal yang menghilangkan kontak dengan urgensi penyelesaian persoalan sosial dan politik yang mendesak.
BERSAMA MELESTARIKAN BUMI
Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.
Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.
Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.

Guru Besar Kebijakan Kehutanan pada Fakultas Kehutanan dan Lingkungan serta fellow pada Center for Transdiciplinary and Sustainability Sciences, IPB.
Topik :
















