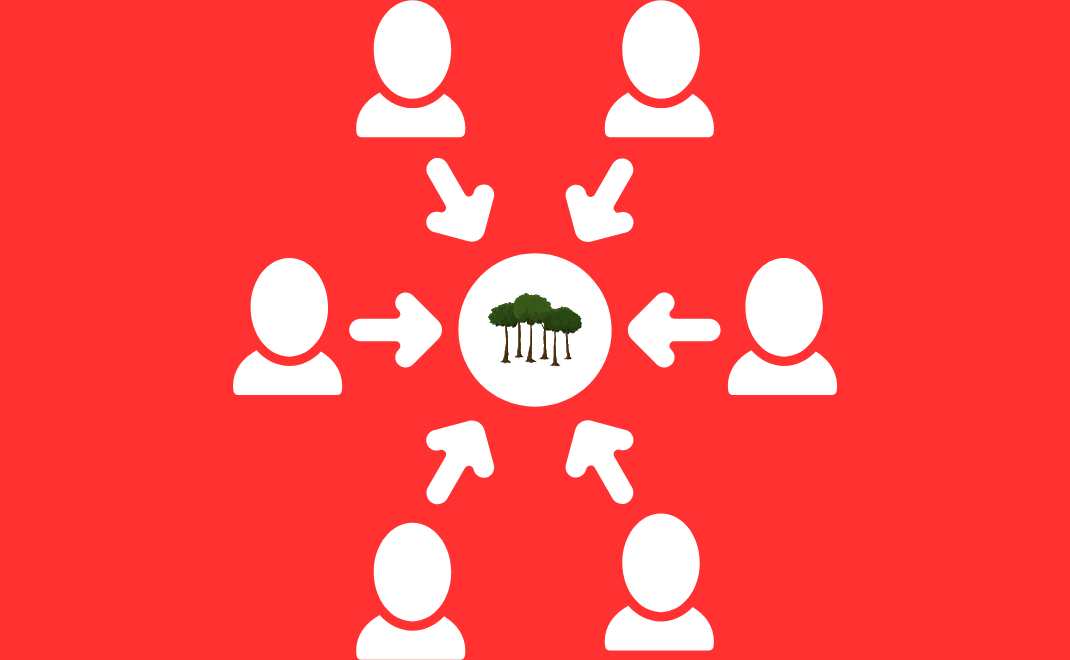
SAMPAI akhir tahun lalu, beberapa inisiatif telaah kebijakan publik mempertanyakan ulang seberapa besar kesesuaian antara konsep dan pelaksanaannya. Misalnya, regulasi pemanfaatan hutan seharusnya mampu menopang manajemen hutan berkelanjutan. Maksud pernyataan itu tak hanya mempersoalkan hutan itu berkelanjutan atau tidak, tetapi hendak mendalami mengapa suatu kebijakan, meski disusun dengan logika valid, tidak bisa berjalan mencapai tujuannya.
Pertanyaan itu kini semakin penting karena kian banyak kebijakan terbukti tidak selalu menghasilkan kinerja yang diharapkan. Untuk pengelolaan hutan alam produksi, misalnya, konsesi hutan alam 30 juta hektare telah ditinggalkan oleh pengelolanya. Untuk hutan tanaman di pulau Jawa yang dikelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kehutanan dari 2,5 juta hektare tinggal 1,3 juta hektare. Di sisi lain, swasta memproduksi 45 juta m3 tiap tahun kayu dari hutan tanaman untuk bahan baku pulp dan kertas.
Apa yang menjadi kriteria implementasi sebuah kebijakan? Mengapa segenap peraturan bisa menjadi penuntun mewujudkan manfaat tertentu dan berhasil bagi pihak tertentu, tapi gagal bagi pihak lainnya. Mengapa hutan alam produksi yang pada awal tahun 1990 dikelola perusahaan swasta berjumlah 580 perusahaan dengan luas 61,48 juta hektare, kini tersisa kurang dari separuhnya.
Sabatier dan Mazmanian (1983) dalam naskah Helga Pulzl dan Oliver Treib di buku “Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods” oleh Frank Fisher, dkk (2015), coba menelaah bagaimana membangun model implementasi yang efektif. Menurut mereka, implementasi kebijakan yang efektif seperti itu memerlukan syarat, yaitu: tujuan kebijakan jelas dan konsisten, program berdasarkan teori kausal yang valid, proses implementasi berjalan dengan baik, pejabat pelaksana berkomitmen dengan tujuan program, kelompok kepentingan dalam tubuh eksekutif dan legislatif mendukung, tidak ada perubahan yang merusak dalam kondisi kerangka sosial ekonomi yang ada.
Dalam pengusahaan hutan, keenam hal tersebut cenderung dikerdilkan oleh kebutuhan pertanggungjawaban administrasi, sehingga kenyataan di lapangan sangat minimal dipertimbangkan dan menjadi fokus dalam pembuatan kebijakan. Dalam implementasinya, kapasitas pembiayaan untuk mengontrol pelaksanaan kebijakan di lapangan cukup rendah, relatif terhadap besarnya kebutuhan terkait luasnya wilayah yang diawasi.
Yang lebih penting, walaupun secara hukum hutan alam produksi itu milik negara, sistem pengelolaan yang berjalan tidak menempatkan hutan alam itu sebagai aset yang harus dipertanggungjawabkan oleh pengusaha apabila tidak bisa dipertahankan keberadaannya. Dengan sekitar 30 juta hektare hutan alam produksi jadi usaha kehutanan yang tidak produktif atau dikonversi menjadi usaha lain, artinya sistem tebang pilih tidak dilaksanakan. Kenyataan itu berlalu begitu saja, seolah tidak ada yang dirugikan, dan tidak ada pelajaran berharga dari kejadian tersebut.
Pendekatan kebijakan “atas-bawah” seperti yang diterapkan dalam kebijakan kehutanan di Indonesia saat ini tidak cukup membawa hasil. Menghadapi kenyataan seperti ini, sebagaimana dinyatakan oleh Sabatier dan Mazmanian, kontrol yang sempurna atas proses implementasi kebijakan dalam praktiknya sulit terwujud. Mereka berpendapat para pembuat kebijakan tidak selalu bisa memastikan implementasi kebijakan yang efektif.
Di Indonesia, sebagian besar pembahasan kebijakan bukan mengenai bagaimana praktiknya kemudian, tetapi lebih berkaitan dengan dasar-dasar dan batasan substansi hukum. Adapun praktik yang dilakukan oleh lembaga negara berjalan dengan logika administrasi, sehingga walaupun penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan, tetapi belum tentu menjawab persoalan di lapangan.
Lipsky (1980) dalam karyanya yang terkenal “Street Level Bureaucracy: The Dilemma of Individuals in the Public Services” menganalisis perilaku pegawai untuk pelayanan publik seperti guru, polisi, pegawai di lembaga pemerintah dan lain-lain, yang ia sebut sebagai “birokrat jalanan” (street-level bureaucracy). Ia berpendapat analisis kebijakan perlu mempertimbangkan interaksi langsung antara pegawai pemerintah dan warga negara.
Dalam praktiknya, kekuasaan yang dimiliki oleh birokrat berada di luar kontrol warga negara. Mereka dianggap mempunyai otonomi besar yang isa melampaui fungsi organisasi tempat mereka bekerja. Maka, sumber utama kekuasaan otonom para birokrat itu berasal dari banyaknya keleluasaan yang mereka miliki.
Pendekatan Lipsky itu juga menunjukkan bahwa pendekatan atas-bawah gagal menjelaskan mata rantai hierarki komando. Tujuan kebijakan yang disiapkan dengan baik belum cukup menjamin keberhasilan implementasinya. Untuk itu, dalam mempelajari implementasi kebijakan perlu mengembangkan metodologi pemahaman jaringan aktor, serta karakter multiaktor dalam pelaksanaan kebijakan.
Implementasi kebijakan adalah kontinum di antara pemerintah pusat dan daerah. Helga Pulzl dan Oliver Treib mencatat ada lima hal yang perlu diperhatikan dalam hubungan keduanya.
Pertama, preferensi birokrasi jalanan adalah suatu kenyataan dan harus diperhitungkan dalam pelaksanaan kebijakan. Kedua, implementasi kebijakan sesungguhnya dapat mendorong perubahan karena implementasi adalah proses yang melibatkan berbagai kepentingan yang bisa mendorong kebijakan terbentuk kembali, dirumuskan ulang, bahkan diganti. Ketiga, dari saran pendekatan bawah-atas, implementasi dan proses pembuatan kebijakan saling tergantung. Keempat, pembaruan kebijakan perlu memperhatikan pengaruh luar, termasuk perkembangan ekonomi dan sosial. Kelima, karakter sosial-politik suatu daerah juga penting sehingga negara-negara yang berbeda mempunyai gaya implementasi berbeda pula.
Dalam dunia nyata praktik administrasi publik tidak memiliki hierarki yang ketat daripada yang diasumsikan. Para birokrat di lapangan bisa mempunyai tujuan sendiri daripada tujuan yang ditetapkan oleh kewenangan atau atasannya. Hal itu bisa memunculkan model kemudi kebijakan yang non hierarkis. Hal ini sering disebut “tata kelola jaringan kebijakan” atau sistem yang menegosiasikan kepentingan para aktor dari tingkat yang berbeda-beda, yang kemudian dapat saling bekerja sama.
Berdasarkan pendekatan telaah implementasi kebijakan seperti itu, penyebab manajemen hutan produksi alam dan tanaman yang tidak lestari terjadi karena jaringan kebijakan dalam pengusahaan hutan. Jaringan kebijakan itu berada pada persimpangan pendekatan-pendekatan administrasi publik, teori organisasi, manajemen publik, serta studi ilmu politik.
Maka, daripada hanya fokus pada hutan, pohon, dan aspek sosial serta pengaturannya, wacana mengatur kehutanan ke depan perlu memakai pendekatan multidisiplin yang terkait dengan administrasi, organisasi, manajemen publik, serta ilmu politik. Tanpa pendekatan seperti itu, pengelolaan hutan akan dihadapi dengan cara yang sama seperti dulu yang menghasilkan pengelolaan hutan tak lestari.
Dengan kenyataan separuh lebih luas hutan produksi tidak lagi produktif, pembaruan kebijakan perlu diikuti dengan pembaruan cara berpikir agar pengelolaan hutan tidak mengulang kegagalan di masa lalu.
Ikuti percakapan tata kelola kebijakan publik di tautan ini
BERSAMA MELESTARIKAN BUMI
Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.
Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.
Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.

Guru Besar Kebijakan Kehutanan pada Fakultas Kehutanan dan Lingkungan serta fellow pada Center for Transdiciplinary and Sustainability Sciences, IPB.
Topik :
















