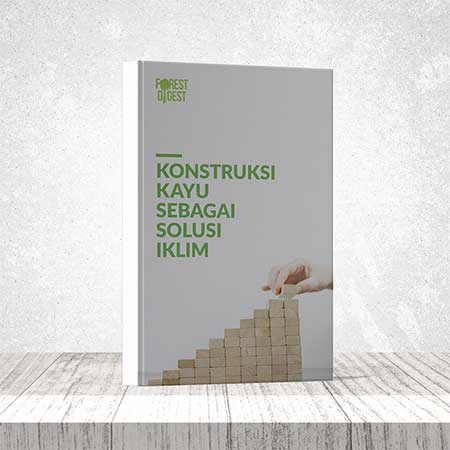Kabar Baru| 02 Juni 2019
Posisi Masyarakat dalam Mengelola Kawasan Konservasi
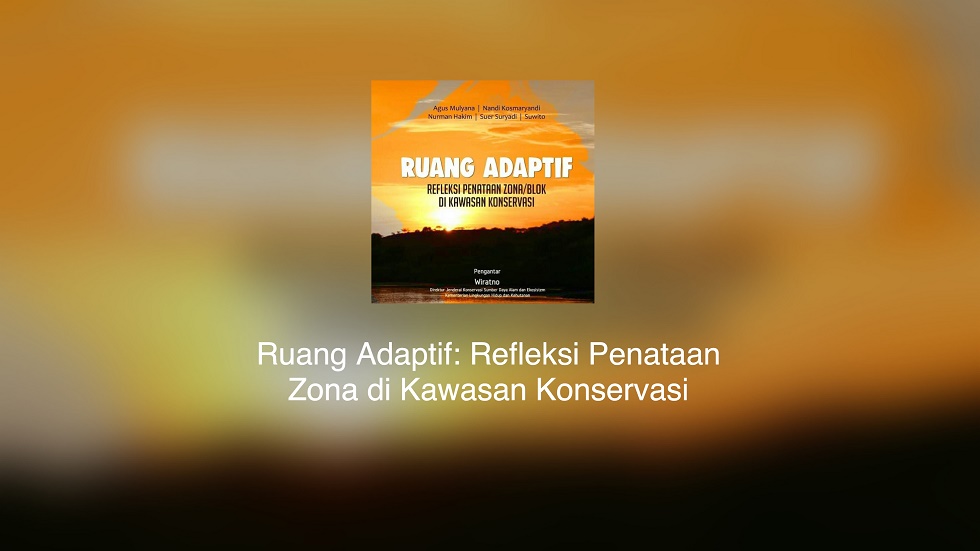
JUDUL-judul buku yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terasa lebih segar dalam tiga tahun terakhir. Tak lagi memakai kata-kata birokrat yang kaku, yang menggelembung tapi hampa, yang kosong makna karena klise. Seperti buku baru yang diterbitkan KLHK atas sokongan Yayasan Rakyat Amerika (Usaid), 29 Mei 2019.
Judulnya “Ruang Adaptif: Refleksi Penataan Zona/Blok di Kawasan Konservasi”. Judulnya menjanjikan karena terasa ada upaya untuk kian mendekatkan problem pelik mengelola kawasan konservasi kepada pembaca lewat gaya populer. Sebab, buku adalah anasir propaganda, alat penyampai pesan. Jika ia tak bisa dibaca karena ditulis dengan gaya yang kaku dan kering, propaganda dan komunikasi itu telah gagal sejak awal.
Kehutanan dan lingkungan terlalu penting untuk dikampanyekan dengan gaya kaku. Ia harus menjadi bagian dari paradigma setiap orang Indonesia. Problem-problemnya harus bisa dipahami awam agar kampanye partisipasi bisa lebih efektif. Lingkungan dan kehutanan harus menjadi pusat perhatian orang Indonesia orang seorang karena mengabaikannya berakibat pada bencana yang tak terperi. Eksploitasi hutan selama puluhan tahun telah mengakibatkan bencana yang merebak di mana-mana.
Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Wiratno—yang memberi pengantar buku ini—menyebut eksploitasi hutan secara masif itu mengakibatkan fenomena “Island Ecosystem” dan “fragmentasi habitat”. Dari 22,12 juta hektare kawasan konservasi daratan, 12,6 persennya kini menjadi kawasan terbuka akibat perambahan untuk perkebunan, pertanian lahan kering, pembalakan liar, hingga penambangan liar. Pembangunan secara teknokratik dan berorientasi pada kemajuan ala urban membuat bencana lingkungan yang sulit dipulihkan, karena merambah pula ke kawasan-kawasan konservasi.
Sejak 1996, pemerintah telah mengatur kawasan konservasi dengan sistem zonasi—membagi-bagi kawasan hutan berdasarkan fungsinya: zona inti, rimba, dan buru. Zonasi ini lalu diterjemahkan dalam pelbagai status hutan. Dari cagar alam, suaka, hingga taman nasional. Belakangan konsep zonasi itu meluas dengan melibatkan peran-peran masyarakat di sekitar hutan sebagai subjek penjaga kawasan.
Pada 2017, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan buku kecil berjudul “10 Cara Baru Mengelola Kawasan Konservasi” (silakan klik judul itu untuk mengunduh versi pdf). Isinya strategi-strategi pemerintah menjaga kawasan konservasi dengan mengubah paradigma lama yang memberikan peran sentral kepada negara. Dalam cara baru itu, peran komunitas dan masyarakat lebih diutamakan. Masyarakat dan penghormatan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat dalam strategi pertama dan kedua.
Para penulis buku ini merujuk jauh ke dalam prasasti-prasasti dan praktik-praktik lama dalam kearifan lokal masyarakat adat sebagai referensi karena mereka terbukti kontinu dan stabil melakukan cara-cara konservasi seperti yang dipraktikkan Raja Sriwijaya di abad ke-6. Pertanyaannya, bagaimana cara praktis dan teknis penerapannya di lapangan? Ruang Adaptif merujuk pada cara ketiga: kerja sama lintas eselon I di KLHK, yakni kerja sama Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dengan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
Dari total 27,14 juta hektare kawasan konservasi—9 kali luas Jawa Barat—yang tersebar di 552 unit terdapat 6.381 desa dan 134 komunitas adat. “Kenyataan ini memunculkan kesadaran kita bersama bahwa pengelolaan Kawasan Konservasi tidak lagi hanya berkutat pada aspek keanekaragaman hayati bersama atribut fungsi ekologisnya, tetapi juga tentang relasi-relasi sosial terhadap kawasan yang melibatkan segala aspek kehidupan masyarakat di sekitarnya,” tulis Wiratno.
Masyarakat adat—di dalam maupun di luar kawasan hutan—berada dalam kewenangan Ditjen PSKL. Hutan adat bahkan menjadi salah satu dari lima skema perhutanan sosial. Ini program nasional yang memberikan pengakuan hak mengelola hutan selama 35 tahun agar masyarakat di sekitarnya mendapatkan manfaat sosial, ekonomi, dan ekologi. Setelah melalui sejarah yang panjang, untuk pertama kalinya masyarakat adat diberikan hak secara resmi mengelola hutan mereka, bahkan ekosistem mereka dipisahkan dari hutan negara lewat putusan Mahkamah Konstitusi pada 2012.
Untuk masyarakat adat, pemerintah sudah meluncurkan Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase I pada 27 Mei 2019 seluas 472 ribu hektare. Pemerintah akan memperbarui peta tersebut tiap tiga bulan jika ada usulan-usulan baru yang diterima. Soalnya, untuk mendapatkan penetapan sebagai hutan adat, masyarakat harus menempuh tahap-tahap verifikasi dan sertifikasi sejak pemerintah daerah.
Agaknya, dengan melihat kemajuan-kemajuan itu, problem koordinasi di KLHK relatif terpecahkan dalam konteks menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama kawasan konservasi. Buku Ruang Adaptif masih memberikan catatan pada kerja sama lintas kementerian (halaman 93) yang belum mulus. Pengaturan masyarakat adat tak hanya berada dalam lingkup kehutanan, tapi juga diatur dalam Undang-Undang Desa, termaktub dalam kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, bahkan ada urusan Kementerian Dalam Negeri yang menaungi urusan pemerintah daerah.

Taman Nasional Ujung Kulon
Masalahnya, di luar soal datanya yang kaya, buku ini terlalu mengabstraksi problem-problem lapangan dalam menerapkan aturan sistem zonasi kawasan konservasi. Karena abstraksi, ia penuh dengan rumusan-rumusan ilmiah, sehingga kita tak tahu problem nyata yang sesungguhnya dalam sengkarut penerapan kebijakan itu. Buku ini kurang menyajikan cerita-cerita riil yang dihadapi petugas dan masyarakat dalam tarik-menarik kepentingan melihat hutan.
Sebab, di setiap kawasan konservasi tak hanya ada masyarakat adat. Eksploitasi yang panjang mendorong perusahaan-perusahaan masuk ke sana dan kini menjadi para pihak yang punya kepentingan atas kawasan hutan. Suara-suara mereka, yang mengakibatkan problem pelik relasi negara-masyarakat, tak mendapat tempat secara utuh.
Ada memang contoh orang Rimba di Jambi yang menuntut ruang adat lebih longgar ketika pemerintah membuat zonasi Taman Nasional Bukit Dua Belas. Tapi cerita mereka pun diabstraksi menjadi problem semata tanpa menyajikan masalah nyata yang menjadi keinginan mereka.
Problem utama laporan ilmiah memang minim menyajikan cerita manusia, yang dekat, yang riil, yang bisa menjadi pembelajaran untuk wilayah-wilayah lain. Buku ini menyajikan problem untuk perbaikan, tapi problem itu sulit diraba dan dipahami oleh orang awam yang tak berkecimpung dalam urusan konservasi. Padahal, seperti disebut di awal-awal buku ini, urusan lingkungan adalah masalah tiap-tiap orang.
Barangkali ini kecenderungan umum laporan-laporan mengenai hutan dan lingkungan. Isu penting ini tak disajikan secara evokatif ke khalayak karena mengabaikan soal pokok dalam pengelolaannya: problem manusia dan lingkungan yang dinarasikan dengan cara bercerita. Sebab, dengan teknik pengisahan, masalah dibumikan dengan problem nyata sehari-hari yang menimpa masyarakat sebagai subjek pengelolaan hutan dan lingkungan.
Kisah-kisah itu akan menjadi pembelajaran di tempat lain di waktu yang lain untuk mengail solusi yang mungkin dan relevan.
BERSAMA MELESTARIKAN BUMI
Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.
Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.
Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.

Redaksi
Topik :