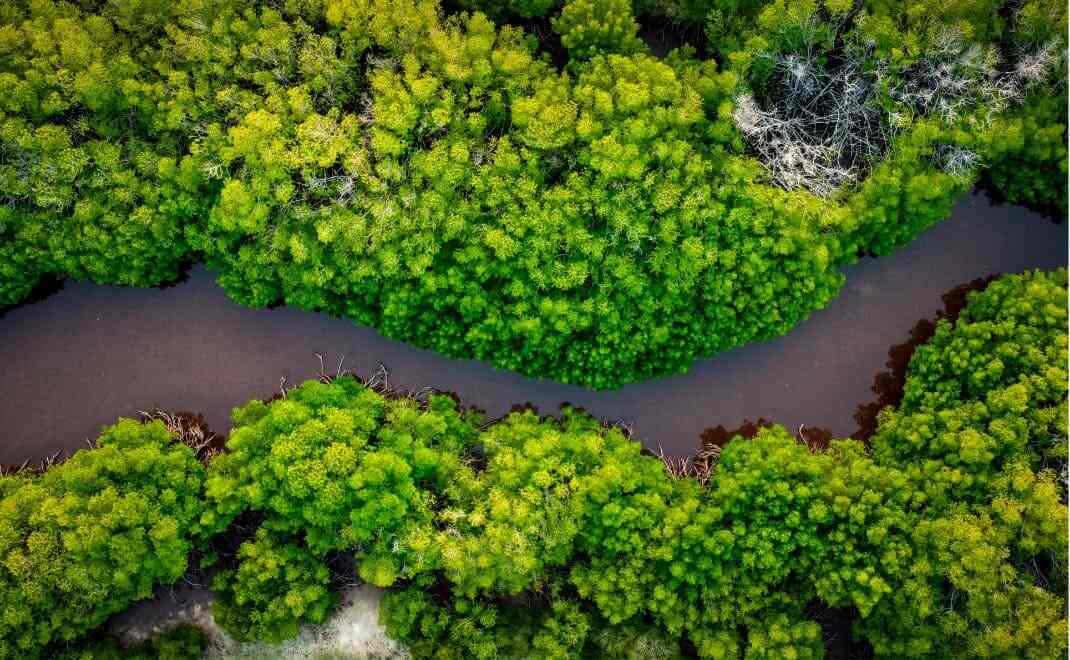
PEMANFAATAN kayu dari hutan alam membuat potensinya surut. Pemanfaatan hutan alam pun kini perlu beralih dengan mengeksplorasi sektor jasa lingkungan yang belum banyak tergarap.
Pada 1970-1980, potensi kayu hutan tropis Indonesia bisa mencapai 150 meter kubik per hektare. Saat ini menurun tinggal 30 meter kubik per hektare. Karena itu perlu transformasi pemanfaatan hutan dari kayu ke jasa lingkungan. Mengapa baru sekarang?
Undang-Undang 5/1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan telah mengamanatkan manfaat hutan tidak sekadar ditinjau dari aspek ekonomi, juga aspek sosial, ekologi, hingga kelestarian. Penerbitan PP 21/1970 diikuti Surat Keputusan Direktur Jenderal Kehutanan tahun 1972 tentang kelestarian hutan melalui penerapan silvikultur hutan alam yakni sistem tebang pilih Indonesia (TPI), tebang habis permudaan buatan (THPB), dan tebang habis permudaan alam (THPA). Faktanya, potensi hutan alam Indonesia dalam setengah abad menyusut drastis tinggal 30 meter kubik per hektare.
Secara ekonomis, apabila potensi hutan alam yang rendah tersebut akan diusahakan melalui pemanfaatan kayunya, jelas tidak menguntungkan bagi perusahaan atau korporasi. Bagaimana semua ini dapat terjadi pada hutan alam Indonesia yang luasnya mencapai 120,3 juta hektare atau lebih dari 60 persen daratan Indonesia, secara de jure?
Ada dua manfaat hutan, yakni manfaat langsung (tangiable) dan manfaat tidak langsung (intangiable). Pemanfaatan langsung hutan selama ini diukur dan dilakukan melalui pendekatan nilai ekonomi yang bersifat kuantitatif yang mendatangkan nilai rupiah atau dolar. Sementara itu pemanfaatan tidak langsung diukur dan dimanfaatkan melalui pendekatan kelestarian (sustainable) ekosistem yang sebenarnya sulit atau tidak mudah diukur dengan nilai ekonomi karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Pengelolaan hutan alam di Indonesia, khususnya hutan alam produksi lebih dari setengah abad yang lalu sejak diizinkannya HPH dan HPHH pada 1970 hingga saat ini, pada prinsipnya tidak banyak berubah, yakni pada pendekatan ekonomi kuantitatif semata.
Awal 1970, kita mengenal kawasan hutan alam Indonesia seluas 122 juta hektare yang tersebar dari ujung barat Sumatera sampai ujung timur Papua. Hutan alam Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan mempunyai potensi jenis Dipterocarpaceae (Meranti sp) yang laku dalam perdagangan kayu dunia.
Permintaan akan kayu meranti dipasar internasional cukup tinggi. Bonanza kayu oleh rezim Orde Baru selama tiga dekade dimanfaatkan benar sebagai penggerak roda pembangunan, dan merupakan penyumbang devisa negara nomor dua setelah minyak bumi. Akibatnya hutan alam dieksploitasi habis-habisan untuk diekspor kayunya dalam bentuk bahan mentah log (gelondongan). Izin pengusahaan kayu alam dalam bentuk HPH (Hak Pengusahaan Hutan) baik asing maupun domestik terus bertambah. Produksi kayu lapis Indonesia pernah tercatat merajai dan menguasai pasar kayu tropis (hardwood) dunia pada 1990-1995.
Sektor kehutanan bahkan menyumbangkan devisa sebesar US$ 16 miliar per tahun. Pada 2000, misalnya, jumlah hak pengusahaan hutan (HPH) sekitar 600 unit dan mengusahakan areal hutan lebih dari 64 juta hektare. Devisa itu hampir setara devisa minyak bumi US$ 9 miliar per tahun terhadap pendapatan nasional.
Meskipun Orde Baru runtuh, HPH berubah nama dan berganti baju menjadi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), dan hutan tanaman industri (HTI) berubah menjadi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman (IUPHHK-HT), cara mengeksploitasi hasil hutan kayu alam tidak berubah.
Seiring pudarnya kejayaan kayu, banyak IUPHHK yang habis kontrak, izinnya tidak diperpanjang oleh pemerintah akibat banyaknya aturan yang dilanggar bahkan tidak aktif lagi karena produktivitas hutan alam setelah rotasi kedua menjadi sangat rendah atau bahkan tidak ekonomis untuk diusahakan.
Jumlah IUPHHK-HA pada 2010 tinggal 304 unit dengan luas areal kerja lebih dari 25,05 juta hektare. Sementara IUPHHK-Hutan Tanaman sebanyak 284 unit dengan areal kerja 12,35 juta hektare. Kinerja produksi IUPHHK-HA selama kurun waktu 2007-2012 terus menurun. Sebagai contoh, kinerja produksi IUPHHK-HA pada dua tahun berturut turut kontribusinya memenuhi kebutuhan bahan baku industri (BBI) nasional menurun dari 19,8% pada 2007 menjadi 14,6% pada 2008.
Sebaliknya kinerja produksi IUPHHK-HT dalam memenuhi BBI nasional pada dua tahun yang sama meningkat dari 63,5% menjadi 68,8% pada 2008. Pada akhir 2022, dari 30,7 juta hektare yang telah mendapatkan izin pemanfaatan hutan, 61% (atau setara dengan 18,8 juta hektare) berupa IUPHHK-HA dan 36% (atau 11,18 juta hektare) berupa IUPHHK-HT.
Ekses dari izin HPH yang tidak terkendali antara lain tidak cermatnya lokasi konsesi. Banyak kawasan hutan yang mestinya berfungsi lindung/termasuk hutan gambut masuk dalam wilayah HPH. Sistem silvikultur TPTI, tebang habis permudaan buatan (THPB), tebang habis permudaan alam (THPA) tidak dipatuhi di lapangan karena pengawasan aparat kehutanan setempat lemah.
Singkatnya, kaidah kelestarian produksi hutan alam tidak berjalan denganbaik. Ditambah lagi alih fungsi lahan hutan yang masif dan skala luasnya makin meningkat. Timbul masalah baru yang sebenarnya sudah diperhitungkan sebelumnya, yaitu bencana ekologis akibat eksploitasi hutan. Kebakaran hutan dan lahan di bekas hutan gambut yang menghasilkan bencana asap, selalu muncul setiap tahunnya memasuki musim kemarau. Pemerintah pusat maupun daerah dibuat kalang kabut untuk mengatasi kebakaran ini. Belum lagi, masalah bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang dan tanah longsor yang selalu mendera secara rutin setiap tahun di beberapa wilayah yang rawan di tanah air, akibat ekosistem lingkungannya yang rusak.
Makin lama, skala dan luasnya bencana hidrometeorologi ini bertambah besar dan meningkat. Di sisi lain, alih fungsi lahan hutan untuk kepentingan nonkehutanan makin marak dan masif demi dan atas nama pembangunan di era reformasi ini. Secara normatif pengertiannya alih fungsi lahan hutan adalah proses pengalihan fungsi lahan hutan dari kegiatan kehutanan untuk kepentingan kegiatan non kehutanan seperti permukiman, perkebunan, pertambangan.
Dalam UU 41/1999, pasal 38 ayat (1) menyebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya bisa dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Mekanisme alih fungsi lahan hutan diatur melalui dua prosedur, yakni pelepasan kawasan hutan dan izin pinjam pakai kawasan hutan.
Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan alih fungsi lahan hutan secara legal sejak Orde Baru hingga 2017 seluas 6,7 juta hektare. Sedangkan alih fungsi lahan hutan yang menjadi kebun sawit bermasalah seluas 3,1 juta hektare, belum termasuk pertambangan ilegal. Ada juga alih fungsi melalui izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) yang telah diterbitkan dari tahun 1979 hingga 2018 seluas 563.463,48 hektare.
Pemerintah dalam memanfaatkan kawasan hutan secara tidak langsung memakai pendekatan lingkungan, sudah sangat terlambat setelah terjadi kerusakan lingkungan di mana-mana khususnya dalam kawasan hutan.
Menurut data tebaru dari KLHK dalam bukunya “The State Of Indonesia’s Forest (SOIFO) 2020 ”, luas hutan Indonesia 120,3 juta hektare, yang terdiri dari hutan primer 43,3 juta hektare, hutan sekunder 37,3 juta hektare, hutan tanaman 4,3 juta hektare dan kawasan hutan nontutupan hutan seluas 33,4 juta hektare.
Kawasan hutan nontutupan yang dipersoalkan seluas 33,4 juta hektare, merupakan lahan-lahan terbuka, semak belukar dan tanah terlantar bukanlah lahan menganggur yang dapat dimanfaatkan apa saja, karena masing-masing kawasan lahan hutan tersebut mempunyai fungsi kawasan masing-masing. Meski kawasan hutan seluas 33,4 juta hektare merupakan kawasan yang tidak mempunyai tutupan hutan (forest coverage), namun kawasan hutan tersebut masuk dalam kawasan hutan konservasi 4,5 juta hektare, hutan lindung 5,6 juta hektare, hutan produksi terbatas 5,4 juta, hutan produksi biasa 11,4 juta hektare dan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 6,5 juta hektare.
Sementara kawasan hutan produksi yang menjadi andalan dalam mendatangkan nilai ekonomi luasnya mencapai 68,80 juta hektare. Dari luas tersebut, yang telah dibebani hak (dengan perizinan) seluas 34,18 juta hektare (izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam (IUPHHK-HA) 18,75 juta hektare dengan 257 unit usaha, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman (IUPHHK_HT) 11,19 juta hektare dengan 292 unit korporasi dan IUPHHK-RE (restorasi ekosistem) seluas 0,62 juta hektare). Sisanya hutan produksi seluas 34,62 juta ha belum dibebani hak (belum ada perizinan).
Sayangnya pemasukan negara dari sektor kehutanan menurun drastis. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku tak habis pikir bagaimana Indonesia yang memiliki hutan sangat luas, namun sumbangan ke keuangan negara sangat kecil. Sektor kehutanan secara keseluruhan, hanya memberikan setoran dalam bentuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 5,6 triliun. Padahal, PNBP Indonesia sekarang sudah mencapai hampir Rp 350 triliun.
Lebih jauh, Menteri Keuangan menjelaskan bahwa setoran PNBP dari hutan ini kurang masuk akal apabila dibandingkan dengan luas hutan Indonesia yang menguasai daratan Indonesia seluas 120,3 juta hektare.
Kegundahan Sri Mulyani masuk akal. Sektor yang tadinya memberikan pemasukan negara sebesar US$ 16 miliar per tahun, sekarang turun menjadi US$ 375 juta saja. Menteri Keuangan memprediksi dominasi PNBP dari basis kayu masih sangat tinggi, namun PNBP sektor kehutanan sangat kecil disebabkan karena kurangnya pengawasan, penegakan hukum yang lemah dan kurang komprehensif dan optimalisasi potensi termasuk aset yang dinilai masih menganggur (idle time).
Konsep menjual hutan/kawasan hutan Indonesia dari pendekatan manfaat tidak langsung datangnya sangat terlambat. Konsep multiusaha kehutanan (MUK) pada dasarnya baik karena mengoptimalkan pemanfaatan lahan kehutanan untuk kegiatan usaha dan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian hutannya, namun sayang dalam situasi iklim usaha nasional yang lesu.
Konsep MUK bagi para pengusaha kehutanan masih sulit diimplementasikan. Faktor agroklimat, tenaga kerja dan padat modal menjadi kendala di lapangan saat ini. Konsep menjual karbon melalui perdagangan karbon meskipun menjanjikan dan nilainya sangat tinggi tampaknya belum menggembirakan apabila melihat data bursa karbon yang dicanangkan Presiden Jokowi bulan September 2023 lalu.
Di sisi lain, pengendalian dan penurunan emisi gas rumah kaca dalam kontribusi nasional yang sudah ditentukan (NDC) membutuhkan anggaran atau dana yang tidak sedikit. Target Indonesia dalam Perjanjian Paris sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional. Dalam COP27 di Sharm El-Sheikh, Mesir (2022), target penurunan emisi menjadi 32,89 persen dengan usaha sendiri dan menjadi 43,2 persen dengan bantuan asing.
Sebagai contoh dalam penurunan emisi gas rumah kaca di sektor kehutanan dalam FOLU Net Sink 2030 yang disusun 2022, penyerapan gas rumah kaca ditargetkan 140 juta ton setara CO2 pada 2030 dan kemudian naik menjadi 304 juta ton setara CO2 pada 2050.
Sektor kehutanan hendak menurunkan emisi gas rumah kaca 17,2% dari 2,87 miliar ton perkiraan emisi 2030 dalam skenario penurunan emisi nasional 29%. Untuk itu dalam dokumen Rencana Operasional Indonesia FOLU Net Sink 2030 disebutkan bahwa total biaya daur hidup yang dibutuhkan untuk kegiatan mitigasi menuju net sink untuk periode 2020-2030 diproyeksikan sebesar Rp 204.02 triliun (Rp 18,55 triliun per tahun).
Total kebutuhan biaya tersebut masih jauh di atas ketersediaan dana (defisit) yang dihitung dari proses pendanaan RPJMN untuk kegiatan mitigasi 2020-2024 Rp 19,61 triliun (Rp 3,92 triliun per tahun) (KLHK, 2021). Jadi, dalam mencapai skenario jangan panjang yang paling ambisius, dijelaskan kembali oleh Indonesia bahwa terdapat kesenjangan dana untuk kebutuhan aksi mitigasi hingga mencapai Rp 74 triliun (Rp 14,8 triliun per tahun).
Belum lagi, kita bicara mengenai kebutuhan penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor lain seperti sektor energi, sektor pertanian, sektor industri dan penggunaan produk (IPPU); sudah barang tentu total defisit pembiayaan penurunan gas rumah kaca secara keseluruhan akan membengkak lebih besar.
Pembiayaan penurunan gas rumah kaca yang diharapkan dari perdagangan karbon melalui bursa karbon ternyata belum dapat terealisasi, sementara pajak karbon yang menjadi penopang utama dalam penurunan gas rumah masih akan berlaku tahun 2025.
Ikuti percakapan tentang hutan tropis Indonesia di tautan ini
BERSAMA MELESTARIKAN BUMI
Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.
Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.
Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.

Pernah bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Topik :












