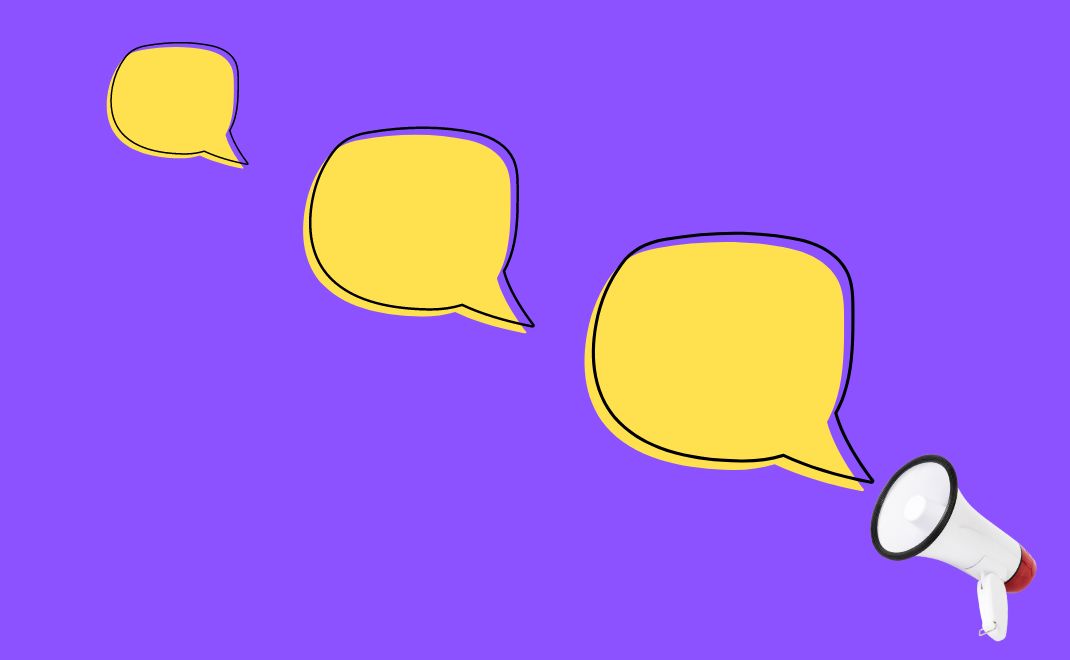
BARU-BARU ini dosen dan guru besar di perguruan tinggi negeri, swasta, dan aktivis lembaga swadaya masyarakat melontarkan kritik keras kepada pemerintah dan proses pemilihan presiden. Setidaknya ada 27 perguruan tinggi negeri, 11 perguruan tinggi swasta, serta lima asosiasi dan perkumpulan komunitas, menyatakan keprihatinan tentang perkembangan politik di sekitar Pemilu 2024 yang berlangsung pada 14 Februari 2024.
Beberapa isu dalam kritik itu, antara lain, penyimpangan nilai-nilai dan prinsip demokrasi, pelanggaran etika, moral berbangsa dan bernegara, keterlibatan pejabat pemerintah dalam kampanye yang melanggar asas netralitas, serta gangguan terhadap kebebasan berekspresi.
Kedua, tuntutan kepada presiden dan jajarannya agar tetap di koridor demokrasi dan menjalankan amanat konstitusi secara berintegritas. Ketiga, tuntutan terhadap aparatur sipil negara, tentara dan kepolisian, serta pejabat publik agar menjunjung netralitas politik, integritas, serta menjunjung profesionalisme.
Keempat, tuntutan terhadap penyelenggara pemilu (Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) agar menjaga pemilu tetap bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kelima, seruan agar masyarakat menggunakan hak pilih dan mengawal pemilu serta menciptakan suasana damai dan kondusif.
Keenam, seruan kepada kalangan intelektual/akademisi untuk bersuara bersama, mengawasi dan mengawal proses demokrasi dalam pemilihan umum. Ketujuh, pemerintah seharusnya mendukung kebebasan berpendapat perguruan tinggi sebagai institusi yang ikut menjaga nilai dan moral pemerintahan.
Forum Keluarga Besar IPB University turut menegaskan bahwa demokrasi harus dijalankan untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan individu, kelompok, maupun penguasa.
Tuntutan dan pendapat seperti itu tidak mudah diwujudkan. Dalam politik, selalu ada kepentingan, meski dengan kadar berbeda-beda. Kepentingan itu dijalankan dengan melanggar atau tidak melanggar peraturan. Menjadi berbahaya jika kehendak melawan seruan berbasis moral itu dilakukan oleh kekuasaan.
Dalam “The Psychology of Freedom” (2017), Craig Hassed menyatakan secara umum manusia menginginkan kebebasan. Kebebasan bukan soal pengekangan secara fisik. Maka Socrates, Boethius, Thomas More, Mahatma Gandhi atau Nelson Mandela dalam banyak hal justru tampak lebih bebas daripada mereka yang memenjarakannya.
Kebebasan sejati pada dasarnya keadaan pikiran. Oleh karena itu olah pikir adalah inti kebebasan. Carl Jung (1875-1961), psikolog Swiss, punya pandangan tentang alam bawah sadar, agama, dan keinginan bebas, yang menghubungkan kita tidak hanya melalui fisik, juga melalui ketidaksadaran kolektif. Jung percaya kehendak bebas adalah cara berpikir.
Misalnya, tiba-tiba saya mendapat dukungan pendapat dari orang-orang yang tak saya kenal. Rupanya mereka membaca artikel-artikel saya. Saya tahu dukungan itu muncul karena kesamaan sikap. Jaring-jaring komunikasi yang menyatukan pendapat itu bisa sangat cair, bisa terjadi dengan siapa saja, kapan saja, di mana saja.
Manusia, kata psikolog Burrhus Frederic Skinner (1904-1990), memang bisa dikondisikan. Pada dasarnya kita seperti mamalia lain yang bisa dilatih sehingga cara pikir pun bisa diformulasikan. Bagi orang seperti itu, melanggar hukum untuk kepentingan tertentu, bisa dianggap sebuah kewajaran karena dia dilatih seperti itu.
Karena itu, kita bisa bertanya pada diri sendiri saat sedang berpendapat. Pendapat kita itu dari mana? Di balik pendapat itu, kita sedang punya kepentingan apa? Apakah pendapat itu murni dari pikiran dan perasaan kita? Apakah pendapat kita karena membela atau menentang pandangan orang lain?
Kebebasan, bagi Viktor Frankl (1905-1997), bukan pengaruh eksternal manusia. Manusia selalu punya pilihan sikap terhadap peristiwa apa pun. Frankl, ketika diminta mengomentari pandangan Skinner, mengatakan “Manusia tidak berhenti menjadi binatang, pada saat yang sama manusia jauh lebih dari sekadar binatang. Segala sesuatu dapat diambil dari manusia kecuali satu hal: kebebasan memilih sikap dalam situasi apa pun, kebebasan memilih jalannya sendiri.”
Penelitian Martin Seligman pada hewan menuntunnya menemukan apa yang disebutnya “ketidakberdayaan yang dipelajari”, yang muncul dari situasi menyakitkan, yang membuat hewan tidak bisa melarikan diri. Maka ketika potensi kabur itu terbuka, ia tak memanfaatkannya.
Seligman menyamakannya dengan orang-orang yang depresi. Dengan kata lain, orang yang sudah terbiasa dalam tekanan, meragukan situasi bebas yang menjadi syarat perbaikan kondisi itu. Secara implisit mereka ini sudah terbiasa menjadi obyek penderita yang ditentukan, bukan subyek yang ikut menentukan.
Dengan memperhatikan kritik berbagai guru besar perguruan tinggi dan masyarakat sipil, bisa kita maknai sebagai sikap yang perlu dicatat dan menjadi perhatian. Tetapi di ruang publik, masyarakat tidak selalu mengambil posisi permintaan tinggi (high call) dalam menuntut hak-haknya. Maka, dalam demokrasi, yang harus dilakukan kekuasaan sesungguhnya sederhana: mendengarkan.
Ikuti percakapan tentang kebebasan berpendapat di tautan ini
BERSAMA MELESTARIKAN BUMI
Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.
Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.
Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.

Guru Besar Kebijakan Kehutanan pada Fakultas Kehutanan dan Lingkungan serta fellow pada Center for Transdiciplinary and Sustainability Sciences, IPB.
Topik :
















