Kabar Baru| 02 Juli 2019
Agroforestri Sawit untuk Menyelesaikan Konflik Lahan. Mungkinkah?

SENGKETA lahan di kawasan hutan menjadi momok serius dalam pengelolaan lingkungan yang lestari, terutama penyerobotan lahan oleh masyarakat maupun perusahaan. Dari 16,6 juta hektare kebun sawit yang ada sekarang, 3,4 juta hektare berada di kawasan hutan. Perambahan terjadi akibat pelbagai kebijakan yang tak sinkron dalam memberikan izin sejak mula, hingga penyerobotan oleh masyarakat akibat euforia reformasi 1998.
Sawit pun menjadi tertuduh utama dalam deforestasi dan degradasi lahan. Uni Eropa sangat keras menentang dan melarang sawit Indonesia. Meski anggota-anggotanya punya alasan berbeda menolak sawit—sehingga memunculkan dugaan unsur perang dagang—umumnya mereka berargumen soal aspek lingkungan karena sawit Indonesia menyerobot kawasan hutan negara.
Buku ini, Hutan Kita Bersawit: Gagasan Penyelesaian untuk Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kawasan Hutan yang baru saja diterbitkan Yayasan Kehati (2019), menawarkan satu solusi menangani konflik lahan itu dengan berpijak pada sawit adalah komoditas yang, bagaimana pun, menyumbang penghidupan ekonomi penduduk Indonesia.
Mematikan sawit, kata para penulis buku ini, tak akan menyelesaikan problem tata ruang dan konflik lahan. Apalagi, sawit tak hanya dibudidayakan perusahaan, melainkan oleh masyarakat. Mereka bahkan telah menanam sawit jauh sebelum perusahaan diberi izin mengembangbiakannya.
Solusi menyelesaikan konflik lahan sawit milik perusahaan di kawasan hutan yang ditawarkan buku ini adalah menata kembali perizinannya yang morat-marit akibat compang-campingnya aturan dan praktik kacau tata ruang. Moratorium izin baru sejak 2018 bisa menjadi kesempatan emas melakukan itu.
Pemerintah didorong memakai waktu tiga tahun selama penundaan izin baru untuk mendata izin-izin perkebunan sawit yang terserak di seluruh Indonesia. Tumpang tindih izin akibat pendelegasian kewenangan kepada pemerintah daerah perlu dibenahi agar kita punya satu data untuk menganalisisnya.
Penegakan hukum adalah jalan terakhir dari solusi yang mesti dilakukan, terutama bagi kebun sawit yang menyerobot kawasan hutan. Sementara lahan sawit yang telantar dan ditinggalkan pemiliknya, buku ini menganjurkan agar pemerintah memakai redistribusi lahan dalam skema reforma agraria dengan memberi kepercayaan kepada desa dalam mengelolanya.
Solusi yang menarik dan agak panjang dibahas adalah menyelesaikan konflik lahan di kawasan hutan antara negara dengan masyarakat. Berbeda dengan perusahaan yang mencari untung besar, masyarakat masuk kawasan hutan untuk mencari penghidupan yang lebih baik.
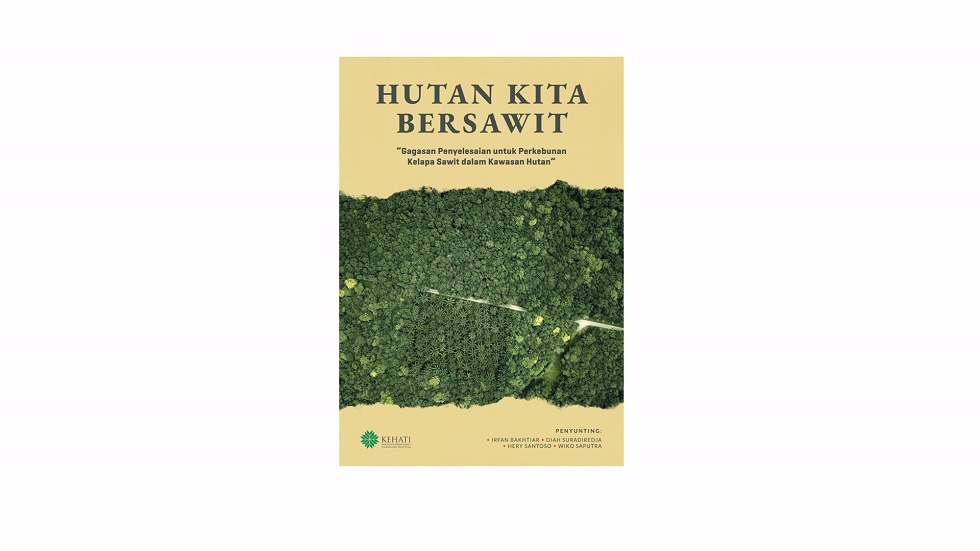
Hutan Kita Bersawit: Gagasan Penyelesaian untuk Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kawasan Hutan yang diterbitkan Yayasan Kehati (2019),
Euforia Reformasi 1998 membuat masyarakat menyerbu kawasan hutan lalu menanaminya dengan, umumnya, tanaman sawit. Permintaan yang tinggi dan harga yang melonjak membuat sawit menjadi bonanza ekonomi Indonesia. Konflik pun tak terhindarkan, hingga pemerintah membuat solusi melalui skema perhutanan sosial.
Mereka yang merambah kawasan hutan, tinggal di sana membentuk desa-desa baru, diizinkan mengusulkan tanah mereka menjadi skema satu dari lima perhutanan sosial: hutan desa, kemitraan kehutanan, hutan adat, hutan kemasyarakatan, atau hutan tanaman rakyat. Jika disetujui mereka akan mendapatkan izin mengelola lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga, dengan izin diberikan kepada kelompok petani, selama 35 tahun.
Perhutanan sosial pun menjadi solusi yang menguntungkan kedua belah pihak: masyarakat bisa meneruskan mengelola lahannya dengan kewajiban menjaga tutupan hutan, menjaga mata air, mencegah kebakaran; negara tetap memiliki aset kawasannya. Sebab, tujuan perhutanan sosial ada tiga: meningkatkan ekonomi masyarakat, menghentikan konflik sosial, dan menjaga ekologi kawasan hutan.
Masalahnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83/2016 yang mengatur perhutanan sosial melarang masyarakat menanam sawit. Padahal, menurut perhitungan Universitas Gadjah Mada (2018) setidaknya ada 1,3 juta hektare kebun sawit masyarakat di kawasan hutan. Menggusur kebun sawit mereka hanya memperpanjang konflik, memutihkannya bukan solusi yang arif.
P 83/2016 mengatur bahwa jika penduduk telanjur menanam sawit ketika mengajukan izin hutan sosial, mereka harus menggantinya dengan agroforestri jika sawitnya berusia di bawah tiga tahun. Jika lebih tiga tahun mereka diizinkan memelihara sawit hingga setengah daur atau 12 tahun. Setelah itu wajib mengganti dengan sistem tumpang sari: menanam pohon hutan dan memberdayakan ruang di bawahnya dengan komoditas lain.
Menurut para penulis buku ini, skema hutan sosial itu kurang adil bagi penduduk yang telanjur menanam sawit di lahannya. Sebab, sawit di atas 12 tahun sedang matang dan harganya sedang tinggi. Ada aspek ekonomi masyarakat yang tereduksi akibat larangan dalam P83/2016 itu, terutama pasal 56 ayat 5. Seperti dinyatakan petani di Tebo, Jambi, yang mendapatkan izin perhutanan sosial skema Hutan Rakyat yang mustahil membongkar sawit mereka yang berusia 15 tahun.
Buku ini menawarkan satu solusi untuk kasus seperti di Tebo, yakni agroforestri sawit yang mereka sebut dengan Strategi Jangka Benah, yang merupakan tawaran dari serial diskusi sejumlah lembaga nonpemerintah berdasarkan penelitian Fakultas Kehutanan Gadjah Mada Yogyakarta pada 2018. SJB adalah strategi menjadikan hutan kembali dengan tindakan silvikultur dengan menggabungkan tanaman sekunder dan primer.
Dasar empirisnya adalah praktik SJB di sejumlah desa di Sumatera dan Kalimantan. Para petani sudah lama menggabungkan sawit dengan pohon-pohon hutan semacam jelutung, bahkan dengan karet. Mengutip penelitian-penelitian sebelumnya, buku ini menganjurkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan merevisi pasal 65 huruf h dengan mengizinkan sawit rakyat tetap hidup seraya mewajibkan mereka menanam 100 pohon berkayu per hektare.
Meski menganjurkan sistem ini, para penulis buku mewanti-wanti agar kebijakan ini didukung oleh seperangkat aturan untuk memastikan hutan campur sawit tak justru merusak hutan yang menjadi tujuan utama perhutanan sosial.
Agaknya pengalaman masyarakat Desa Lubuk Seberuk di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, perlu menjadi bahan perbandingan. Mereka mendapat izin skema hutan rakyat dari Presiden Joko Widodo pada Desember 2018, tapi mereka sudah telanjur menanami lahan di hutan Register 10 yang izin konsesinya dipegang Inhutani III itu dengan sawit. Ketika Jokowi meminta mereka membunuhnya, penduduk beramai-ramai menyiramkan solar ke pucuk sawit di areal seluas tiga hektare.
Sawit-sawit berusia 10-12 tahun itu pun meranggas dan mati (foto di atas). Penduduk lalu menggantinya dengan karet. Masyarakat lima desa di sana kini fokus menyadap getah karet yang sudah mereka tanam sejak 2000-an. Mereka sudah lama mengganti sawit, yang ditanam mulai 1997, dengan karet karena harga komoditas ini lebih stabil.
Di tengkulak harganya Rp 8.000 per kilogram. Mereka memanen getahnya 50 kilogram per hektare per pekan. Artinya, satu keluarga bisa memanen 100 kilogram per pekan. Dalam sebulan tiap kepala keluarga mendapatkan penghasilan Rp 3,2 juta. Itu dari karetnya saja, belum dari gaharu atau dari tanaman tumpang sari lain. Jika satu keluarga rata-rata 4-5 anggota, keluarga di Lubuk Seberuk sudah tergolong bebas dari kemiskinan.
BERSAMA MELESTARIKAN BUMI
Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.
Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.
Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.

Redaksi
Topik :












