
GAMBUT adalah areal hutan yang tak produktif. Gambut itu tak berpenghuni. Hutan gambut telah rusak dan tak cocok untuk sumber penghidupan. Gambut sumber kebakaran. Gambut sumber bencana ekologis di Indonesia.
Itulah stigma negatif terhadap gambut yang disimpulkan Eko Cahyono, peneliti gambut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, yang memaparkannya dalam diskusi “Perhutanan Sosial di Lahan Gambut: Mau Dibawa Kemana?” di Hotel Holiday Inn Express Jakarta pada 23 Juli 2019. Akibat stigma itu, kata Eko, kebijakan terhadap pengelolaannya menjadi tak komprehensif dan gambut telah dipandang sebelah mata.
Padahal, seperti ekosistem hutan lain, ada jutaan orang yang tergantung hidupnya pada gambut—kawasan biomassa maha luas yang terbentuk oleh serasah selama berabad-abad. Menurut Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah Kementerian Pertanian, luas hutan gambut setidaknya 26,5 juta hektare, tersebar di semua kepulauan Indonesia terutama Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Akibat pengelolaan hutan yang tak lestari, disusul perubahan orientasi bisnis dari hutan ke perkebunan, membuat gambut rusak seluas 3,7 juta hektare. Kerusakan ini agaknya yang membuat stigma negatif terhadap gambut. Akibatnya, pemerintah sangat berhati-hati menelurkan kebijakan perhutanan sosial di gambut.
Selain ada moratorium izin baru pembukaan lahan gambut, yang hendak dipermanenkan setelah habis masa perpanjangannya Juli tahun ini, gambut dianggap rawan kebakaran karena ia berfungsi menyimpan panas.
Walhi mencatat ada 237.472 hektare pengajuan izin perhutanan sosial yang belum disetujui pemerintah. Dari 3,09 juta hektare izin perhutanan sosial hingga Juni 2019 yang sudah diterbitkan pemerintah, mayoritas diberikan untuk hutan non gambut.
BACA: Efektifkah Lidah Mertua Menyerap Polusi Jakarta?
Dari catatan Walhi baru ada tujuh desa di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, yang mendapat izin mengelola kawasan dengan skema hutan desa seluas 10.390 hektare yang surat keputusannya terbit pada 2017 . Lalu di Desa Buntoi, Kalimantan Tengah, berupa hutan tanaman rakyat seluas 1.912 hektare.
Kesulitan mendapatkan izin akses masyarakat sekitar gambut mengelola hutan melalui perhutanan sosial setidaknya terbaca dari pengalaman Akiat, penduduk Desa Kapau Baru, Kepulauan Meranti, Riau. Akiat menceritakan usahanya mendapat legalitas mengelola hutan di kawasan gambut. “Setelah lima tahun belum berhasil sampai mendapat izin hutan kemasyarakatan sampai sekarang,” kata Akiat dalam diskusi yang dihela oleh Wahana Lingkungan Hidup dan Kemitraan ini.
Penduduk Desa Kepau Baru—150 kilometer dari Pekan Baru ke arah selat Malaka—umumnya mengandalkan hidup dan kebun sagu sejak awal mereka menghuni kampung. Desa dengan tiga dusun itu dihuni sekitar 2.000 jiwa yang sebagian besar merupakan Suku Akit. Sejak 1970 mereka mengandalkan hidup pada kebun sagu atau menjadi nelayan.
Menurut Akiat, ia dan tetangganya mengajukan skema hutan kemasyarakatan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena sebagian besar wilayah desa berada dalam konsesi hutan tanaman industri PT Nasional Sago Prima. “Sebagian dari kami adalah korban sistem ijon karena mengolah kebun di atas lahan yang izinnya di pegang perusahaan,” kata dia.
Bagi suku Akit, gambut menjadi ekosistem penting karena menjadi penjaga ketersediaan air bersih. Karena itu, dengan memelihara kebun sagu secara otomatis mereka menjaga air dalam kawasan gambut itu. Kayu, sementara itu, hanya mereka pakai untuk membangun rumah atau membuat perahu. “Kami memelihara sagu dengan kearifan lokal,” kata Akit.
Wujud kearifan lokal itu berupa mengombinasikan kayu dan sagu sebagai agroforestri, tak memakai kanal sebagai jalur distribusi maupun akses dari rumah ke kebun, tak membakar lahan untuk mengolah pertanian, dan tak memakai pupuk kimia untuk meningkatkan produksi sagu. “Kalau sudah ada izin, kami tak lagi menumpang kebun sagu di lahan tauke,” kata Akiat.
BACA: Menguji Keabsahan Hutan Adat
Kesulitan memberikan izin perhutanan sosial di areal gambut juga diakui para pejabat Kementerian Lingkungan Hidup. Menurut Direktur Kemitraan Lingkungan Jo Kumala banyak pertimbangan dari pemerintah sebelum memberikan izin perhutanan sosial di gambut. “Ada regulasi yang belum harmonis,” katanya. “Dan risikonya lumayan tinggi di gambut.”
Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Bambang Supriyanto menambahkan bahwa peraturan Menteri Lingkungan soal perhutanan sosial di gambut belum terbit. “Semoga pekan ini,” katanya.
Prinsip utama perhutanan sosial di lahan gambut, kata Bambang , adalah mengedepankan pelestarian Kesatuan Hidrologis Gambut. Peraturan tersebut akan mengatur pengembangan ekonomi di lahan ini. Pada gambut dengan fungsi lindung yang ketebalannya lebih dari 3 meter, pemanfaatan gambut tidak bisa dilakukan melalui budi daya, melainkan jasa lingkungan semacam ekowisata. Budidaya baru bisa dilakukan untuk gambut dengan ketebalan 1-3 meter berupa penanaman pohon.
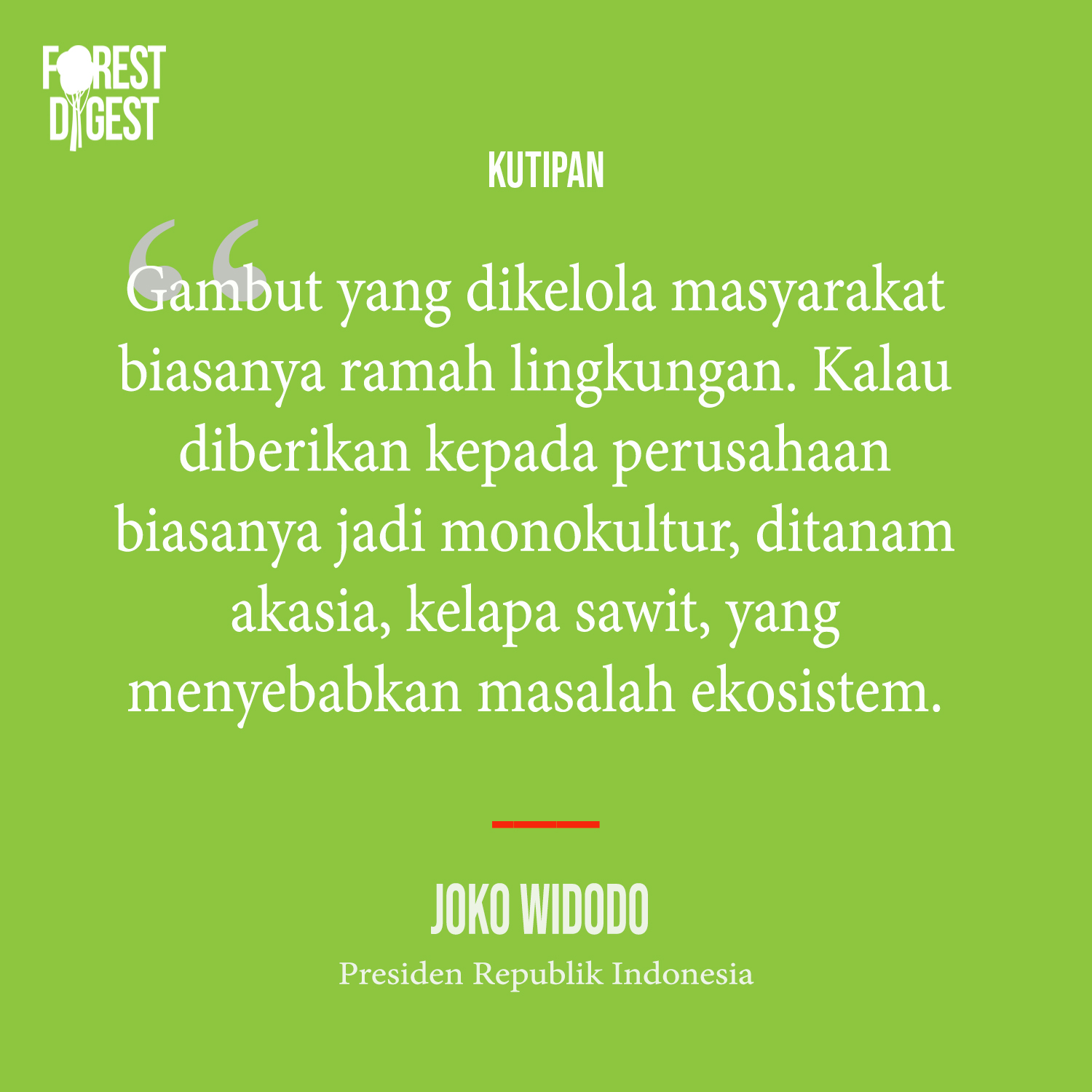
Joko Widodo
Selama ini perhutanan sosial untuk lima skema mengacu pada Peraturan Nomor 83/2016 tentang perhutanan sosial. Di sana gambut hanya disinggung jika pemanfaatan hutannya untuk tujuan restorasi. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah 71/2014 yang mengatur fungsi lindung gambut untuk penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan dan jasa lingkungan.
Karena itu Boy Jerry Even Sembiring, Manajer Kajian Kebijakan Eksekutif Nasional Walhi, mengajukan usul agar Menteri Lingkungan membuat peraturan khusus perhutanan sosial di gambut melalui hutan desa, hutan kemasyarakatan, kemitraan kehutanan, dan hutan adat. Tanpa revisi aturan, kata dia, masyarakat sekitar gambut akan terus kesulitan mendapatkan akses kelola.
BACA: Bahasa, Senjata Paling Ampuh Mencegah Pemanasan Global
Menurut Boy, pengelolaan hutan sosial oleh masyarakat di gambut terbukti ramah lingkungan. Di Desa Sungai Tohor, tetangga Kepau Baru, masyarakat menghasilkan 300-500 ton sagu per bulan yang diproduksi secara konsisten. Masyarakat tak merusak ekosistem gambut. “Kearifan lokal ini mampu menjadi nadi perekonomian, menyelamatkan hutan dan ekosistem gambut, sehingga menyelamatkan mereka dari ancaman bencana ekologi,” kata dia.
Kekhawatiran akan risiko kebakaran di lahan gambut, menurut Boy, juga terbantahkan oleh data bahwa pada kebakaran 2018 titik api lebih banyak berada di konsesi perusahaan dibanding di areal gambut yang dikelola masyarakat.
BERSAMA MELESTARIKAN BUMI
Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.
Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.
Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.

Lulus program doktor Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB
Topik :












