Kabar Baru| 21 September 2019
RUU Pertanahan Berpihak pada Korporasi Besar
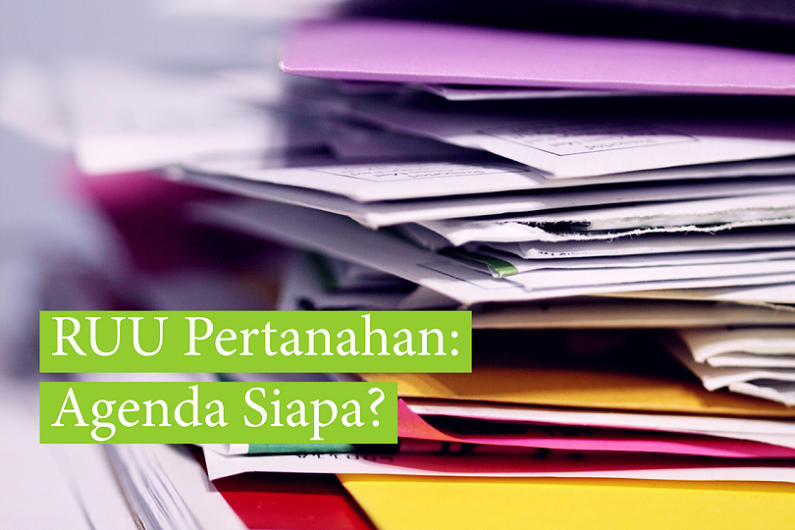
SALAH satu yang mencuat dalam Rancangan Undang-Undang Pertanahan yang tengah digodok DPR adalah keberpihakan negara kepada korporasi besar dalam hal izin memanfaatkan lahan negara. “Hak guna usaha masih diprioritaskan bagi elite pemilik modal besar,” demikian salah satu bunyi rekomendasi para guru besar Fakultas Kehutanan IPB dari hasil diskusi pada akhir Agustus 2019.
Menurut Didik Suharjito, guru besar IPB yang memimpin diskusi RUU Pertanahan itu, rekomendasi ini dibuat sebagai tindak lanjut diskusi para guru besar lintas universitas di Yogyakarta. Dalam diskusi itu para guru besar meminta pemerintah dan DPR menunda pembahasan RUU ini karena ada banyak hal yang tak sesuai dengan prinsip keadilan penggunaan lahan. “Rekomendasi ini sudah kami kirim ke DPR,” kata Didik.
Salah satu wujud keberpihakan negara kepada korporasi dalam pengelolaan lahan berupa rencana pembentukan Bank Tanah jika Rancangan ini disahkan DPR. Masalahnya adalah pembentukan Bank Tanah ini terkesan sekadar menjawab keluhan korporasi dan pemilik modal ketika mereka terhambat dalam membebaskan tanah untuk usaha mereka atau ketika hendak membangun infrastruktur.
Lebih rancu lagi adalah sumber pembiayaan Bank Tanah. Tidak saja berasal dari anggaran negara melalui APBN, sumber uang bank ini diizinkan dari penyertaan modal pemerintah, kerja sama pihak ketiga, pinjaman dan sumber lainnya. Artinya, korporasi bisa masuk menjadi pemodal bank tanah yang ironisnya bisa mencaplok simpanan tanah yang dimiliki bank ini. Sementara status tanah yang dikuasai Bank Tanah adalah milik negara.
Para guru besar IPB cemas bahwa pembentukan Bank Tanah akan memperparah ketimpangan akses masyarakat terhadap lahan, meruncingkan konflik sosial, dan melempangkan cara-cara perampasan tanah oleh korporasi kepada masyarakat. Bahkan Bank Tanah bisa menjadi lembaga yang meneruskan praktik spekulan tanah.
Rancangan ini juga bertabrakan dengan undang-undang dan aturan lain. Misalnya, soal “hak penguasaan tanah, oleh negara” yang diatur Pasal 3. Di sini diatur bahwa penguasaan tanah, ruang, dan kawasan merupakan kewenangan presiden yang bisa didelegasikan kepada menteri. Soalnya ada Ketetapan MPR IX/2001 yang mengatur pemisahan ketiga unsur itu. Penggabungan akan menabrak ketetapan ini karena aspek teknisnya tidak bisa didelegasikan kepada seorang menteri.
Hal lain soal pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, khususnya hak guna usaha kawasan hutan. Pasal 30 ayat (3) menyebutkan "dalam hal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di kawasan hutan, pemberian Hak Guna Usaha dilakukan setelah pelepasan kawasan hutan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
Sementara dalam Undang-Undang 41/1999, berdasarkan peruntukan saat pengajuan permohonan pelepasan kawasan hutan, pada ayat (4) disebutkan tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan penggunaan dan pemanfaatannya ditetapkan oleh Menteri yang berimplikasi pada:
(1) Pelepasan kawasan hutan tidak mungkin dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanpa analisis peruntukan dan penggunaannya dan tanpa permohonan peruntukan, sehingga terjadi kerancuan dalam mekanisme pelepasan hutan untuk HGU.
Sebaliknya, (2) apabila penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan diatur oleh Kementerian Agraria maka bertentangan dengan Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Lingkungan, hingga merusak sistem dan prosedur pemerintahan.
Hal penting lainnya adalah Rancangan ini bisa menimbulkan konflik sosial karena dalam perkebunan ada aturan soal penyediaan plasma yang direstui oleh korporasi. Negara tak hadir sebagai penengah sehingga konflik antar petani yang rebutan memasok plasma kepada perkebunan inti yang dibangun pengusaha akan sangat tinggi.
Rekomendasi selengkapnya:
REKOMENDASI UNTUK PENYEMPURNAAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERTANAHAN
1. Tanah untuk Kedaulatan pangan dan menghadapi krisis pangan dunia 2050
- Tata kelola sumber daya alam, tata ruang dan agraria nasional masih bersifat fragmented sehingga tidak efisien dan menyisakan sumber daya alam yang menganggur serta moral hazard;
- Indonesia masih menghadapi faktor pembatas ketercapaian kedaulatan- kemandirian-ketahanan pangan nasional, khususnya akibat keterbatasan lahan untuk pangan secara struktural;
- Indonesia masih memiliki peluang meningkatkan kapasitas produksi pangan dan percepatan pertumbuhan ekonomi, serta mampu menghadapi krisi pangan dunia pada tahun 2050 melalui terobosan pengaturan pertanahan, tata ruang dan keagrariaan baru;
- Single Land Administration System jika dilaksanakan dengan tepat dapat menjadi jalan tengah harmonisasi peraturan perundang-undangan;
- RUU Pertanahan berpeluang menjadi pelengkap, pelurus tafsir dan alat harmoni filosofis, konsep dan praktik tata kelola SDA dan sumber daya Agraria;
- RUU Pertanahan sangat diperlukan namun masih memerlukan berbagai penyempurnaan dan perlu menghindari ketergesa-gesaan.
2. Tanah untuk pengembangan usaha perkebunan
- Pengembangan perkebunan (kelapa sawit) dan dampaknya terhadap lingkungan berkaitan dengan banyak hal: perizinan, konflik lahan (masyarakat adat/ setempat dengan perusahaan), hubungan antara petani lokal (plasma) dengan perusahaan, deforestasi dan kebakaran hutan;
- Kerangka kebijakan diperlukan untuk mengatur pengembangan lahan perkebunan (kelapa sawit) yang terencana, legal, dan ramah lingkungan;
3. Aspek sosio-kultural dan politik ekonomi tanah
- Kondisi agraria mutakhir di Indonesia saat ini: (1) Ketimpangan struktur agraria yang semakin tajam; (2) Maraknya konflik agraria struktural; (3) Kerusakan ekologis yang meluas; (4) Laju cepat alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian; (5) Kemiskinan akibat struktur agraria yang menindas;
- UU Pertanahan harus dapat menyelesaikan dan menjadi jalan keluar bagi lima krisis pokok agraria tersebut pada butir (1), namun naskah RUU Pertanahan belum mampu menjawab lima krisis Undang-Undang Pertanahan nasional seyogyanya menjadi titik tolak dalam mewujudkan keadilan agraria yang dicita-citakan pasal 33 UUD 1945, UUPA 1960, dan TAP MPR IX Tahun 2001;
- Beberapa isu krusial yang harus menjadi perhatian utama terkait RUU Pertanahan antara lain:
- Kedudukan Hak Pengelolaan (HPL) berpotensi memunculkan kerumitan penguasaan tanah dan menghidupkan kembali domeinverklaring, yang sudah dihapuskan dalam UUPA;
- Masalah Hak Guna Usaha (HGU) di dalam RUU Pertanahan memperlihatkan bahwa HGU tetap diprioritaskan bagi elit pemilik modal besar dan korporasi. RUU Pertanahan belum memasukkan komponen keterbukaan informasi HGU;
- Permasalahan Masyarakat Hukum Adat: Konstitusi sudah dengan jelas mengakui keberadaan Masyarakat Adat beserta hak-hak tradisionalnya. Namun RUU Pertanahan tidak memiliki langkah konkrit dalam administrasi dan perlindungan hak ulayat masyarakat adat atau yang serupa dengan itu;
- Kontradiksi dengan agenda dan spirit Reforma Agraria (RA): Terdapat kontradiksi antara semangat reformasi di dalam konsideran dan ketentuan umum RUU Pertanahan dengan isinya. Pertama, reformasi agraria dalam RUU Pertanahan dikerdilkan menjadi sekadar program penataan aset yang tidak memuat prinsip, tujuan, mekanisme, lembaga pelaksana, pendanaan untuk menjamin reformasi agraria yang sejati, yakni operasi negara untuk menata ulang struktur agraria Indonesia yang timpang secara sistematis, terstruktur dan memiliki kerangka waktu yang jelas. Tidak ada prioritas obyek dan subyek RA untuk memastikan sejalan dengan tujuan-tujuan reforma agraria di Indonesia.
Kedua, spirit RA di RUU Pertanahan sangat parsial (hanya sebatas bab reformasi agraria), namun tidak tecermin di bab-bab lain terkait rumusan-rumusan baru mengenai Hak atas tanah (Hak Pengelolaan, HM, HGU, HGB, Hak Pakai), Pendaftaran Tanah, Pengadaan Tanah dan Bank Tanah, dan Pengadilan Pertanahan. Apabila pengaturan reforma agraria belum detail dalam suatu undang-undang, harus dapat dipastikan pendetailannya pada Peraturan Pemerintah;
- Bank Tanah: Keinginan RUU Pertanahan untuk membentuk Bank Tanah nampaknya hanya menjawab keluhan investor soal hambatan pengadaan dan pembebasan tanah untuk pembangunan Bank Tanah yang akan dibentuk pemerintah adalah lembaga yang sumber pendanaannya tidak hanya berasal dari APBN bahkan dapat berasal dari penyertaan modal, kerjasama pihak ketiga, pinjaman, dan sumber lainnya. Jika dibentuk, Bank Tanah beresiko memperparah ketimpangan, konflik, melancarkan proses-proses perampasan tanah atas nama pengadaan tanah dan meneruskan praktik spekulan tanah. Ironisnya, sumber tanah Bank Tanah justru berasal dari tanah Negara sehingga berpotensi menghalangi agenda reformasi agraria.
4. Tinjauan potensi disintegrasi sistem pelayanan publik terkait SDA
- Pada pasal 3 disebutkan: ayat (3) Penyelenggaraan hak menguasai dari negara atas tanah, ruang dan kawasan dalam satu kesatuan sistem tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kewenangan Presiden; ayat (4) Pelaksanaan kewenangan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bersifat teknis dapat didelegasikan kepada Menteri sesuai dengan tugas dan fungsi; ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak menguasai dari negara dan pendelegasian kewenangan diatur dengan Peraturan Implikasinya adalah:
- Apabila aspek tanah, ruang dan kawasan digabungkan dalam RUU Pertanahan maka bertentangan dengan TAP MPR Nomor IX/2001. Maka, penyelenggaraan kewenangan negara atas tanah, ruang dan kawasan yang dilaksanakan oleh Presiden tidak dapat didelegasikan kepada 1 (satu) menteri;
- Apabila didelegasikan pada satu menteri maka Peraturan Presiden yang mengatur kewenangan mengenai Hak Menguasai Negara bertentangan dengan kewenangan yang diatur undang-undang lain;
- Pengaturan oleh Perpres akan bertentangan dengan UU dan PP, serta Perpres.
- Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan khususnya HGU dari kawasan hutan: Pasal 30 ayat (3) menyebutkan: Dalam hal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di kawasan hutan, pemberian Hak Guna Usaha dilakukan setelah pelepasan kawasan hutan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. Hal ini harus sesuai dengan ijin lokasi, ijin lingkungan dan rekomendasi Tim Terpadu (sebagaimana disebutkan pada pasal 19 UU 41 Tahun 1999) berdasarkan peruntukan saat pengajuan permohonan pelepasan kawasan hutan. Pada ayat (4): Tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penggunaan dan pemanfaatannya ditetapkan oleh Menteri. Implikasinya adalah:
- Pelepasan kawasan hutan tidak mungkin dilakukan oleh LHK tanpa dilakukan analisis peruntukan dan penggunaannya dan tanpa permohonan peruntukan (terkait Pasal-pasal 3,5, 6, dan 30), sehingga terjadi kerancuan dalam mekanisme pelepasan untuk HGU;
- Apabila penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan diatur oleh kementerian ATR maka: (a) Bertentangan dengan UU Kehutanan, UU Lingkungan, (b) Membuat kekisruhan dan ketidakpastian usaha, dan (c) Merusak tatanan sistem dan prosedur
5. Konsekuensi kerawanan serta potensi masalah hukum
- Kawasan-kawasan pertambangan akan bisa lepas dengan penetapan HPL oleh Menteri ATR (misal Cagar Alam, KBAK CAT Rembang dll ) sehingga fungsi kawasan tidak menjadi perhitungan (seperti habitat,dll). Dengan UU ini, semua masalah tanah dalam kawasan hutan secara otomatis akan dilepaskan dan pelanggaran akan “diputihkan”.
- Distorsi yang akan terjadi adalah:
- Distorsi dengan langkah yang sedang ada di KPK, BPK, dan K/L dalam mekanisme yang diatur UU Kehutanan, UU Minerba, dan UU Wilayah Pesisir;
- Tanah-tanah bermasalah langsung diserahkan kepada Menteri ATR dan diputuskan oleh menteri ATR; Masalah residualnya (residual effect) akan diselesaikan oleh siapa ?
- Kewenangan untuk penyelesaian sektoral masalah-masalah ini sudah ada dalam UU sektoral masing-masing, sehingga pengaturan baru (RUU Pertanahan) tanpa kejelasan konseptualnya akan menyebabkan distorsi tata kerja
- Akan menimbulkan konflik horisontal baru antar masyarakat dengan norma dalam RUU untuk penyediaan plasma kebun. Kondisi lapangan mencatat bahwa ada plasma yang “diatur” oleh korporat. Akan terjadi klaim-klaim tanah (hutan) atas perintah UU;
- Akan menimbulkan konflik vertikal baru antara masyarakat dengan pemerintah cq KLHK dimana masyarakat ("atas dorongan swasta") karena dalam UU ditegaskan bahwa masyarakat mendapat areal di sekitar lahan swasta (di lahan mana saja), dan itu diperoleh dari pemerintah;
- Terdapat potensi tindakan korupsi:
- Terdapat ketidak-sesuaian kaidah, norma dan pengaturannya, baik terhadap Ketetapan MPR No IX/2001 terutama mengenai kebijakan pembaruan agraria (Pasal 5), maupun potensi ketidak-sesuaian dengan undang-undang lain. Hal itu selain menyebabkan ketidak- pastian hukum, berpotensi menghilangkan efektivitas dan efisiensi dalam implementasinya, maupun potensi pemborosan sumberdaya;
- Terdapat multi-tafsir interpretasi isinya, yang dapat menjadi penyebab perbedaan interpretasi dan memungkinkan subyektivitas dalam pengambilan keputusan. Misalnya, dalam Pasal 7 (3) disebut “Dalam keadaan tertentu, pemegang Hak Pengelolaan dapat memberikan rekomendasi pemberian Hak Atas Tanah pertama kali dan perpanjangan diberikan sekaligus atas persetujuan Menteri dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. Dalam penjelasannya, pengertian “dalam keadaan tertentu” yaitu “sesuatu keadaan yang dipertimbangkan oleh Menteri”. Penjelasan tersebut masih berpotensi multi-tafsir;
- Terdapat penjelasan yang tidak final atau sama sekali tidak ada penjelasan terhadap hal-hal yang dikecualikan. Hal ini membuka peluang terjadinya diskresi akibat ruang interpretasi terlalu lebar;
- Dibuka peluang adanya insentif ganda serta alokasi sumberdaya tanah yang belum diketahui secara pasti kriterianya, yang memungkinkan dibukanya peluang pemihakan atau pemenuhan kepentingan bagi pihak-pihak Pada Pasal 22 disebut terdapat insentif bagi pemegang hak atas tanah yang lokasinya terjadi perubahan tata ruang, walaupun pemegang hak itu masih menguasai, memiliki, menggunakan dan memanfaatkannya. Insentif itu berupa ganti rugi paling banyak 100 persen dari nilai tanah sebelum perubahan tata ruang, sementara pemegang hak hanya menyerahkan tanahnya seluas 50 persen dari luas bidang tanah yang terkena perubahan tata ruang;
- Lemahnya perlindungan sosial maupun ekologi dalam penetapan hak atas tanah maupun kebijakan pertanahan, sehingga berpotensi menghapus inisiatif konservasi tanah dan jasa lingkungan;
- Tidak tersedia kesempatan maupun instrumen untuk mengembalikan kekayaan (tanah) negara, maupun hilangnya kesempatan mencegah terjadinya kerugian negara dan/atau kerugian perekonomian
BERSAMA MELESTARIKAN BUMI
Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.
Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.
Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.

Redaksi
Topik :












