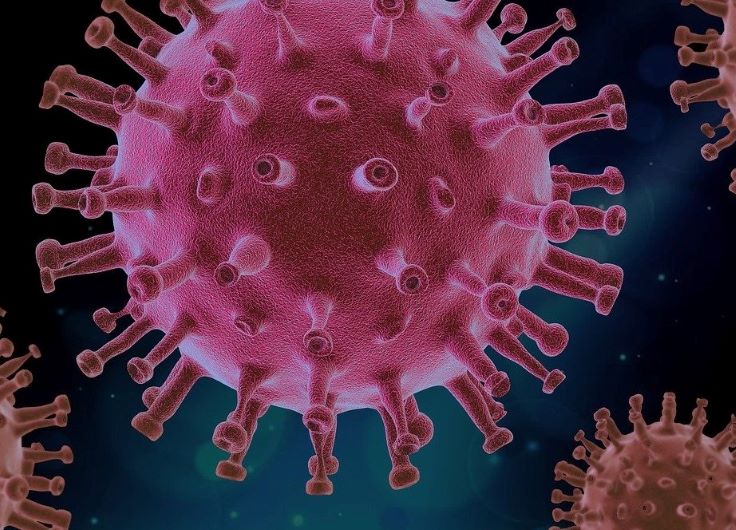
MEREBAKNYA virus corona (Covid-19) membuat ramai perbincangan di dunia maya dan dunia nyata. Obrolan seputar ini tidak sekadar tentang bagaimana mematikan dan berbahayanya virus yang mulai merebak di Wuhan, Cina, Desember 2019, tapi juga tentang dampak ekonomi, soal politik, hingga yang tak kalah seru adalah pembahasan tentang dampak pada kehidupan keberagamaan kita.
Sejak awal corona memancing diskusi, tak terkecuali para penceramah agama. Saat virus ini baru merebak di Cina, sejumlah penceramah mengaitkannya sebagai kutukan Tuhan, sebagai balasan terhadap perlakuan pemerintah Cina kepada muslim di Uighur. Bahkan, virus ini mendapat tempat “terhormat” karena dijuluki sebagai tentara Allah.
Ketika virus ini mulai menyebar ke seluruh dunia dan mulai mempengaruhi ibadah mahdhah kita (seperti umrah, salat jamaah, Jumatan, bahkan mungkin haji), corona turun derajat dari tentara Allah menjadi setan yang menghalang-halangi ibadah kepada Allah.
BACA: Udara Jakarta di Tengah Wabah Corona
Masalahnya kemudian, ini bukan sekadar retorika. Banyak yang kemudian mengajak kita berani menghadapinya dalam arti yang membahayakan: tak usah takut, virus juga ciptaan Allah, kita tetap ramaikan masjid dan Jumatan seperti biasa. Bahkan ada yang mengatakan, dengan wudu virus bisa dibasmi.
Tulisan ini tidak akan membahas satu per satu masalah tersebut. Dalam tulisan ini saya fokus pada bagaimana Islam menanggapi wabah seperti ini, hingga kita tidak asal menamakan Islam untuk sikap yang kurang tepat. Meski nCov-19 termasuk virus baru, masalah wabah penyakit dalam berbagai bentuknya, sudah pernah terjadi di masa lalu dan memiliki dampak yang cukup besar.
Yang harus dipahami terlebih dahulu adalah pendekatan dasar kita dalam memandang penyakit dan wabah. Kalau kita perhatikan buku-buku klasik, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa para ulama Islam terdahulu memandang penyakit sebagai sebuah fenomena alam. Kejadian duniawi yang tidak melulu dihubungkan dengan kutukan Tuhan.
Pemahaman ini kemudian berimbas pada pendekatan yang mereka pakai. Saat membahas penyakit dan wabah (thaun), para ulama memakai pendekatannya sangat saintifik. Itulah yang membuat ilmu pengetahuan di Masa Keemasan Islam begitu maju, menjadi jembatan sebelum muncul Renaisance di Eropa.
Di masa Keemasan Sains Islam, saat orang-orang di Eropa masih menganggap penyakit adalah kutukan dan sihir, para pemikir Islam seperti Ibn Sina, Ar-Razi, dan Al-Kindi sudah membahasnya secara ilmiah. Mereka sangat pragmatis, memakai percobaan yang harus bisa dibuktikan. Karenanya, kalau kita menyingkirkan pendekatan saintifik ini, kita seperti mundur ratusan tahun.
Ini bukan tidak ada dasarnya. Sejak awal Rasulullah SAW pun telah memberi teladan soal itu. Rasul memerintahkan untuk memisahkan yang sehat (al-mushih) dari yang sakit (al-mumridh) untuk mencegah penularan. Rasul juga sudah membicarakan konsep lockdown. Beliau memerintahkan kita tidak masuk ke kawasan yang terserang penyakit. Mereka yang sudah berada di kawasan wabah tidak boleh keluar dan yang ada di luar tidak boleh masuk.
Bagaimana dengan salat jamaah yang berpotensi menjadi sarana tertularnya penyakit ke orang lain? Jangankan menghindari penyakit mematikan, menghindari hujan deras yang cuma membuat kita basah saja mendapatkan rukhsah (keringanan) agar kita tidak ke masjid. Dari zaman Rasulullah SAW sudah ada penggantian kalimat dalam azan, hayya ala shalah (mari kita salat) menjadi ash-shalah fi rihalikum (salatlah di tempat tinggal kamu).
Banyak yang menuduh mereka yang hati-hati dalam menghadapi virus ini (misalnya dengan tidak salat jamaah dan Jumat) sebagai pengecut yang takut pada makhluk Allah lainnya. Bukankah kita tidak boleh takut kecuali pada Allah?
Pernyataan itu sekilas tampak benar. Namun, sesungguhnya pernyataan itu muncul dari ketidaktahuan kita akan salah satu dasar dalam Ushul Fiqh (Dasar Hukum) yang didasari dari hadis Nabi SAW: laa dharara wa laa dhirara. Intinya, kita tidak boleh membahayakan diri kita dan orang lain. Bagaimana mengukur bahaya? Ya kita diminta memakai akal sehat dan ilmu pengetahuan.
Ada tuduhan lain: kok seperti tidak percaya takdir? Kok seperti tidak mau bertawakal? Tuduhan ini juga keluar dari salah paham kita pada tawakal dan takdir. Tawakal itu bukan pasrah, takdir bukannya tidak memberi pilihan.
Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa kita bertawakal setelah mengikat onta atau hewan piaraan kita. Artinya, kalau onta, kuda, mobil, kita biarkan tidak diikat atau dikunci lalu hilang (kabur atau dicuri), itu namanya bukan tawakal. Usaha dulu sekeras mungkin, setelah itu baru tawakal. Bukan pasrah dan tidak berbuat apa-apa. Ukuran kerasnya usaha ini juga harus memakai pertimbangan sains. Kalau untuk mencegah penyebarannya harus melalui social distancing, maka untuk sementara tidak salat jamaah adalah bagian dari usaha itu.
Setelah berusaha keras, kita baru tawakal. Kenapa? Karena meski sudah berusaha bukan berarti kita tidak ada kemungkinan tertular. Yang bisa kita lakukan hanya meminimalkan penularan.
BACA: Problem Lain Virus Corona: Sampah Medis
Bagaimana dengan takdir? Sahat Rasulullah SAW, Umar bin Khattab yang ilmunya luar biasa pernah batal pergi ke negeri Syam yang sedang diserang wabah penyakit. Loh kan sakit itu takdir, Umar menjawab, “Saya pergi dari satu takdir (kena penyakit) ke takdir lain (tidak tertular)."
Dalam takdir ada free will, keinginan bebas, pilihan. Di situlah Allah memberikan kita ikhtiar. Ikhtiar dari khair (baik), artinya mencari yang terbaik berdasarkan pertimbangan kita. Orang yang tidak belajar kemudian tidak lulus tidak boleh berkata, “Ini sudah takdir saya.” Karena ada hal yang bisa kita kontrol yang tidak kita lakukan: belajar.
Soal wudu, apakah bisa mencegah wabah? Belum tentu. Pada abad ke-18 dan 19, saat ada wabah kolera, para ulama berdebat apakah boleh wudu mesti memakai kran atau tidak. Saat itu semua masjid menyediakan kolam tempat orang berwudu bersama. Orang tinggal menyiduk atau mengambil air dengan tangan dari kolam tersebut. Hal ini menjadi media penularan penyakit.
Mungkin karena sudah terbiasa dan menjadi tradisi, rata-rata ulama saat itu tidak membolehkan wudu memakai gayung atau kran. Hanya ulama dari mazhab Hanafi yang membolehkannya. Karenanya, kran dalam bahasa Arab dikenal sebagai hanafiyah, karena dulu cuma dipakai di masjid bermazhab Hanafi. Kini, hampir semua masjid dalam mazhab apa pun memakai kran, tapi nama terkenalnya tetap hanafiyah.
Kenapa bisa berubah? Karena fiqh adalah pemahaman ulama yang bisa berkembang dan berubah sesuai dengan zaman dan input yang mereka terima. Islam itu fleksibel dan memiliki prinsip-prinsip untuk menjaga kemanusiaan.
BERSAMA MELESTARIKAN BUMI
Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.
Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.
Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.

Sarjana Hadits Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar, Kairo
Topik :
















