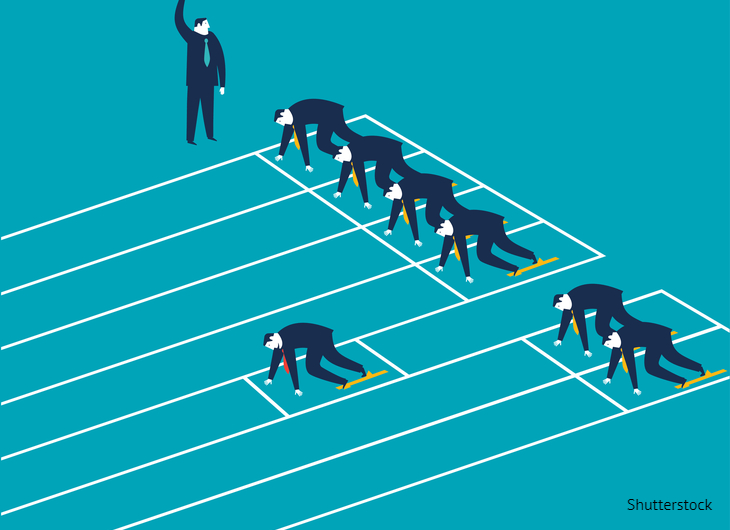
DALAM sebuah perbincangan pekan lalu yang membahas soal kriminalisasi terhadap masyarakat adat karena melindungi sumber daya alam mereka, muncul satu pertanyaan: “Apa yang harus kita lakukan jika problemnya adalah buruknya tata kelola pemerintahan?”
Pertanyaan itu muncul karena fakta masalah yang dihadapi masyarakat telah diurai dengan pelbagai solusi, tapi tak diikuti taraf hidup yang lebih baik. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, misalnya, dianggap berhasil mengendalikan deforestasi dan mitigasi perubahan iklim, tapi transaksi izin kebun dan tambang—dengan atau tanpa meminjam kawasan hutan—membuat masyarakat adat dan lokal tetap jadi korban.
Bisakah objektivitas menilai keberhasilan menekan deforestasi dipakai juga untuk menilai munculnya korban-korban itu? Mengapa ada yang menyebut masyarakat lokal dan adat sebagai penghalang pembangunan?
Ilmu pengetahuan alam mungkin bisa secara objektif menilai sebuah fenomena, kejadian, peristiwa. Tapi ilmu sosial selalu mengandung elemen subjektif karena interpretasi selalu dipengaruhi latar belakang budaya yang mempengaruhinya.
Dalam Philosophy of Science for Scientists, Lars-GÓ§ran Johansson menyebut bahwa pendekatan ilmu alam dan ilmu sosial itu layak diberi label “sains” jika memakai deduktif-hipotetis. Artinya, karena ilmu hukum bagian dari ilmu sosial, hal yang sejalan atau tak sejalan dengan norma itu harus dibuktikan sebagai hipotesis, bukan hanya pada kesesuaian prosedurnya.
Untuk itu, terkait dengan korban-korban masyarakat adat, penguasaan sumber daya alam itulah yang harus dibuktikan, bukan hanya prosedur perizinan sebagai alat sahnya aktivitas satu pihak. Dalam hal ini, keadilan dan manfaat tidak hanya ditelisik dari ilmu hukum saja. Sejarah dan kebijakan administrasi yang tidak adil terhadap masyarakat adat perlu juga dipakai sebagai fakta.
Demikian pula fakta bahwa perizinan usaha besar makin terus dipermudah dan diperluas. Sementara perizinan untuk masyarakat adat dibiarkan terkatung-katung, meski kecil jumlahnya.
Johansson menambahkan ketidakpastian metode kualitatif dalam ilmu sosial tidak terletak pada klasifikasi skala nominal atau ordinal, melainkan pada pencarian makna dari sebuah fenomena. Klaim kualitatif yang obyektif—benar atau salah—adalah bahwa objek yang dibicarakan ada dalam kenyataan dan telah dibuktikan secara independen. Hal itu dapat dilakukan hanya bila cara kerja penetapannya dilakukan secara hati-hati, lengkap, dan adil.
Soal kehati-hatian dalam pengambilan keputusan, Johansson menyitir buku Daniel Kahneman yang terkenal: Thinking: Fast and Slow. Menurut Kahneman, manusia memiliki sistem pengambilan keputusan cepat dan lambat. Otak cepat yang pertama kali menerima informasi biasanya mengedepankan respons emosional. Karena itu keputusan yang keluar darinya biasanya tak logis.
Sementara otak lambat bertindak lebih logis karena menyerap lebih banyak informasi. Masalahnya, sesuai namanya, otak lambat bekerja sangat lambat. Maka yang terjadi adalah keputusan-keputusan diambil berdasarkan respons otak cepat dengan hanya memakai informasi yang tersedia.
Akibatnya, kita menduga sudah berpikir dan bertindak adil dan lengkap, padahal sebaliknya. Kahneman menyebutnya bias WYSIATI, what you see is all there is—kita membuat keputusan hanya dari informasi yang kita punya. Kita luput bertanya dan membuka ruang mencari informasi yang mungkin belum kita pahami sebelum membuat sebuah tindakan atau keputusan.
Maka, dalam tata kelola pemerintahan yang buruk, keputusan-keputusan lebih menonjolkan kepentingan (political interest), bukan pembaruan pemikiran (discources/narrative) (Kartodihardjo, 2018). Dalam membuat Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, atau Rancangan Undang-undang Cipta Kerja, tidak terlihat perdebatan pemikiran di ruang-ruang publik.
Dalam hal masyarakat adat yang jadi korban dalam penguasaan sumber daya alam berbasis izin, penyelesaiannya acap dilakukan secara parsial. Akibatnya, paradigma akibat aturan yang tak pas itu memakan korban di lain waktu dan lain tempat. Sampai kita sulit mengurai akar masalahnya. Dus, pandangan positivistik yang menganggap semua peraturan harus dijalankan, meski hasilnya jauh dari tujuannya mewujudkan keadilan sosial.
Kenyataan seperti itu mengingatkan kita pada eksperimen pemikiran Thomas Hobbes (1588–1679) dalam Leviathan. Menurut Hobbes, kita hidup tanpa otoritas jika tak ada negara. Dalam keadaan itu, hidup tiap orang tergantung pada penilaian dan kekuatan sendiri. Hukum rimba. Maka yang terjadi adalah chaos, karena kita akan berperang melawan semua. Maka kita menerima otoritas negara karena kita menukarnya dengan keselamatan pribadi dan kebahagiaan melalui rasa damai.
Rosen dkk membantah eksperimen Hobbes itu dalam The Norton Introduction to Philosophy (2018). Menurut mereka, keadaan tanpa negara mungkin memang mengerikan, tapi keadaan dengan negara juga bisa lebih buruk. Dalam kondisi normal, negara bisa memakai koersif untuk dalih menegakkan hukum. Otoritas politik yang menindas membuat negara menjadi destruktif.
Maka untuk mencegah destruksi oleh negara itu, Rosen mengajukan perlunya lembaga-lembaga konstitusi, supremasi hukum, pemisahan kekuasaan, dan pemantauan secara demokratis atas pelaksanaan kekuasaan. Masalahnya, secara faktual, meski semua syarat itu ada, destruksi negara bisa tetap terjadi.
Rosen dkk beralih ke pemikiran Jean-Jacques Rousseau, terutama dalam The Social Contract. Mereka menyimpulkan otoritas politik yang meminta setiap orang tunduk pada mereka bukan untuk membayar perlindungan negara kepada masyarakat, tapi untuk pembagian setara dalam otoritas politik sebagai cara mengekspresikan sifat yang bebas. Agaknya, hal ini yang masih jadi persoalan kita sehingga hal-hal yang prosedural masih jadi acuan ketimbang fakta riil dalam mewujudkan keadilan sosial.
BERSAMA MELESTARIKAN BUMI
Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.
Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.
Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.

Guru Besar Kebijakan Kehutanan pada Fakultas Kehutanan dan Lingkungan serta fellow pada Center for Transdiciplinary and Sustainability Sciences, IPB.
Topik :
















