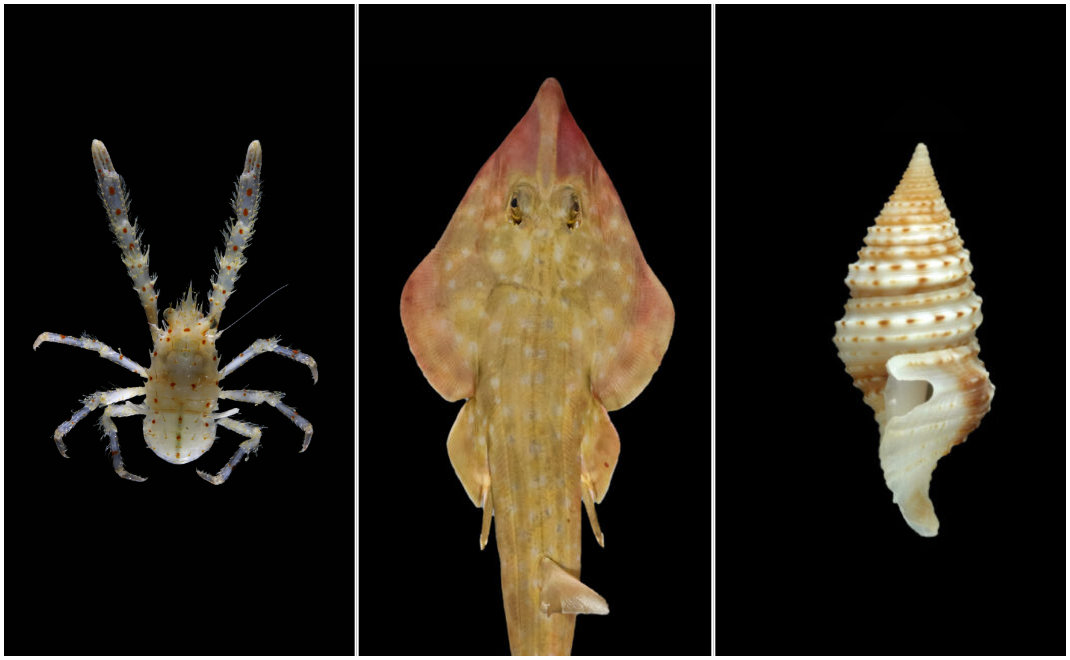WAJAH puluhan orang tua semringah ketika mengiringi anak-anak mereka sunatan massal di Desa Laman Panjang, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, 16 Juli 2018. Anak-anak dari empat desa, Senamat Ulu, Lubuk Beringin, Sangi Letung Dusun Buat dan Sungai Telang, siapa memasuki ritual muslim ini. Tiap desa mengirim 15 anak.
Biaya sunatan massal berasal dari TUI Airways, perusahaan penerbangan di Eropa. Perusahaan ini membayar US$ 36 ribu (sekitar Rp 400 juta) untuk 6.000 ton cadangan karbon (carbon sink) dari kawasan hutan lindung Bukit Panjang Rantau Bayur (biasa disebut Bujang Raba) seluas 5.339 hektare yang dikelola warga lima desa di Kabupaten Bungo.
Selain sunatan massal, uang itu juga berguna untuk membeli bibit durian, duku, juga meningkatkan patroli perlindungan hutan. Sisanya untuk desa sebesar Rp 32 juta per desa. “Di desa kami, uang itu untuk membeli tiga ekor sapi dan membiayai kegiatan ibu-ibu,” kata Fadli, Sekretaris Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Senamat Ulu pada 15 Juni 2019.
Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi mendaftarkan Bujang Raba ke dalam pasar karbon sukarela (voluntary carbon market) melalui skema Plan Vivo. Dari perhitungan KKI Warsi, pada zona lindung hutan desa yang merupakan hutan primer, penyerapan emisi atau cadangan karbon rata-ratanya sebesar 287 ton per hektare atau 1,052 ton setara CO2 per hektare. “TUI Airways hanya membeli 6.000 ton,” kata Direktur Eksekutif KKI Warsi Rudi Syaf pada 23 April 2019.
Kepada Plan Vivo, Warsi juga melampirkan keberhasilan lima LPHD Bujang Raba mencegah deforestasi berdasarkan interpretasi citra satelit Landsat tahun 1993 dan 2013. Laju deforestasi di reference area (wilayah rujukan) rata-rata 1,6 persen per tahun. Mereka membandingkannya dengan interpretasi citra satelit tahun 2015 ketika LPHD mendapat izin mengelola hutan desa selama 35 tahun. “Saat mendapatkan izin, kerusakan tutupan hutan pada 2018 nol persen,” kata Rudi Syaf. “Bisa dikatakan, perhutanan sosial mencegah kerusakan hutan.”
Sejak 2015, ada 20 komunitas yang tergabung dalam The Indonesia Community Payment for Environment Service Consortium (Konsorsium Pengelola Jasa Lingkungan Indonesia) yang memakai standar Plan Vivo. Antara lain Hutan Desa Laman Satong, Ketapang Kalimantan Barat; Hutan Desa Durian Rumbun, Merangin, Jambi; Hutan Kemasyarakatan Aik Bual, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat; dan Hutan Nagari Padang Limau Sundai–Solok Selatan.
Selain Plan Vivo, skema lain yang mengikuti pasar karbon sukarela adalah Verified Carbon Standard (VCS), Gold Standard (GS), Panda Standard, American Carbon Registry dan sebagainya. Di Indonesia, hanya Plan Vivo (untuk skala kecil) dan VCS yang digunakan oleh lembaga atau perusahaan yang mengelola hutan.
Ada dua perusahaan swasta yang mendapat Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) selama 60 tahun dari Kementerian Kehutanan, yang mengikuti skema VCS, yaitu PT Rimba Makmur Utama (RMU) dengan luas 157.000 hektare di Kabupaten Katingan dan Kotawaringin Timur (Kalimantan Tengah), dan PT Rimba Raya Conservation seluas 64.000 hektare di Kabupaten Seruyan (Kalimantan Tengah).
PT RMU mengaku mengeluarkan dana puluhan miliaran rupiah untuk proyek restorasi dan konservasi lahan gambut di 34 desa. Mereka membidik perusahaan raksasa seperti Google, Microsoft, Disney, yang ingin menurunkan emisinya untuk membeli cadangan karbon di proyek RMU.
Pembeli cadangan karbon PT Rimba Raya Conservation adalah Gazprom (perusahaan penghasil minyak terbesar asal Rusia), The Clinton Climate Initiatives, Allianz dan Microsoft. Gazprom setuju membeli dengan harga US$ 10-11,4 per ton karbon dioksida. Total jumlah karbon yang diterbitkan sebesar 3.527.171 ton setara CO2.
Pemerintah Indonesia dan pemerintah Jerman juga bekerja sama di enam wilayah demonstration activities program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+). Proyek Forest and Climate Change Programme (Forclime) ini dimulai sejak 2010 dan berlangsung di Kabupaten Kapuas Hulu (Kalimantan Barat), Kabupaten Berau (Kalimantan Timur) dan Kabupaten Malinau (Kalimantan Utara).
Ada 78 desa yang terlibat dan memiliki target menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) 300.000-400.000 ton setara CO2 dibandingkan emisi gas rumah kaca tanpa ada intervensi program Forclime. Sebanyak 80% dari kegiatan percontohan REDD bakal berdampak sosial ekonomi yang positif pada program dan kelompok sasaran.
Menurut Rudi Syaf, pembelian cadangan karbon lewat pasar karbon sukarela merupakan bonus bagi kelompok perhutanan sosial di Indonesia. Hasil penjualan cadangan karbon yang mereka terima hanya ratusan juta rupiah. Berbeda dengan perusahaan swasta yang mengantongi IUPHHK-RE dan menerima dana miliaran rupiah dari korporasi internasional.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menjelaskan hutan Indonesia memiliki peran sebagai katalis dalam pelaksanaan Kesepakatan Paris (Paris Agreement) dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Peran berikutnya adalah menjadi lokomotif dalam pencapaian Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional (Nationally Determined Contribution/NDC), menurunkan emisi gas rumah kaca secara nasional dan mendukung aktivitas yang memiliki dampak netral terhadap iklim global.
NDC Indonesia menetapkan target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29% tanpa syarat (dengan usaha sendiri) dan 41% dengan dukungan internasional yang memadai pada 2030. Target NDC itu dapat tercapai melalui penurunan emisi GRK sebanyak 17,2% pada sektor kehutanan, 11% pada sektor energi, 0,32% pada sektor pertanian, 0,10% pada sektor industri, dan 0,38% pada sektor limbah.
Artikel 5 Kesepakatan Paris memuat upaya penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta mekanisme insentif berbasis hasil yang diakui oleh dunia internasional. Siti Nurbaya menyatakan bahwa strategi kehutanan Indonesia dalam adaptasi terhadap perubahan iklim dilaksanakan melalui pencegahan deforestasi dan degradasi hutan, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) terpadu, peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya alam, konservasi dan restorasi ekosistem, serta perlindungan kawasan pantai.
“Contoh yang komprehensif atas peran hutan di tingkat tapak dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dapat dilihat dalam program perhutanan sosial,” ujar Siti Nurbaya.
Sampai 11 Juni 2019, pemerintah memberikan akses lahan seluas 3,096 juta hektare kepada warga sekitar hutan, termasuk masyarakat adat. Mereka memiliki peran dalam pengelolaan hutan lestari, konservasi keanekaragaman hayati, peningkatan kesempatan berusaha, dan pencegahan konflik tenurial.
Walhasil, perhutanan sosial dapat mencegah terjadinya deforestasi dan degradasi hutan. Program ini menyasar pada 25.000 desa di dalam dan sekitar hutan, serta mencakup sekitar 10 juta masyarakat miskin. Perhutanan sosial juga membantu upaya pengentasan kemiskinan yang menjadi ruh program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Apa yang dilakukan kelompok-kelompok usaha perhutanan sosial dan pemegang izin restorasi ekosistem, merupakan bagian dari mitigasi perubahan iklim melalui program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+).
Buku ini memaparkan praktik baik dari beberapa kelompok masyarakat di sekitar hutan, baik yang melalui program perhutanan sosial (mendapat izin dari KLHK melalui skema hutan desa, hutan kemasyarakatan dan hutan adat) atau yang bukan, untuk mendukung pencapaian NDC.
Cuplikan Bab I buku Praktik Terbaik Perhutanan Sosial dalam Menjaga Iklim Bumi. Silakan mengunduh seluruh isi buku di tautan ini.
BERSAMA MELESTARIKAN BUMI
Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.
Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.
Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.

Wartawan, anggota Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ)
Topik :