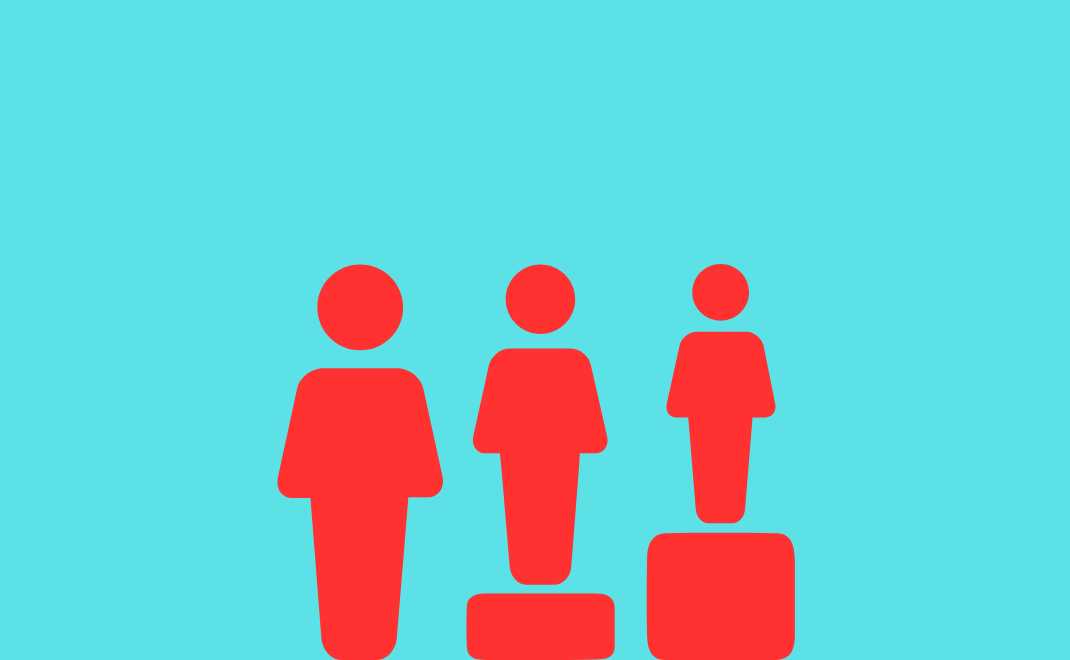
FAKTA bahwa 35 juta hektare hutan produksi—lebih dari separuh luas hutan produksi secara nasional—tidak lagi memiliki kriteria sebagai hutan, seharusnya memberi pelajaran signifikan dalam membuat kebijakan kehutanan. Terutama kenyataan bahwa beberapa pengaturan kelestarian hutan oleh negara terbukti tidak berjalan mulus.
Para sarjana kehutanan mengerti bahwa agar hutan lestari, luas hutan alam produksi atau hutan tanaman untuk dimanfaatkan kayunya dibatasi sesuai dengan kemampuan tumbuh dan regenerasinya. Logikanya sederhana: dengan menebang sesuai kemampuan tumbuh itu volume pohon yang ditebang akan sama dengan volume yang tumbuh dan akan tersedia pada waktu menebang berikutnya.
Dalam suatu usaha komersial dengan modal serta risiko, mendapat keuntungan juga berarti harus mengembalikan modal. Maka usaha komersial itu layak secara finansial sekaligus layak secara ekologi apabila produksi secara fisik dibatasi sejumlah kemampuan tumbuh hutan itu. Karena itu biaya juga akan terbatasi oleh kemampuan hutan dalam mengembalikan biaya itu kepada pemiliknya.
Masalahnya, apabila biaya itu naik karena pos-pos yang tak terencanakan—misalnya suap untuk mendapatkan izin, pengesahan perencana, serta biaya-biaya lain di luar ongkos produksi—produksi harus dinaikkan agar menutup seluruh biaya itu. Di sini moral hazard terjadi. Kenaikan produksi usaha kehutanan akan tinggi meski pos-pos “tak terduga” itu tak dilaporkan secara resmi.
Menurut seorang pengusaha hutan alam, hutan produksi itu seperti barang semi-publik. Ia milik negara tapi pengelolanya diserahkan kepada pemegang izin. Praktiknya pengelolaan itu bisa “dicuri” oleh pengelolanya sendiri. Maka bila digeneralisasi, 35 juta hektare lebih hutan produksi yang tidak lestari itu juga akibat kompensasi biaya transaksi.
Hutan tanaman semula mendapat subsidi, kemudian insentif itu dihapus. Untuk itu jika pengusaha akan membangun konsesi secara mandiri, walaupun layak secara finansial, keuntungannya menjadi sangat terbatas akibat biaya-biaya tak terduga tadi. Sementara hutan tanaman yang terintegrasi dengan industri pulp dan kertas mungkin lebih menguntungkan. Kini industri ini memerlukan bahan baku 45 juta meter kubik per tahun.
Dalam praktiknya, kebijakan tertulis, seperti undang-undang, atau yang tidak tertulis seperti bagaimana melaksanakan aturan tertulis, bisa tidak sinkron. Karena itu dalam membuat kebijakan, para pembuatnya tak hanya harus berkonsentrasi pada isinya tapi mesti membayangkan bagaimana kelak aturan itu dijalankan.
Di instansi pemerintah ada unit kerja khusus yang tugasnya membuat, merevisi, atau membatalkan sebuah peraturan. Kadang ada juga yang terlibat dari luar pemerintahan. Mereka kemudian membentuk apa yang disebut dalam jurnal-jurnal sebagai “komunitas kebijakan”.
Dalam “Policy Communities” bab dalam “Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods” (2015), Hugh T. Miller dan Tansu Demir membedah apa itu dan bentuk-bentuk “komunitas kebijakan”:
Pertama, mereka punya jaringan isu dalam menekankan aspek-aspek yang dianggap penting dalam sebuah kebijakan. Komunitas ini mempunyai jaringan yang dapat berjalan mendahului perumusan kebijakan formal serta mempengaruhi penyusunan dan pelaksanaannya.
Dalam pemanfaatan hutan alam atau hutan tanaman di Indonesia, komunitas ini tampak diisi oleh kelompok atau asosiasi pengusaha. Kelompok ini cenderung tidak berasosiasi dengan kelompok lain yang mengisi kepentingan masyarakat lokal maupun masyarakat adat. Padahal, masyarakat lokal dan adat selalu berjuang memperoleh hak atas hutan dan tanah yang lokasinya tidak terbatas pada hutan produksi.
Pemanfaatan sumber daya alam yang masih terjerembap ke dalam persoalan hak atas tanah ini merugikan semuanya, selain berpotensi memunculkan konflik. Semua kelompok masih cenderung bersaing untuk mendapat hak masing-masing dan secara umum belum sampai pada upaya-upaya untuk mewujudkan tujuan bersama.
Kedua, kelompok kepentingan informal, bisa juga pelobi kebijakan. Mereka membuat kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu. Birokrasi pemerintah pun menjadi tidak netral posisinya antara publik dan para legislator. Kita baru tahu siapa sponsor sebuah kebijakan ketika ia sudah terimplementasi di lapangan.
Ketiga, sebuah komunitas kebijakan bermasalah apabila para pembuat aturan menggunakan politik untuk kepentingan mereka sendiri, dengan mengelabuhi prinsip kedaulatan rakyat. Biasanya, manipulasi ini terjadi dalam pembuatan kebijakan yang dilakukan secara tertutup. Celakanya, komunitas kebijakan itu merasa sudah mewakili aspirasi orang banyak.
Konglomerasi usaha di bidang kehutanan di Indonesia sejak 1970-an menunjukkan adanya “komunitas kebijakan” yang mengendalikan pengaturan investasi sumber daya alam itu. Dampak paling nyata yang ekornya masih terasa hingga kini adalah lambatnya pemanfaatan akses bagi masyarakat lokal dan adat akibat pola dan infrastruktur ekonomi yang terbangun cenderung untuk usaha besar daripada usaha masyarakat. Di sini, saya kira, pentingnya kebijakan pemanfaatan sumber daya alam yang hanya harus adil, juga memihak.
Miller dan Demir mencontohkan pemihakan itu dalam kebijakan pertanian di Amerika Serikat yang dibuat untuk menguatkan masuknya kepentingan petani ke dalam proses pembuatan kebijakan. Mereka mempertahankan peran lembaga petani, pelaksana lobi agribisnis, dan legislator yang mewakili distrik pertanian. Hubungan tripartit itu menunjukkan kepedulian dan pemihakan kepada kelompok rentan melalui desain kebijakan dan politik.
Di sini, pemihakan itu belum terlihat nyata. Menurut saya ini penyebab tata kelola pemerintahan yang baik dan pencegahan korupsi Indonesia masih rendah. Menurut Transparency International, pada 2022 indeks tata kelola pemerintah hanya 34 dari maksimum 90 dan minimum 16. Ada gap yang lebar antara laporan administrasi dengan kenyataannya di lapangan. Tata kelola yang baik, antara lain melalui pembuatan kebijakan yang fair, bisa mengecilkan jurang itu.
Ikuti pembahasan tentang tata kelola dan kebijakan kehutanan di tautan ini
BERSAMA MELESTARIKAN BUMI
Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.
Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.
Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.

Guru Besar Kebijakan Kehutanan pada Fakultas Kehutanan dan Lingkungan serta fellow pada Center for Transdiciplinary and Sustainability Sciences, IPB.
Topik :

















