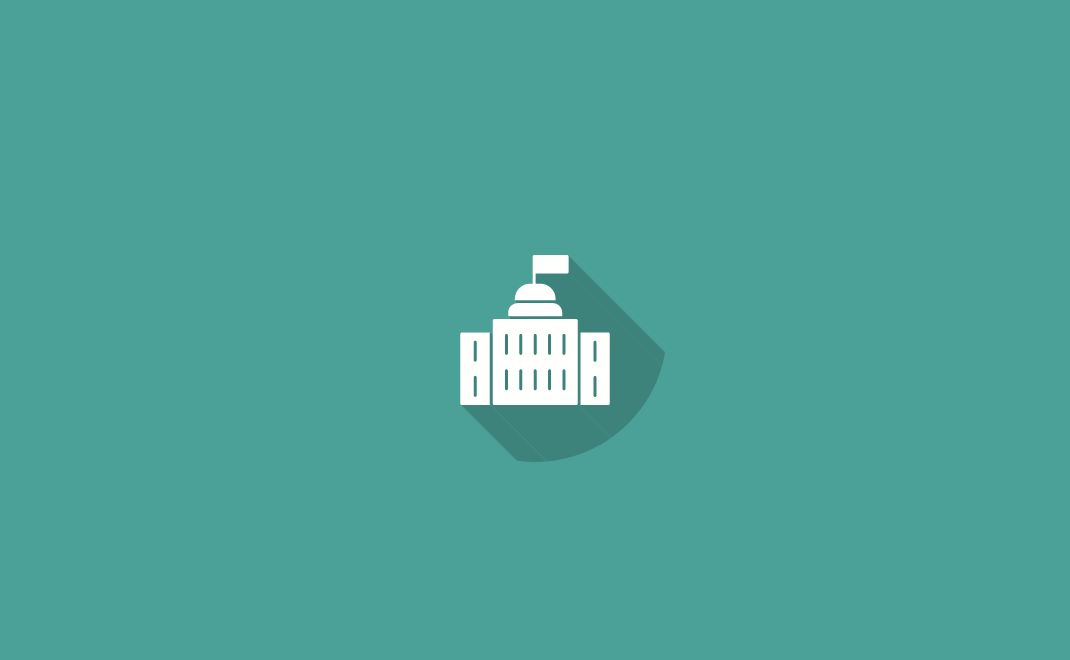
ADA diskusi menarik pekan lalu yang membahas hasil investigasi lokasi-lokasi usaha di dalam kawasan hutan yang izinnya telah dicabut. Juga evaluasi program perhutanan sosial dan instrumen fiskal berbasis ekologi, yang akan berujung pada sorotan terhadap problem kelembagaan atau krisis institusional.
Diskusi tema pertama soal investigasi lokasi usaha di kawasan hutan dilakukan oleh Jikalahari dan Walhi. Dua LSM ini melacak 23 perusahaan di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah.
Hasilnya meski izin mereka sudah dicabut ada beberapa perusahaan yang masih memakai area kerja mereka untuk operasi. Ada juga area kerja yang sudah dicabut itu berganti usaha menjadi perkebunan kelapa sawit, pertambangan, atau pemanfaatan hutan oleh masyarakat di sekitar konsesi.
Menurut temuan Jikalahari dan Walhi, lokasi-lokasi konsesi yang dicabut izinnya sebagian besar perlu dipulihkan karena terdegradasi.
Jikalahari dan Walhi merekomendasikan agar lahan-lahan yang izin pemanfaatannya sudah dicabut harus dialokasikan untuk masyarakat adat. Mereka mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 1/2022 tentang satuan tugas penataan penggunaan lahan dan penataan investasi yang memang mengamanatkan seperti itu.
Rekomendasi lain kepada pemerintah adalah menjalankan kebijakan ekonomi berkelanjutan (sustainable finance), agar semua lembaga keuangan ikut bertanggung jawab ketika uang yang dipinjamkan digunakan untuk investasi yang merusak lingkungan dan memantik konflik sosial.
Di tempat terpisah, The Asia Foundation bersama mitra-mitranya mengulas praktik baik dalam pelaksanaan perhutanan sosial dan instrumen fiskal berbasis ekologi di beberapa kabupaten. Ada kesimpulan umum bahwa berbagai inisiatif itu bertumpu pada kekuatan jaringan antara kelompok pelaku perhutanan sosial, kelompok masyarakat sipil, serta pemerintah pusat dan daerah, maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Instrumen fiskal berbasis ekologi atau disebut Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Kinerja ekologis (TAKE), yang diselenggarakan untuk tingkat desa dengan menggunakan alokasi dana desa (ADD), rupanya juga terpengaruh oleh jaringan-jaringan aktor tersebut.
Sebagaimana dilaporkan JARI Indonesia, pada 2022 ada ADD Rp 75,9 miliar untuk Kabupaten Kubu Raya di Kalimantan Barat. Dana tersebut disalurkan untuk 20 desa penerima TAKE 2022 yang anggarannya dipakai untuk mengelola sumber daya alam berbasis ekologis sebesar 45%, pengelolaan badan usaha milik desa 10%, pembangunan responsif gender 15% dan tata kelola keuangan desa 30%.
Pada tahun sebelumnya, alokasi untuk pengelolaan sumber daya alam berbasis ekologi berupa pembiayaan pengurusan izin perhutanan sosial dan pengelolaan sampah.
Wakil Kementerian Dalam Negeri mengatakan bahwa kriteria berbasis ekologi, kemandirian desa, dan gender itu sangat baik dan perlu penguatan kelembagaan. Juga perlu peningkatan ketersediaan fiskal melalui dana alokasi umum (DAU), maupun peningkatan keberadaan data untuk indikator lingkungan hidup.
Selain itu, ADD dan TAKE memerlukan sinergi perencanaan di kabupaten dan desa, selain peraturan yang melindunginya, serta pengembangan kepemimpinan yang mempunyai basis lingkungan (green leadership).
Walaupun beberapa topik yang telah ditelaah itu berbeda-beda dan lokasinya tersebar di berbagai provinsi, antar topik punya hubungan fungsional yang saling mendukung.
Pencabutan izin menghasilkan ruang baru. Bila ruang ini dimanfaatkan untuk memulihkan ketidakadilan alokasi pemanfaatan sumber daya alam, persetujuan perhutanan sosial perlu menjadi prioritas dalam ruang itu. Bila masalah yang dihadapi berupa rendahnya kapasitas menjalankan perhutanan sosial, salah satu alternatif solusinya adalah adopsi program TAKE.
Semua solusi itu bisa berjalan—walaupun terpisah satu sama lain—jika ditopang kepemimpinan yang mampu mengatasi persoalan dalam keputusan dan kebijakan. Kita tahu pencabutan izin pemanfaatan konsesi hutan, perhutanan sosial, maupun program TAKE berjalan bukan tanpa masalah. Ada pelbagai kepentingan yang berkelindan di sana.
Bagaimana mengintegrasikan berbagai program itu agar bisa dilakukan di tempat yang sama, dalam kapasitas dan waktu yang sesuai dengan hasil yang diinginkan? Apakah itu berarti harus dapat menyatukan langkah para pemimpin itu? Mengapa dalam Keputusan Presiden Nomor 1/2022 tidak menyertakan lembaga negara lain yang terkait dengan urusan dalam negeri dan urusan keuangan?
Dalam “Sustainability through institutional failure and decline? Archetypes of productive pathways”, di jurnal Ecology and Society 2019, Newig, dkk memberikan pembahasan atas tiga pertanyaan tersebut. Penjelasannya seperti ini:
Pertama, setiap pemerintahan selalu terikat oleh institusi—berupa norma dan peraturan tertulis maupun tidak tertulis—yang menentukan pola perilaku yang stabil, bernilai, dan berulang, dengan fungsi terpenting untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Karena institusi memandu dan membatasi tindakan, perubahan institusi merupakan ranah penting transformasi keberlanjutan.
Kedua, institusi bisa diperlakukan sebagai “rezim” yang mengakui interaksi antara peraturan dan aktor yang, melalui praktik mereka, selalu menstabilkan dan mereproduksi institusi yang menentukan pola perilakunya. Rezim institusional ini merupakan sistem adaptif kompleks yang mampu belajar dan beradaptasi terhadap keadaan yang berubah, sambil mempertahankan identitas dan selalu mereproduksi diri sendiri. Dengan demikian, berorientasi pada stabilitas.
Ketiga, institusi mampu merespons tekanan melalui pembelajaran, adaptasi dan reorganisasi, bahkan meningkatkan fungsi sistem utama: struktur dan fungsi. Krisis berpotensi memicu respons menuju keberlanjutan, jika krisis adalah “periode ketidakteraturan” dalam perkembangan sistem yang tampaknya “normal”. Krisis kelembagaan bisa terjadi akibat kegagalan internal, misalnya, oleh kekakuan organisasi dan pemimpin secara berlebihan.
Dengan memperhatikan ketiga hal itu, sifat keputusan presiden cenderung tidak pernah cukup menghasilkan sinergi antar lembaga negara, apabila persoalan yang mereka hadapi berupa persoalan institusional. Maka apa yang menjadi solusi-solusi pemanfaatan sumber daya alam yang sedang berjalan saat ini hanya dapat ditopang oleh kepemimpinan yang secara parsial dapat berkomunikasi dan berjejaring.
Jejaring itu tak terbentuk oleh kekuatan institusional. Soalnya, apabila komunikasi dan jaringan itu tidak bisa dipertahankan, prestasi yang telah dicapai oleh masing-masing bidang cenderung tidak akan bisa bertahan. Akibatnya, program tidak akan berkelanjutan.
Dengan kata lain, kita kini sedang menghadapi krisis institusional. Dalam kondisi begitu, solusi melalui perintah koordinasi tidak akan menjadi solusi berkelanjutan. Studi Jikalahari dan Walhi serta The Asia Foundation telah menunjukkannya.
Ikuti perkembangan terbaru soal krisis institusional di tautan ini
BERSAMA MELESTARIKAN BUMI
Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.
Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.
Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.

Guru Besar Kebijakan Kehutanan pada Fakultas Kehutanan dan Lingkungan serta fellow pada Center for Transdiciplinary and Sustainability Sciences, IPB.
Topik :
















